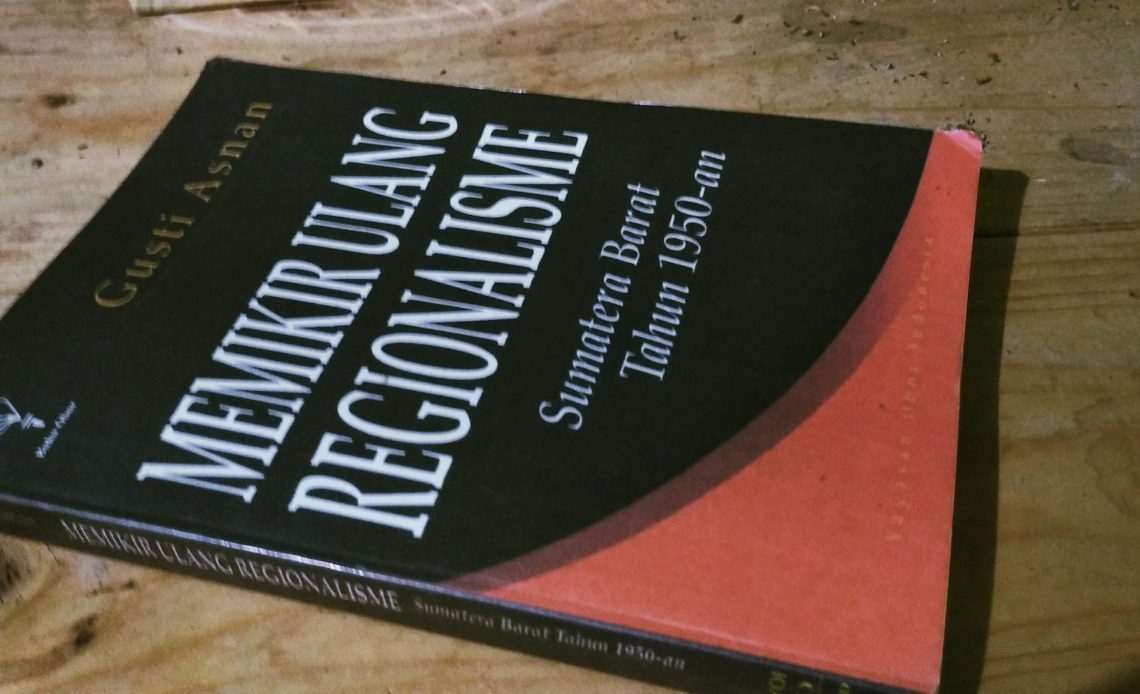
Judul Buku: Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat 1950-an
Penulis: Gusti Asnan
Penerbit: Yayasan Obor Indonesia-Jakarta, 2007
Tebal: xxvi + 263
ISBN: 978-979-461-640-6
Dalam ulasan buku Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an karya Gusti Asnan sebelumnya, saya hanya menekankan pembahasan pada salah satu fenomena yang muncul dalam masyarakat Sumatera Barat pada paruh pertama dekade 1950-an. Ketika itu muncul upaya elit lokal dengan latar belakang etnis Minangkabau, untuk melakukan Minangkabauisasi Sumatera Tengah. Tapi, itu baru satu aspek yang penting untuk dibahas. Tahun 1950-an yang dibahas buku tersebut, jauh lebih kompleks dan mesti dilihat sebagai tahun-tahun yang penting dan menentukan wajah Sumatera Barat hari ini.
Tahun 1950-an adalah masa-masa penuh perubahan dalam sejarah Sumatera Barat. Tahun 1950-an ditandai dengan datangnya era baru dengan terbukanya kemungkinan demokratisasi. Revolusi yang bersamanya terkandung aspirasi demokratik, telah mengenyahkan atau setidaknya membuat tiarap feodalisme, baru saja melanda Sumatera termasuk Sumatera Barat. ‘Daulat Raja’ disingkirkan dan diganti dengan ‘Daulat Rakyat’. Di dalam era baru tersebut, masyarakat Sumatera Barat “memformulasikan identitas budaya (serta masyarakat) mereka di dalam negara bangsa yang baru saja terbentuk” (hal: xxi). Masa-masa tersebut dipenuhi kontradiksi-kontradiksi, gagasan-gagasan untuk mewujudkan suatu tatatan baru, serta penyesuaian-penyesuaian masyarakat Sumatera Barat terhadap kekuasan yang silih berganti yang pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana masyarakat Sumatera Barat memandang “identitas, imajinasi mereka tentang masyarakat, daerah dan negara bangsanya” (hal: xxiv).
Beberapa karakteristik utama masyarakat Sumatera Barat yang terus bertahan sampai hari ini, merupakan produk sejarah periode 1950-an tersebut. Penerimaan masyarakat Sumatera Barat atas kepemimpinan dan pemerintahan bergaya militer—suatu kecendrungan mental yang belum ada presedennya dalam sejarah Sumatera Barat, serta ‘pengerasan identitas’ sebagai warga daerah yang diiringi munculnya sentimen terhadap Jawa sebagai pusat, adalah beberapa contoh.
EMPAT KARAKTERISTIK BARU
Dalam buku ini, Gusti Asnan mengemukakan temuannya tentang empat karakteristik yang saling mempengaruhi. Keempat karekateristik tersebut baru muncul pada 1950-an dan tidak ditemukan pada masa-masa sebelumnya. Karakteristik pertama adalah adanya dua pola hubungan pusat daerah. Secara nasional, pusat dipahami sebagai Jakarta (Jawa) dan Provinsi (Sumatera Tengah) sebagai daerah (pinggiran). Sedangkan pada tingkat Provinsi, Bukittinggi (Sumatera Barat) dianggap sebagai pusat dan Riau serta Jambi sebagai daerah (pinggiran).
Pola hubungan tersebut menciptakan karakteristik kedua. Ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Di satu sisi, Sumatera Tengah sebagai daerah memiliki ketidakpuasan terhadap Jakarta (Jawa) sebagai pusat. sementara di sisi lain, sebagai daerah Riau dan Jambi juga merasa tidak puas atas dominasi Bukittinggi/Sumatera Barat [Minangkabau] sebagai pusat di Provinsi Sumatera Tengah.
Ketidakpuasan tersebut kemudian melahirkan karakteristik ketiga, yaitu gagasan tentang batas-batas wilayah. Di satu sisi, Sumatera Tengah, dengan Bukittinggi sebagai pusat, mencoba mendefinisikan wilayah administratif berdasarkan klaim kejayaan masa lalu Minangkabau. Sedang di sisi lain, demi melepaskan diri dari dominasi Bukittinggi, Riau dan Jambi juga melakukan hal yang sama—mencari klaim sejarah untuk membedakan diri dengan Bukittinggi dan pada saat bersaman membangun narasi historis untuk mempersatukan daerah masing-masing. Proses pendefinisian batas-batas daerah tersebut kemudian dicampuri oleh kepentingan Jakarta sebagai pusat. Jakarta, yang menginginkan stabilitas dan bermaksud mengembosi kekuatan PRRI sebagai pemberontakan daerah, berperan dalam ‘memerdekakan’ Riau dan Jambi.
Proses ‘negosiasi batas wilayah’ tersebut kemudian melahirkan elit-elit lokal dari masing-masing daerah. Elit-elit lokal yang muncul pada masa-masa tersebut berupaya mendefenisikan ulang pemaknaan atas wilayahnya masing-masing sekaligus mendefenisikan ulang gagasan daerah-pusat. Dalam kolom-kolom opini di koran lokal yang berpengaruh, Haluan, di mana para elit menyebarkan gagasannya, terjadi perubahan besar dalam cara para elit melihat dirinya sebagai bagian dari daerah (Sumatera Tengah). Inilah karakteristik keempat yang dimaksud Asnan. Keempat karakteristik yang muncul pada periode tersebut terus bertahan, ia “tetap terpola pada waktu-waktu berikutnya” (hal: xxi).
MUNCULNYA ELIT DAERAH
Secara implisit, Asnan menempatkan elit lokal sebagai salah satu faktor sejarah penting di Sumatera Tengah 1950-an. Akan tetapi, yang memainkan peranan paling penting pada masa-masa ini di Sumtera Tengah adalah para elit lokal Sumatera Barat dengan latar budaya Minangkabau. Mereka sangat dominan dalam banyak bidang. Para elit lokal itulah yang, terutama semenjak paro kedua 1950-an, menyiapkan penulisan sejarah dengan perspektif Minangkabau untuk para siswa di sekolah-sekolah Sumatera Tengah, menyiapkan bahasa Minangkabau sebagai bahasa wajib bagi para siswa tersebut, menyiapkan lembaga khusus untuk mengurusi kebudayaan Minangkabau, serta berupaya mendefenisikan ulang gagasan tentang kepahlawanan. Melalui peneribitan buku-buku biografi pahlawan daerah, para elit lokal berupaya menandingi biografi pahlawan nasioanal dari daerah seperti Imam Bonjol yang kental dengan citra ‘pahlawan nasional’ yang banyak diproduksi pada masa-masa sebelumnya. Dengan kata lain, para elit daerah memunculkan gagasan mengenai ‘pahlawan daerah’ untuk melegitimasi eksistensinya.
Namun dominasi elit Bukittinggi ditentang oleh elit-elit lokal dari pinggiran (Jambi dan Riau). Mereka melakukan rangkaian pertemuan untuk merumuskan tuntutan otonomi bagi Riau dan Jambi guna melepaskan diri dari dominasi Bukittinggi. Perjuangan elit-leit lokal Riau dan Jambi tersebut “di samping dilakukan di Riau dan Jambi sendiri […] juga dilaksanakan di Sumatera Barat dan Jakarta. Namun, hingga munculnya gerakan daerah (aksi Dewan Banteng dan PRRI), perjuangan tersebut selalu kandas” (hal: 219). Perjuangan elit lokal Riau dan Jambi untuk mewujudkan daerah otonomi setingkat Provinsi baru berhasil setelah mereka menjalin kontak dengan elit Jakarta yang berkepentingan mengucilkan Sumatera Barat sebagai basis PRRI dengan sumber daya ekonominya di Riau dan Jambi. Asnan menyebut manuver tersebut sebagai Jakarta strategi untuk “‘mematikan’ gerak langkah Dewan Banteng di Riau dan Jambi yang merupakan sumber pendapatan (ekonomi) utama bagi Sumatera Tengah” (hal: 234).
TRANSFORMASI YANG MENENTUKAN WAJAH SUMATERA BARAT
Dalam buku ini, Asnan membagi “Tahun 1950-an” menjadi beberapa kurun waktu. Kurun pertama (1950-1956), kurun kedua (1956-1958) dan kemudian masa PRRI. Dengan pembagian seperti ini, nampaknya Asnan mencoba memperlihatkan gambaran umum Sumatera Barat sebelum dan sesudah pemilu 1955 serta munculnya Gerakan Daerah (Dewan Banteng) pada 1958. Dalam tiap-tiap kurun terjadi perubahan-perubahan penting di Sumatera Barat.
Pada kurun 1956-1956 terjadi perubahan dalam cara masyarakat Sumatera Barat dalam memandang identitas serta imajinasi tentang daerah dan negara bangsa. Hal tersebut nampak dari pergeseran wacana yang dilemparkan para elit lokal. Opini para elit yang pada masa-masa awal 1950-an lebih bercorak international minded dan national minded, bertransformasi menjadi daerah-sentris memasuki paro kedua 1950-an. Sejak 1952, berita-berita serta opini yang diterbitkan Haluan tidak lagi berorientasi Internasional serta nasional “sebagai gantinya muncullah berita-berita tentang persoalan daerah” serta berkurangnya secara drastis opini yang berisi “resolusi bagi upaya pemantapan NKRI, bahkan sebaliknya mulai muncul suara-suara pembentukan negara federal” (hal: 124). Pada saat yang bersamaan, Sumatera Barat, melalui politik bahasa, politik penulisan sejarah, serta mata pelajaran geografi yang digagas para elitnya, mencoba memantapkan posisi sebagai Pusat bagi Sumatera Tengah.
Kurun waktu setelahnya (1956-1958), ditandai oleh perubahan-perubahan yang tak kalah penting dan menentukan. Pada tahun pertama pasca pemilu 1955, gagasan mengenai otonomi daerah yang pada dasarnya mengandung semangat demokratik, mulai dilempar ke publik oleh para elit politik lokal dari kalangan sipil. Namun gagasan dengan semangat demokratik ini bertransformasi menjadi gagasan yang bercorak otoritarian dan militeristik setelah elit lokal dari golongan tentara ikut ambil bagian dalam masalah sipil ini “dengan melibatkan diri secara langsung dalam gerakan daerah yang pada mulanya dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan otonomi daerah, desentralisasi pemerintahan, serta menumbuhkan kehidupan demokrasi yang lebih demokratis” (hal: 144-145). Dengan kata lain, gerakan daerah yang awalnya berwatak demokratis bertransfomasi menjadi gerakan daerah dengan watak otoriter dan militeristik.
Seiring dengan masuknya tentara ke dalam gelanggang gerakan daerah yang secara formal ditandai dengan pengambilalihan pemerintahan sipil oleh Dewan Banteng yang militeristik, berbagai bentuk organisasi civil society yang muncul pada paro pertama 1950-an dengan mengusung semangat demokrasi ikut bertransformasi. Beberapa organisasi sipil yang pada awal 1950-an menunjukkan wajah demokratik dan nasionalisnya, menyesuaikan diri dengan gerakan daerah yang telah didominasi oleh para perwira daerah. Mereka memberi dukungan, bersyarat ataupun tidak, kepada Dewan Banteng pada masa-masa awal terbentuknya Dewan Banteng. Meski dalam perjalanannya partai politik seperti Perti menarik dukungan, akan tetapi secara umum organisasi sipil lainnya pada masa-masa 1956-1958 ini telah bertransformasi menjadi lebih militeristis dan tersentralisasi dalam soal ideologi politik. Tidak ada lagi keberagam orientasi politik. Yang ada hanya dikotomi politik pro-pusat dan pro-PRRI. Dengan kata lain, upaya demokratisasi yang pernah muncul di Sumatera Barat pada awal 1950-an telah gagal dan Sumatera Barat terjatuh pada militerisme di bawah Dewan Banteng.
Setelah berakhirnya PRRI, dan kemudian Demokrasi Terpimpin yang singkat tapi merestui pendekatan militer untuk menyelesaikan persoalan PRRI itu, Sumatera Barat di era Orde Baru telah menjelma menjadi “Sumatera Barat baru” yang berbeda dengan Sumatera Barat sebelum PRRI. Sikap represif serta cara-cara militeristik yang diterapkan oleh Jakarta untuk ‘membebaskan’ Sumatera Barat dari PRRI, telah membuat masyarakat melakukan penyesuaian dengan kondisi tersebut.
Kondisi-kondisi tersebut akhirnya mempersiapkan masyarakat Sumatera Barat untuk menyesuaikan diri dengan cepat begitu kekuasaan militeristik Orde Baru datang. Penyesuaian yang cepat itu, merupakan kombinasi dari pengalaman historis masyarakat Sumatera Barat. Pengalaman di bawah Dewan Banteng dan kemudian PRRI di mana militersime demikian dominan, serta pendekatan militeristik pemerintah pusat pasca-PRRI telah membuat masyarakat Sumatera Barat dengan cepat menyesuaikan diri begitu rezim militeristik Orde Baru datang. Militerisme yang semakin kuat pada masa pasca-PRRI adalah ekses tak terduga dari gerakan daerah. “Demokratisasi pemerintahan yang diinginkan oleh para pencetus dan para pemberontak PRRI ternyata menghasilkan pemerintahan daerah yang otoriter (militeristik). Militer menjadi sangat berkuasa di daerah ini” (Hal: 241). (*)


