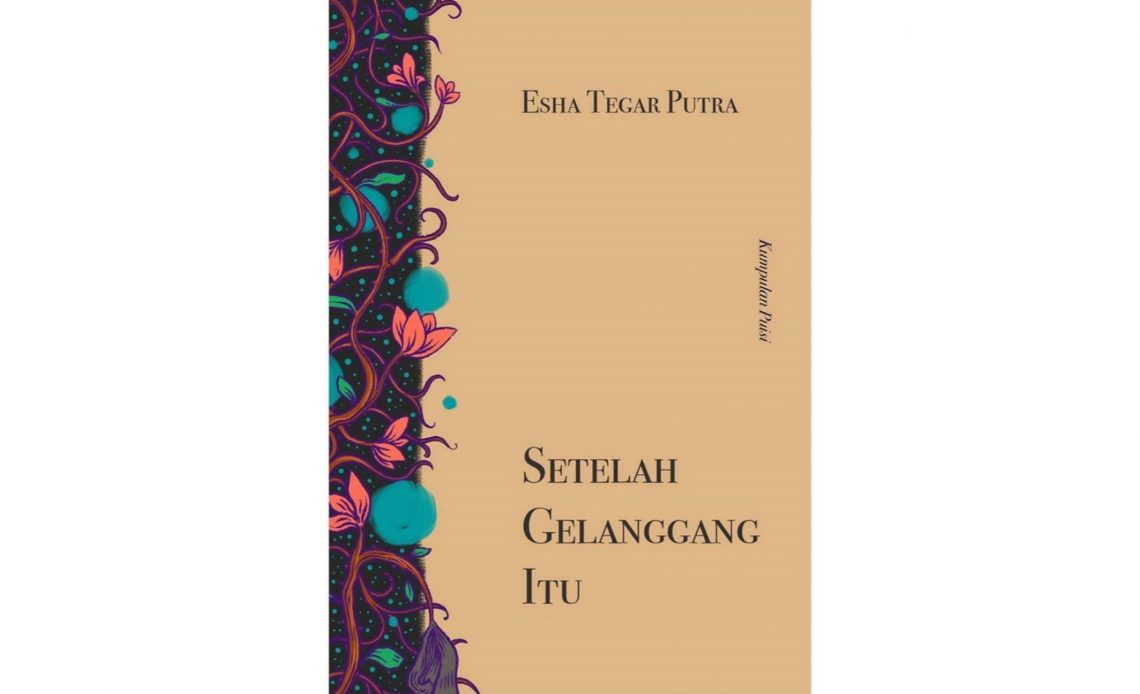
Membaca Setelah Gelanggang Itu bukan sebuah perkara mudah. Sebabnya, Esha Tegar Putra menuntut kita untuk masuk ke dalam sebuah ‘gelanggang’ yang sudah beberapa kali terlompati oleh beberapa variabel.
Variabel pertama, dalam kasus saya, adalah geografi. Sebagai pembaca yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan tanah Minang, apalah yang saya tahu tentang kisah Cindua Mato, tanpa bantuan rujukan, yang membingkai bagian pertama dari buku Setelah Gelanggang Itu? Kemudian, variabel kedua mungkin adalah waktu. Beberapa ahli, yang tentunya karena mereka ahli, lebih paham dari saya mengenai asal muasal kisah Cindua Mato, mengatakan bahwa kisah ini kemungkinan bermula pada abad ke-16 atau pada abad-abad selanjutnya sampai abad ke-19. Intinya, bagi saya, dan saya perkirakan bagi pembaca lain yang bukan berasal dari Sumatera Barat, kisah tersebut terlalu jauh dan lampau.
Variabel waktu juga memiliki turunannya sendiri, yaitu kemajuan zaman. Di zaman sekarang ini, rasanya orang lebih tahu drama Korea daripada sebuah kisah rakyat. Ini akhirnya menjadi variabel lain yang menghalangi kenikmatan membaca kumpulan puisi Setelah Gelanggang Itu.
Meskipun begitu, Setelah Gelanggang Itu adalah sebuah karya epos. Karya epos yang untuk membacanya kita butuh bingkai pemahaman tertentu. Sebagian dari karya ini membuat alusi kepada Kaba Cindua Mato, sebuah kisah rakyat dari tanah Minang yang mengisahkan keseimbangan dan keselarasan.
Dalam bahasa Minang, kaba berarti kabar atau berita. Kata kaba berasal dari bahasa Arab, achbar. Tradisi Minang terkadang menukar kata kaba dengan carito atau cerita dalam bahasa Indonesia. Kaba, dalam tradisi Minang, biasanya berkisah tentang tatanan masyarakat yang keberadaannya “diganggu oleh ‘penyamun’ kaba.” Itulah sebabnya, kaba tidak senantiasa berbicara mengenai adat dan berbagai turunannya. Namun, menurut Taufik Abdullah, Kaba Cindua Mato unik dalam bentuknya yang memadukan kaba dan tambo. Kaba pada awalnya merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang diceritakan oleh seorang tokoh perantau yang setelah membakar dupa dan membaca mantra akan menuturkan kaba dengan cara menyanyikannya, diiringi oleh permainan rebab.
Mengulang kisah Cindua Mato ke dalam tulisan ini hanya akan berfungsi untuk memanjang-manjangkan tulisan dan justru kontra terhadap kecenderungan inter-tekstual yang menjadi latar buku kumpulan puisi Setelah Gelanggang Itu. Maka dari itu, tulisan ini hanya akan memberikan catatan pendamping dan menggarisbawahi hal-hal penting yang berkaitan dengan buku kumpulan puisi Esha Tegar Putra, terutama pada bagian pertamanya. Buku kumpulan puisi ini terbagi ke dalam empat bagian, yaitu: Membuka Kitab, Ratap Mahali, Belakang Pintu dan Sebuah Hikayat.
Adat, Alur dan Kepantasan
Disebutkan bahwa pada awalnya Kaba Cindua Mato adalah sebuah kisah yang disebarkan secara lisan. Akan tetapi, pada akhirnya Kaba Cindua Mato dialihwahanakan menjadi sebuah buku, atau kitab dalam istilah Esha. Untuk mencerap isi sebuah kitab, kita pertama-tama harus membukanya atau kalau mau lebih jauh lagi, kita harus memiliki akses terhadapnya, baik itu dengan cara meminjamnya atau membelinya. Itulah yang disarankan oleh Esha, agar kita membuka kitab tersebut. Tetapi, bagi Esha sang perantau, kitab tersebut sudah menubuh ke dalam setiap jengkal badannya.
Hal ini dibuktikan dengan puisi pertama yang berjudul Setelah Membuka Kitab. Di dalamnya terdapat semacam doa atau mantra yang dibacakan oleh Esha sang perantau agar arwah penutur dapat turun dan menguasai sekujur tubuhnya dan mulai menceritakan kisah epos tersebut:
Kemari ingatan,
ke pangkal telingaku
ke ruas-ruas jariku
ke gelupas triplek pada pintu kamarku
tapi jangan berharap apa-apa lagi pada urat kudukku
tidak lagi ada denyut
tidak lagi membikin segala macam ketakutan susut.
Citra seorang perantau, yang pengetahuan tentang kisah Cindua Mato sudah menubuh dalam dirinya itu, diberikan latar yang bisa dipahami sebagai suasana modern. Simak bagian ketika Esha sang perantau menyatakan “Kecuali rumah tinggi / tegak dengan bagak di hadapanku / kota ini telah berkerut / dan bikin angin bergerak menggelambir.” Dan bagaimana dalam selimut kota modern sang perantau dapat mengingat kisah Cindua Mato dan dengan demikian menjadikan tubuhnya kitab itu sendiri. Ia berkata “dan selesai sudah kelam raya / hari telah hitam muda / sementara kitab itu tersebut terjaga / di dalamnya kalian berjaga.”
Penggunaan kata perantau di sini juga menjadi penting karena dalam ‘gelanggang’ kehidupan masyarakat Sumatera Barat, hanya terdapat dua pembagian, pertama adalah luhak yang berarti dataran tinggi dan rantau yang artinya adalah bantaran sungai. Luhak diyakini sebagai tempat hunian penduduk asal Minangkabau yang pada awalnya berada di dataran tinggi. Sedangkan rantau adalah daerah menetapnya para migran yang turun dari gunung dan biasanya menempati daerah pinggir sungai serta daerah pesisir. Luhak dan rantau meskipun terpisah tetap merupakan bagian dari Minangkabau.
Dengan pandangan terhadap ‘rantau’ ini, barangkali masyarakat Minangkabau merasa bahwa dimanapun mereka berpijak, itulah tanah Minangkabau. Hubungan antara alam atau ‘gelanggang’ dan keterasingan darah Minangkabau menjadi salah satu motif besar yang bisa kita serap dari keseluruhan kumpulan puisi Esha.
Puisi pertama yang dikisahkan oleh Esha sang perantau adalah Cindua Mato Kepada Lenggogeni, sebuah monolog Cindua Mato untuk kekasihnya. Dalam kisahnya, Cindua Mato adalah seorang tangan kanan (atau saudara?) dari Dang Tuanku, putra dari Bunda Kanduang. Ia dijodohkan dengan Lenggogeni, seorang putri bendahara yang ketika itu sedang mengadakan sabung ayam di gelanggangnya (sabung ayam untuk menjodohkan putrinya atau sabung ayam karena memang masyarakat Minang gemar menyabung ayam, sehingga bukan spesifik untuk menikahi putrinya?).
Dalam masyarakat Minang, sebelum dilarang oleh kaum Padri, dalam setiap nagari terdapat gelanggang atau arena sabung ayam. Hal ini bisa kita kutip dari puisi Cindua Mato Kepada Lenggogeni yang berbunyi: “dan sebelum kokok pertama / taji ayam selesai sudah kuasah tajam.”
Akan tetapi, situasi tersebut kemudian disandingkan dengan keluhan Cindua Mato yang melihat “cuma ada bumbungan api / gelanggang gadang di mana seisi kampung / terbakar perlahan.” Penggunaan istilah ‘kampung’ dan bukan ‘nagari’ memperkuat dugaan bahwa Cindua Mato sudah tercabut dari akar Minangnya yang “terbakar perlahan.”
Ia meratapi dirinya yang malang harus terjebak di antara kemalangan dan dialihkan menjadi “sebuah kitab berupa jalan nasib / akan dicatat dengan teramat rapi / kitab dari mulut ke mulut / kitab tanpa penting lagi diusut benar atau tidak kisahnya.” Bagian pertama dari kumpulan puisi ini, Membuka Kitab, bisa dibaca sebagai upaya Cindua Mato untuk mengisahkan perjalanan hidupnya dalam versinya sendiri. Semacam sebuah kisah alternatif, kontra dengan “kitab dari mulut ke mulut / kitab tanpa penting lagi diusut benar atau tidak kisahnya.”
Keluh kesah Cindua Mato pun bergema dalam ratapan Lenggogeni; kumpulan puisi dalam bagian pertama adalah gaung yang memantul maju-mundur dalam dunianya sendiri. Simak bagian “ketika tiga malam berturut-turut / murai memekik di tandan buah kelapa / dan bengkalai kain selesai kubakar / sudah jadi abu, sudah berupa debu” dalam Lenggogeni Kepada Cindua Mato. Kemudian kewajiban itu ditunaikan oleh Lenggogeni yang bisa kita cerap dalam Setelah Gelanggang Itu: “dan ketika suatu malam kau dengar / murai hitam memekik-mekik / di tandan buah kelapa / memekik tiga malam berturut-turut lamanya.” Baris-baris di atas menunjukkan bahwa Cindua Mato adalah seorang penutur yang berada di luar waktu, bergerak maju-mundur, sehingga mampu mengetahui kondisi mental dan tindakan Lenggogeni.
Setelah meramalkan nasibnya yang “akan dicatat dengan teramat rapi,” setelah Lenggogeni selesai membakar bengkalai kain dan mengguyur tubuhnya dengan gulai mendidih (kenapa gulai?), plot bergerak mundur (atau maju?) ke kisah Cindua Mato sebelum menuju gelanggang untuk meminang Lenggogeni dalam sajak Ke Gelanggang.
Cindua Mato dikisahkan dalam Setelah Gelanggang Itu “hilang dalam sebuah gelanggang / tapi tidak pada kitab itu.” Sedangkan dalam Kaba Cindua Mato, ia dipertemukan kembali dengan Lenggogeni setelah ia kembali ke Kerajaan Pagaruyung. Bahkan ia diangkat menjadi Raja Minangkabau, tidak lama setelah Dang Tuanku dan Bundo Kanduang pergi ke khayangan. Tetapi, tidak sebelum ia diminta untuk pergi meninggalkan Pagaruyung, dan Lenggogeni, agar kerajaan tersebut terhindar dari perang yang digencarkan oleh Imbang Jayo.
Imbang Jayo, dalam Kaba Cindua Mato, menyebarkan desas-desus bahwa Dang Tuanku terkena penyakit agar ia bisa menikahi Puti Bungsu, seorang putri yang seharusnya dinikahi oleh Dang Tuanku. Kabar ini membuat Bunda Kanduang murka.
Maka, diutuslah Cindua Mato untuk mengunjungi Sikalawi dengan membawa seekor kerbau sakti, Sibinuang, sebagai mahar pernikahan Dang Tuangku dengan Puti Bungsu (Mencari Puti Bungsu). Cindua Mato, yang baru saja ‘memenangkan’ Lenggogeni dalam sebuah gelanggang (Ke Gelanggang)—gelanggang tempat ia menghitung “berapa mata tergeriap / ketika kainmu tersibak / betis ubi dikubak / leher tiang ulin tegak membengkak”—terpaksa harus menuju gelanggang lain. “Aku akan pergi, Lenggo / gelanggang lain sudah menunggu” keluhnya dalam Setelah Gelanggang Itu. Padahal, Cindua Mato “serasa sudah di bibir tepi cawan / tuak belum direguk / tapi mabuk tertunaikan sudah” (Ke Gelanggang).
Berat hati, Cindua Mato mengemban tugas yang membikin dirinya terpaksa mengarungi gelanggang demi gelanggang dan dalam pengembaraannya ia melihat “dusun tersibak di balik kabut pagi / barangkali itu kota tersumbul seusai asap berhari-hari / lenguh seekor babi hutan diterkam anjing / pada bagian leher / gerung truk-truk tua pengangkut pasir / pada pendakian kesekian.” Sajak Mencari Puti Bungsu memperlihatkan bahwa Cindua Mato seakan sebuah roh yang terjebak di luar waktu dan meramalkan modernitas masyarakat yang tidak sepenuhnya selesai. Simak bagaimana ia mampu “melihat hari lalu / sekaligus hari depan saling bertaut / dusun dan kota seakan lempeng mata uang logam / bergasing.”
Dalam perjalanan, di bukit Tambun Tulang, Cindua Mato bertemu dengan hamparan tulang-belulang. Dikisahkan Cindua Mato kepada Lenggogeni dalam Di Bukit Tumbun Tulang, “tulang-belulang berserakan di sepanjang perjalanan.” Dengan mantra Cindua Mato bisa membuat kumpulan tulang tersebut “bicara padaku, Lenggo.” Tulang-belulang tersebut adalah korban penyamun yang dipekerjakan Imbang Jayo untuk memperkaya diri dan sekaligus memutus hubungan dengan Pagaruyung.
“Orang-orang samun/ hantu paling biadab dari Bukit Tambun Tulang / di atas punggung kuda ini aku duduk / sementara punggungku maut juga menumpang / duduk” dalam (Orang-Orang Samun) menjadi protagonis yang mengganggu alur (dalam bahasa Minang berarti kepantasan atau jalan yang benar). Tetapi, itu semua tidak menghalangi Cindua Mato untuk menerjang kemalangan dari gelanggang ke gelanggang. Itu terbukti dari sajak yang berbunyi, “tak ada samun tak ada hantu rimba raya / dapat menghampang jalan lapang ke gelanggang.”
Pada akhirnya (Di Akhir Kitab) Cindua Mato tiba. Ia berkata, “Aku sudah sampai, Lenggo / ke inti kitab petualangan orang-orang muda / telah aku buang jauh-jauh diri sendiri.” Sajak Di Akhir Kitab kembali menekankan bahwa, “Kecuali dalam kitab / yang disalin dari kisah mulut ke mulut / aku tidak akan lagi pernah ada.” Kaba Cindua Mato sebagai cerita rakyat hanya menjadi dongeng pengantar tidur ketika “orang-orang juga akan terus tertidur / bersama cerita dalam kitab.”
Tidak Ada Apapun di Luar Adat
Bagian pertama Setelah Gelanggang Itu, bisa dilihat sebagai sebuah ‘kitab’ alternatif. Sebuah kitab yang dikisahkan oleh pelaku dalam sudut pandang orang pertama, seperti yang sudah disimpulkan di muka. Cindua Mato, sang tokoh, merasuki Esha sang perantau dan menuturkan kisah yang menurut dirinya benar. Ada beberapa hal yang bisa dicatat dari kisah tersebut. Karena Kaba Cindua Mato bisa dikatakan sebagai sebuah kitab kanon dalam tradisi Minangkabau, maka, hal pertama yang bisa disimpulkan adalah Setelah Gelanggang Itu membuka wacana bahwa kanon bisa disangsikan. Terutama kanon yang disebar “dari mulut ke mulut / kitab tanpa penting lagi diusut benar atau tidak kisahnya.”
Kecenderungan ini seturut dengan gejala sastra pascamodern yang bermain dengan narasi alternatif untuk mengisi kekosongan yang dibuat oleh narasi kanon. Selain itu juga, Esha juga mengandalkan narasi inter-tekstual, semacam exergue yang berada di dalam sekaligus di luar teks. Artinya, pembaca yang tidak mengikuti Kaba Cindua Mato akan kesulitan untuk menikmati jalinan cerita yang dibentangkan oleh Esha.
Hal kedua adalah: Terjebak dalam gelanggang berarti terjebak di antara malang demi malang. Dalam sajak Cindua Mato Kepada Lenggogeni Cindua Mato berkata “kita memang akan terus bergerak / di antara malang demi malang.” Sebuah sajak yang akan menemukan gemanya di sajak Setelah Gelanggang Itu dalam baris yang berbunyi, “Aku akan pergi, Lenggo / Gelanggang lain sudah menunggu.” Kata ‘lain’ dalam sajak tersebut menekankan bahwa ia sebelumnya baru saja dari sebuah gelanggang, yang akhirnya membuat dirinya terhimpit antara gelanggang. Keadaan ‘antara’ gelanggang berarti keadaan di ‘antara’ kemalangan.
Sajak Orang-Orang Samun menyebutkan “tak ada samun tak ada hantu rimba raya / dapat menghampang jalan lapang ke gelanggang.” Jika alur kita pahami dalam bahasa Minang yang berarti adat atau kepantasan, maka, perjalanan dari gelanggang ke gelanggang adalah juga perjalanan adat atau kepantasan yang tidak akan bisa dihalangi oleh ‘penyamun’ yang mengganggu plot. Kemampuan menempatkan diri, atau tahu adat tidak bisa dihalang-halangi oleh penyamun sekalipun, karena pada akhirnya, dalam Kaba Cindua Mato, antagonis, mereka yang melawan adat, mendapatkan hukumannya.
Tetapi, Cindua Mato ingin membenarkan sejarah, memperbaiki alur. Ia ingin menguasai kitab “berupa jalan nasib” yang sudah dicatat “dengan teramat rapi.” Jika kitab berupa jalan nasib, maka, mengambil alih narasi adalah upaya untuk menguasai nasib. Menguasai nasib berarti bebas, melawan determinasi adat, sesuatu yang tidak mungkin dalam tradisi narasi Minang. Maka, Cindua Mato pada akhirnya membuang “jauh-jauh diri sendiri / aku gantung tinggi-tinggi tubuh sendiri” gerak yang mengesankan tindakan bunuh diri. Sesuatu hanya bisa terjadi melalui dan di dalam adat.
Cindua Mato, sosok pahlawan dalam Kaba Cindua Mato pada akhirnya menjadi protagonis, atau orang yang tidak tahu adat dalam Membuka Kitab, hilang ditelan oleh perbuatannya sendiri. Semestanya runtuh menimpa dirinya sendiri, sehingga dalam ceritanya sendiri ia dilupakan dan “menjadi kutukan / dilisankan lahir dari rahim tidak berbentuk / diceritakan hilang begitu saja tanpa kabar / tanpa pusara.”
Pemilihan kata gelanggang oleh Esha mau tidak mau mengingatkan kita akan Surat Kepercayaan Gelanggang. Manifesto itu disusun atas kepercayaan bahwa angkatan baru harus melepaskan diri dari angkatan sebelumnya. Mungkinkah ini bisa dibaca sebagai upaya untuk melawan status-quo? Rivai Apin, Asrul Sani dan Chairil Anwar, para sastrawan gelanggang, menulis buku Tiga Menguak Takdir. Melawan takdir, melawan kitab, melawan adat mungkinkah dengan demikian sastrawan selalu didera penyakit lambung, seperti yang dikesankan Esha dalam beberapa sajak dalam Setelah Gelanggang Itu?
Jika setiap angkatan/generasi bisa dibilang memiliki gelanggangnya sendiri, maka sastra adalah pergerakan antar gelanggang, dan dengan demikian sebuah perjalanan mengarungi kemalangan. Jika kita melihat arti gelanggang dalam bahasa Minang yang bermakna arena, khususnya arena sabung ayam, maka apakah sastrawan adalah atlet sabung yang sungguh malang, meratapi nasib “pada lambungku / segala masih tersisa ngilu”? (*)
Deskripsi Buku:
Judul buku: Setelah Gelanggang Itu
Penulis: Esha Tegar Putra
Jumlah halaman: 116
Penerbit: Grasindo (2020)
ISBN: 9786020522685
Catatan kaki :
1. Taufik Abdullah, “Some Notes on the Kaba Tjindua Mato: An Example of Minangkabau Traditional Literature,” Majalah Indonesia, vol. 9 (1970–04): 1–22.
2.Kata yang digunakan oleh Taufik Abdullah adalah villain atau penjahat. Saya di sini menggunakan penyamun untuk mengikuti bahasa yang digunakan oleh Esha Tegar Putra dalam buku Setelah Gelanggang Itu.
3. Ibid.
4. Jika kaba berurusan dengan tatanan sosial masyarakat, tambo sebaliknya justru menceritakan tradisi asal-usul alam Minangkabau yang ideal.
5. Saya membedakan antara Esha sang penyair dan Esha sang perantau yang kisahnya ditulis oleh Esha sang penyair.


