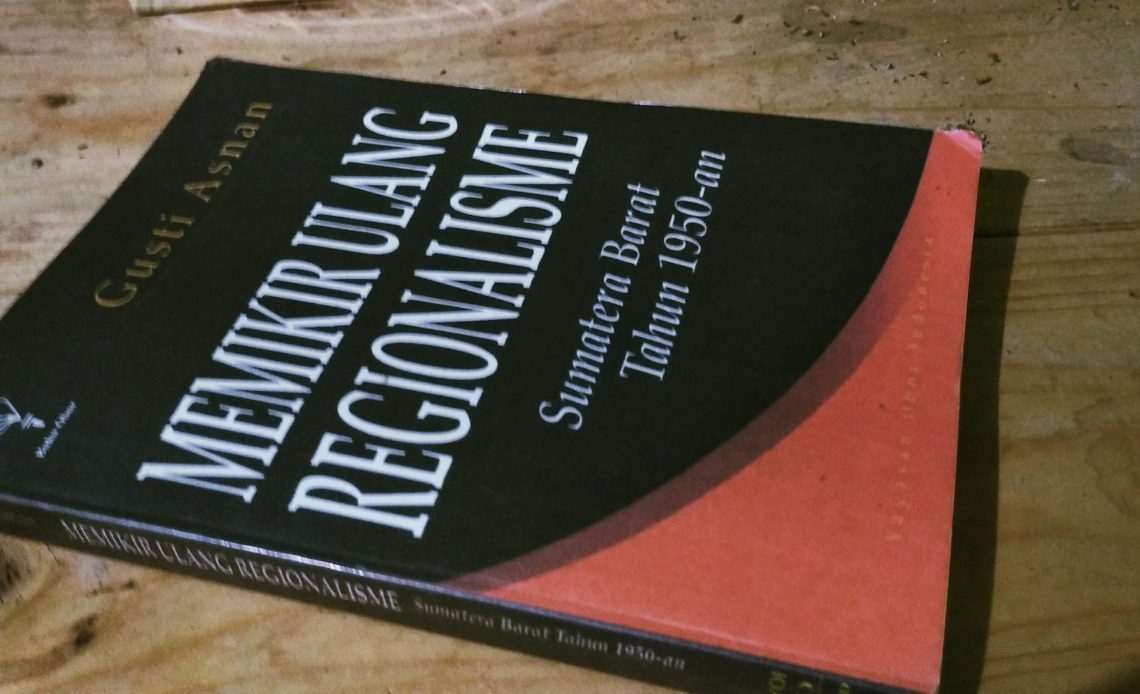
Apa yang kita ketahui mengenai Sumatera Barat periode 1950-an? Sebagian besar dari kita barangkali menjawab: PRRI. Jawaban tersebut disebabkan karena terbatasnya pengetahuan kita terhadap periode 1950-an yang mengakibatkan munculnya anggapan bahwa selain PRRI tidak ada peristiwa sejarah yang benar-benar penting di Sumatera Barat pada masa-masa tersebut.
Dalam penulisan sejarah mengenai Sumatera Barat, periode tersebut memang seringkali terabaikan. Dua karya sejarah tentang Sumatera Barat yang telah jadi klasik, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 (2005) atau buku Sumatera Barat di Panggung Sejarah (1995), misalnya, lebih banyak membahas PRRI dan terkesan meloncati periode 1950-an. Padahal, periode tersebut, menurut Gusti Asnan dalam Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an, merupakan “salah satu episode paling dinamis dalam perjalanan sejarah Sumatera Barat” (hal: xx). Buku karya Gusti Asnan inilah yang akan saya ulas kali ini.
Terabaikannya periode tersebut, dilihat Asnan sebagai akibat penulisan sejarah nasional yang didominasi oleh cara pandang Jakarta. Dalam cara pandang Jakartasentris itu (Baca: Sejarah Nasional Indonesia versi Orde Baru), periode tersebut dideskripsikan sebagai peridoe kegagalan demokrasi parlementer a la Barat yang penuh kegaduhan politik, berbanding terbalik dengan periode Orde Baru yang stabil dan aman. Dalam hubungannya dengan penulisan “sejarah daerah”, cara pandang sejarah Nasional versi Orde Baru yang melebih-lebihkan stabilitas pada masa Orde Baru, membuat narasi tentang sejarah daerah muncul sebagai kebalikannya[1]. Daerah kemudian ditampilkan sebagai “arogan, keras kepala, mengangkat isu povinsialisme” (hal: xviii).
Semua itu pada akhirnya menyebabkan semacam rabun dekat sejarah yang sampai taraf tertentu telah mendorong kebencian tak masuk akal terhadap pusat yang diasosiasikan dengan etnis tertentu. Penyakit rabun dekat tersebut pada gilirannya melahirkan narasi sejarah yang tak lebih dari sekedar pembalikan atas narasi sejarah pusatsentris: jika daerah dalam narasi sejarah pusatsentris dipersalahkan sedemikian rupa, maka dalam narasi ‘sejarah daerah’ ditulis kebalikannya. Apa saja hal buruk mengenai daerah yang ditulis pusat, serta merta dianggap kebohongan. Dan apa saja yang hal baik yang ditulis tentang pusat juga dianggap kebohongan belaka.
Sikap macam itu memang terkesan sebagai pembangkangan terhadap narasi besar sejarah Indonesia versi pusat, namun pada dasarnya ia tidak mengubah apa-apa. Karena yang menjadi aktor utama dalam narasi sejarah itu, tetaplah pusat walau dalam arti yang buruk. Namun tidak seperti sebagian sejarawan kampus serta sejarawan amatiran hari ini yang terjatuh dalam sentimen ‘pusat pasti salah, daerah pasti benar’ itu, Gusti Asnan memasuki periode tersebut dengan lebih objektif. Dalam buku ini, daerah ditampilkan bukan sebagai objek pasif yang bergerak hanya ketika menerima rangsangan dari pusat, melainkan subjek aktif yang punya inisiatif dan dinamikanya sendiri.
Asnan memulai bukunya dengan penelusuran terhadap asal-usul Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif jauh ke masa pemerintahan Kolonial Belanda. Di bagian ini, Asnan menunjukkan bahwa, sebagai produk sejarah, proses terbentuknya Provinsi Sumatera Barat yang kita kenal hari ini tak bisa lepas dari gejolak politik dan tarik menarik kepentingan antara Kolonial Belanda dan elit lokal. ‘Pembekalan’ awal mengenai politik geografi ini akan menjadi modal bagi pembaca untuk mengikuti topik-topik spesifik mengenai periode 50’an yang dibahas buku ini. Yaitu apa yang disebut Asnan sebagai “karakteristik” yang baru muncul pada periode tersebut.
Salah satu “karaktersistik” tersebut adalah gagasan mengenai batas-batas daerah. Gagasan tersebut kemudian dieksekusi oleh kelompok yang juga baru muncul pada periode tersebut: elit-elit lokal, yang tidak seutuhnya anti terhadap gagasan mengenai pusat[2] melainkan mencoba menempatkan diri sebagai pusat bagi ‘yang lain’. Hal tersebut nampak dari upaya mereka untuk “meluaskan pengertian dan cakupan Minangkabau” (hal: xxii). Dengan kata lain, pada masa-masa itu, segolongan elit tengah mendefenisikan ulang Minangkabau sesuai dengan wilayah administratif Provinsi Sumatera Tengah.
Upaya redefinisi itulah yang dapat kita sebut sebagai proyek Minangkabuisasi Sumatera Tengah pada masa-masa 50’an. Melalui penulisan sejarah, peta, serta politik bahasa, elit-elit lokal Minangkabau yang berpusat di Bukittinggi mencoba meyakinkan ‘saudara-saudara’ mereka di Riau dan Jambi bahwa wilayah geografis Sumatera Tengah adalah bagian dari ‘Alam Minangkabau’.
Tambo-tambo yang muncul pada 1950-an mulai menegaskan Sumatera Tengah sebagai bagian inheren dari wilayah kebudayaan Minangkabau. Di sana diceritakan tentang batas-batas geografis ‘Alam Minangkabau’ lengkap dengan petanya. Batas-batas tersebut mencakup wilayah adminitratif Sumatera Tengah yang “berbeda dengan tambo yang terbit pada 1930 yang hanya menyebut alam Minangkabu sampai ke Rokan, Kuantan dan Batanghari” (hal: 128). Artikel-artikel sejarah yang terbit di surat kabar pada periode 1950’an juga berupaya menegaskan bahwa sejarah Sumatera Barat (Baca: Minangkabau) “tidak terpisahkan dari sejarah Riau dan Jambi, serta [Bukittinggi/Darek] sebagai pusat dari Sumatera Tengah, terbit dalam jumlah yang relatif banyak dan dibesar-besarkan” (hal: 131).
Selain lewat politik penulisan sejarah dan peta, para elit lokal dengan latar budaya Minangkabau juga berupaya mendefinisikan wilayah administratif Sumatera Tengah sebagai ‘Alam Minangkabau’ melalui politik bahasa. Bahasa Minangkabau diusulkan untuk menjadi mata ujian tambahan untuk SMA di Sumatera Tengah. Selain itu bahasa Minangkabau juga diusulkan sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas pertama sekolah dasar. Walaupun upaya tersebut juga dapat dinilai sebagai respon masyarakat Minangkabau atas dominasi budaya Jawa (Bahasa Jawa sebagai mata pelajaran pokok) di sekolah-sekolah sejak 1950-an, namun Asnan menambahkan bahwa femomena tersebut “sesungguhnya sebuah ‘kemunduran’ dalam politik berbahasa dan bernegara orang Minang” (hal: 137). Karena dua dekade sebelumnya, para elit Minang justru menolak dengan keras pewajiban Bahasa Minang sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan menginginkan agar bahasa Melayu (Indonesia) menjadi bahasa pengantar.
Upaya mendefinisikan Sumatera Tengah sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau berakhir pada 1957. Terhentinya upaya tersebut adalah akibat politik geografi pemerintah pusat. Pemerintah Pusat dalam usahanya untuk mengembosi sumber-sumber ekonomi PRRI di Sumatera Tengah, memberikan ijin bagi elit-elit lokal Riau dan Jambi untuk memisahkan diri dari Sumatera Tengah dan mendirikan Provinsi terpisah. Keinginan para elit Riau dan Jambi tersebut juga tidak muncul karena ‘hasutan’ pemerintah pusat semata. Semenjak awal 1950-an, para elit tersebut sudah menyatakan ketidaksukaan terhadap dominasi orang Minang dalam dewan perwakilan daerah dan struktur pemerintahan Sumatera Tengah.
Pada masa-masa sebelum PRRI, ‘perjuangan’ orang Riau dan Jambi untuk ‘merdeka’ selalu kandas. Bukittinggi dan Jakarta selalu menolak atau menunda untuk memberikan status otonomi pada Riau dan Jambi. Setelah lobi-lobi panjang yang berkaitan dengan bagi hasil pendapatan daerah antara elit-elit Riau dan Jambi dan Dewan Banteng yang sejak 1956 mengambil alih pemerintahan sipil Sumatera Tengah, memberikan status otonom terhadap Riau dan Jambi. Namun pemerintah Pusat nampaknya berhasil meyakinkan para elit Riau dan Jambi bahwa hanya pemerintah Pusat-lah yang punya kuasa untuk memberi status tersebut. Pemekaran tersebut, menurut Asnan adalah strategi pemerintah pusat untuk “‘mematikan’ gerak langkah Dewan Banteng di Riau dan Jambi yang merupakan sumber pendapatan (ekonomi) utama bagi Sumatera Tengah” (hal: 234).
Saat itu, Sumatera Barat menjadi satu Provinsi sendiri. Orang Minangkabau kehilangan klaim secara legal formal maupun budaya atas Riau dan Jambi yang masing-masingnya menjadi Provinsi. Sebagai catatan, dampak gagalnya proyek Minangkabauisasi Sumatera Tengah pada masa-masa tersebut belum mendapat perhatian khusus sampai hari ini.
Buku Yang Jarang Dibicarakan
Buku ini termasuk buku yang jarang dibicarakan. Kalau pun buku ini dikutip oleh sebuah karya ilmiah, misalnya beberapa skripsi yang pernah saya temukan, pengutipannya baru sebatas pengutipan tahun—bukan salah satu tesis utamanya. Padahal, seperti dipaparkan di atas, selain temuan penting Gusti Asnan tentang “karakteristik” baru di Sumatera Barat yang muncul pada masa 1950-an, buku ini memberi gambaran yang cukup kaya mengenai Sumatera Barat periode tersebut. Buku ini juga menghadirkan dinamika berbagai kelompok sosial yang muncul pada masa-masa tersebut. Mulai dari berbagai organisasi perempuan dengan berbagai pandangan politiknya, kemunculan Partai Adat Rakyat, pertarungan wacana otonomi daerah, dan yang tak kalah pentingnya: kemunculan kelompok sosial bernama tentara.
Untuk kelompok tentara, Asnan memberi ruang pembahasan cukup panjang. Asnan memperlihatkan posisi penting kelompok ini dalam masa-masa pra-PRRI. Kelompok ini dapat tampil sebagai kelompok dominan di Sumatera Tengah yang memungkinkan mereka mendirikan Dewan Banteng dan menjadi aktor penting pada masa itu setelah menjalin aliansi dengan para poltisi lokal. Aliansi yang tercipta di antara kelompok yang sebelumnya kurang akur ini terjadi karena mereka menghadapi persoalan yang sama. Di antaranya ialah munculnya wacana menggelar pengadilan militer bagi para penjahat perang. Wacana ini ditentang tidak hanya oleh kalangan tentara, namun juga politisi lokal dari partai-partai politik yang pada masa revolusi memiliki hubungan dengan lasykar-lasykar yang rentan terseret kasus ‘kejahatan perang’. Selanjutnya ketegangan-ketegangan antara aliansi tentara dan politisi lokal dengan pemerintahan daerah yang merupakan representasi pemerintahan pusat, akan memuncak pada PRRI.
Barangkali, kontradiksi-kontradiksi yang dimunculkan buku ini seperti keinginan Bukittinggi (wilayah inti kebudayaan Minangkabau) untuk menjadi pusat bagi Sumatera Tengah sementara pada saat yang bersamaan mengutuk sentralisme Jakarta, terasa menganggu pembaca dengan latar budaya Minangkabau. Sentralisme Jakarta–seperti dengan mudah dapat dilihat dalam berbagai artikel populer bahkan karya ilmiah yang menyinggung sebab-sebab terjadinya PRRI–kerap dirujuk sebagai salah satu faktor utama ketidakpuasaan daerah yang memicu perlawanan bersenjata PRRI. Narasi sentralisme Jakarta sebagai penyebab utama PRRI memang sering dipakai untuk melawan stigma ‘pemberontak’ yang dilekatkan narasi sejarah resmi terhadap orang Minang.
Buku ini menunjukkan bahwa sejarah Sumatera Barat periode 1950-an amatlah kompleks. Peristiwa sejarah di Sumatera Barat pasca-kemerdekaan, seperti dikatakan Asnan, bukan hanya PRRI saja. Sejarah Sumatera Barat 1950-an juga tidak sehitam-putih yang digambarkan sejarah versi Orde Baru. Diperlukan penelitian dengan pendekatan baru mengenai periode tersebut, terutama pendekatan ekonomi-politik. Ini sangat penting mengingat selama ini faktor-faktor ekonomi yang dalam banyak tulisan mengenai sejarah Sumatera Barat diklaim sebagai salah satu pemicu utama terjadinya PRRI, sesungguhnya belum dianalisa secara mendalam. Dengan begitu, kita akan terhindar dari rabun dekat sejarah dan berhenti mencari kambing hitam dalam sejarah. (*)
Judul Buku: Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an
Penulis: Gusti Asnan
Penerbit: Yayasan Obor Indonesia-Jakarta, 2007
Tebal: xxvi + 263
ISBN: 978-979-461-640-6
Resensiator: Randi Reimena
Rujukan:
Henk Schulte Nordholt et al, Persepktif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Yayasan Obor: Jakart, 2008
Siat van Bemmelem dan Remco Raben, Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an, Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa. Yayasan Obor Indonsia: Jakarta, 2011.
Catatan kaki:
[1] Pembahasan lebih jauh mengenai bagiamana rezim Orde baru melakukan politik periode sejarah demi melegitimasi kekuasaannya, dapat dilihat dalam Vickers, Adrian, Mengapa Periode 1950-an Penting Bagi Kajian Indonesia dalam Henk Schulte Nordholt et al, Persepktif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (Yayasan Obor: Jakarta, 2008). Lihat Juga, Mc Vey, Ruth, Kasus Tenggelamnya Sebuah Dasawarsa dalam Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an, Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa (2011: 18-37)
[2] Asnan melihat suatu pola hubungan baru yang juga muncul pada periode 50’an tersebut, yaitu pola hubungan pusat daerah. Pola hubungan pusat daerah ini memiliki dua pengertian, secara nasional pusat dimaknai sebagai Jakarta dengan Sumatera Tengah sebagai daerah (pinggiran). Sedang di tataran regional, pusat dimaknai sebagai Bukittinggi dengan Riau serta Jambi sebagai daerah (pinggiran).


