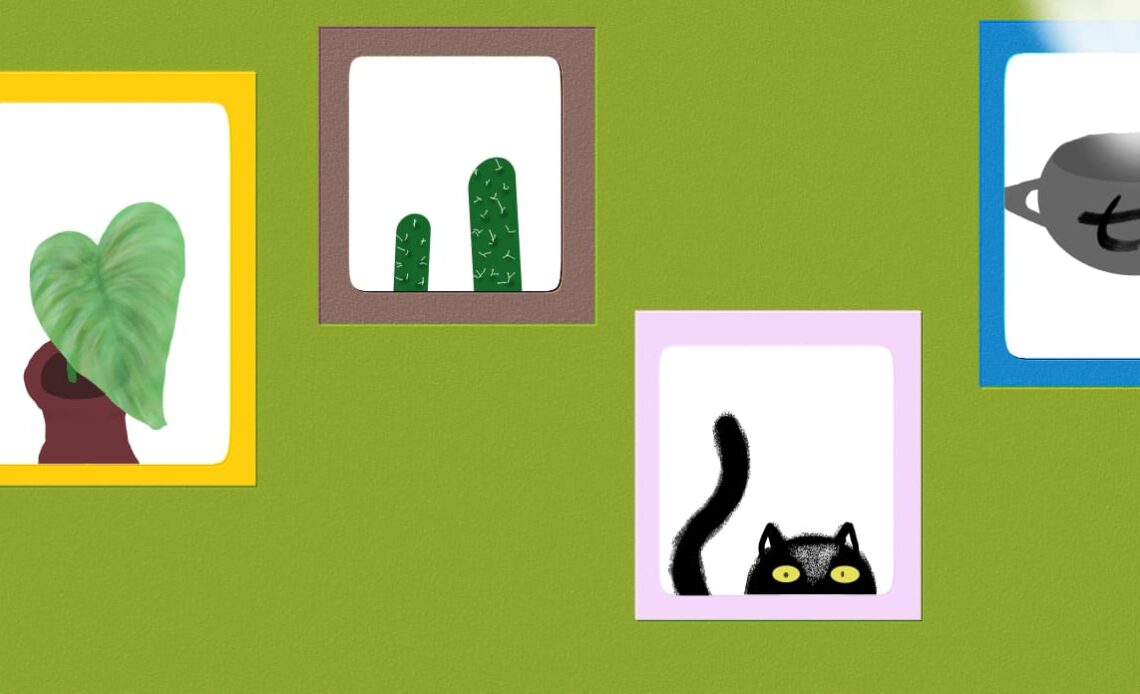
Saya membaca ulasan Heru Joni Putra di Garak.id, respon atas cuitan Pak Miko Kamal (PMK) mengenai bagaimana dikotomi “kampung” dan “rantau” dibangun oleh PMK dari sebuah adagium (pepatah), dan bagaimana adagium tersebut dialih-fungsikan atau diberi-makna jauh dari ruang kehadirannya: dari gelanggang kebudayaan, ke ranah pribadi, lalu ke gelanggang politik. Saya ikut tergerak mengulas cuitan PMK, sebagai perantau ulang-alik, cuitan tersebut seakan merepresentasikan saya sebagai orang linglung.
Bagaimana tidak? Saya anggap proses hidup yang saya jalani saat ini adalah “perantauan ulang-alik”, sebulan dua bulan di rantau lalu pulang, begitu benar nasib badan diri. Bila membaca cuitan PMK, bukankah saya tergolong orang “tidak berguna” bila berangkat ke rantau, lalu menjadi “sangat berguna” bilang pulang, balik lagi ke rantau menjadi “tidak berguna”, pulang lagi menjadi orang “sangat berguna”, dan selalu begitu. Saya serupa golongan orang linglung ketika membaca bagaimana “rantau” dan “kampung” diposisikan oleh PMK. Linglung sekaligus mengasihani diri saya sendiri: begini benar badan diri diposisikan, sudahlah di kampung tidak berharta tidak berpangkat, pergi merantaupun karena dianggap orang tak berguna di kampung. Iba jadinya saya pada diri sendiri.
Melihat bagaimana pemaknaan dibebankan terhadap sebuah adagium, seperti cuitan PMK, maka pembacaan ulang terhadap adagium tersebut melalui perspektif kebudayaan (sastra) menjadi sangat penting. Hal ini guna menghindari agar adagium-adagium lain tidak gampang diseret ke dalam cara pandang personal untuk kemudian dipolitisasi. Adagium tersebut lahir dari lokus kebudayaan Minangkabau, dengan kekhasan, dengan keunikan, dan dengan sejarah panjang yang tidak dapat begitu saja dialih-fungsikan atau diberi-makna demi kepentingan pribadi belaka: kepentingan yang menggeser makna usali, yang menyulih dan menempel dengan makna lain, yang membelah-bagi kesatuan dari adagium itu sendiri.
Adagium yang dibangun dengan model pantun dalam kelisanan Minangkabau, dalam kesatuannya jelas saling berkaitan satu dan lainnya. Kesatuan tersebut, dari bentuk dan isi, tidak dapat begitu saja dipisah dan dibelah-bagi secara serampangan. Dari bentuk, kita akan menemukan sampirannya berbeda dengan pola pantun biasa. Bila pada pantun biasa sampiran bisa saja diganti dengan pengandaian lain, pada pola pantun Minangkabau sampirannya terikat pemaknaanya dengan isi. Pola pantun Minang memungkinan metafora pada sampiran bisa jadi lebih kuat pemaknaanya dibanding isinya sendiri. Dan isi, juga tidak bisa dibelah-bagi begitu saja. Ia adalah kesatuan saling menguatkan, dan pada dasarnya memang difungsikan untuk memberi kekuatan pada subjek yang diusung oleh pantun itu sendiri.
Lalu bagaimana dengan adagium berpola pantun mengenai perantauan yang dikutip oleh PMK? Apakah pantun itu hadir dalam rangka membangun dikotomi antara “kampung” dan “rantau”, atau ia malah sebenarnya hadir untuk saling menguatkan? Apakah pantun itu hadir untuk memisah antara “yang berguna” dan “ yang tidak berguna”, atau ia malah hadir sebagai upaya untuk saling memengikat dan menghubungkan? Atau malahan pantun itu secara pemaknaan malah menggunakan metafora “kampung” dan “rantau” untuk memperkuat subjek lain?
Di sinilah saya ingin “melipat” pantun ini dalam catatan singkat dan mengembalikannya ke rahim pemaknaan Minangkabau, rahim penciptaannya—“melipat” menjadi pilihan bagi saya, sebab jika pembahasan rantau diulas dan dibentang ia tidak akan sudah-sudah, ibarat kata orang tua-tua: kok dibantang salueh alam, kok dilipek saleba kuku (jika dibentang [ia] seluas alam, jika dilipat [ia] selebar kuku).
Reinterpretasi & Kecatatan Pandangan Kultural
Sebuah adagium jika direinterpretasi atau diberikan pemakaan ulang dengan tidak tepat, akan bersalin rupa menjadi tatanan kalimat untuk menghancurkan fungsi kehadiran adagium itu sendiri. Saya kira ini terjadi pada adagium yang digunakan PMK untuk membelah-bagi “rantau”-“kampung” dan “kebergunaan”-“ketidak bergunaan” berikut dengan subjeknya (“orang kampung”-“orang rantau”). Jika kita membaca dengan jernih, adagium tersebut malah tidak berupaya membangun oposisi biner, melainkan guna membangun hubungan strategis antara “kampung” dan “rantau” untuk subjek “bujang” dan Minangkabau secara luas. Coba perhatikan kembali bagaimana isi dari adagium tersebut sebelum PMK menggubahnya ke dalam bahasa Indonesia:
Ka rantau bujang daulu (Ke rantau bujang dahulu)
Di rumah paguno balun (Di rumah berguna belum)
Dalam isi adagium di atas kita dapat melihat hubungan dan satuan pemaknaan antara “rantau” dan “rumah” (kampung) adalah sebuah upaya untuk mengisi “ke-belum-berguna-an” si “bujang”. Penting untuk memberi penekanan, bahwa “belum-berguna” bukan berarti “tidak-berguna”, sebagaimana dituliskan PMK dalam cuitannya. Penghadiran struktur pantun Minangkabau pada dasarnya memungkinkan pemaknaannya dapat berubah fungsi jika seseorang tidak bisa hati-hati membaca bagaimana kata-kata dibangun menjadi sebuah tatanan kalimat. Termasuk dalam pantun ini, kata “balun” (belum) sangat jauh sekali pemaknaannya dari kata “indak” (tidak). Mengganti pemaknaan kata “balun” (belum) dengan “indak” (tidak) adalah sebuah upaya penghancuran pemaknaan.
Kata “balun” pada bagian dalam adagium dimaksud adalah bentuk proses membangun kedirian si subjek “bujang”, membangun “rumah”, “kampung” (nagari), bisa jadi membangun “Minangkabau”. Prosesnya melalui “rantau’, dalam artian, “rantau” adalah sebuah ruang untuk mencari berbagai kemungkinan baru (materi dan non-material) untuk kemudian dibawa ke rumah (kampung). Maka akan salah, dan benar-benar kesalahan fatal, bila PMK hanya memaknai isi dari pantun tersebut dalam bentuk oposisi biner “yang tinggal di kampung adalah orang sangat berguna” dan “merantau karena tidak berguna di kampung”. Saya kutipkan kembali lengkapnya cuitan PMK:
“Org rantau banyak yg sok hebat. Org kampung dianggapnya bodoh semua. Pdhl mamangan adatnya: “keratau madang di hulu, berbuah berbunga belum. Merantau bujang dahulu, di rumah berguna belum. Artinya, yg tinggal di kampung adlh org yg sangat berguna. Dia merantau krn tdk berguna di kampung.” (Twitter @kamalmiko, 7 Maret 2022, 01.44 WIB).
Entah PMK tidak dapat memaknai adagium tersebut dengan jernih atau hanya menguarkan emosi belaka dari pengalaman personalnya terhadap satu-dua-tiga orang (dari rantau). Namun, saya yakin, tidak banyak orang rantau serupa dimaksud dalam cuitan PMK—barangkali PMK menemukan beberapa di lapangan politik praktis dan level pengambil kebijakan, sekali lagi “barangkali”. Dan tidak tepat pula pantun tersebut memberi arti (baca: PMK menuliskan “artinya”): “Yang tinggal di kampung adalah orang yang sangat berguna. Dia merantau karen tidak berguna di kampung”.
Jika ditelisik lebih lanjut, dari pantun mengenai perantauan di atas, proses “rantau” menjadi penting dalam pembangunan “rumah” (kampung). Pantun tersebut malah berupaya memberi saran agar si “bujang” untuk melakukan perantauan, mencari pengetahuan dan berbagai kemungkinan baru, untuk kemudian dibawa ke kampung. Ini dimaksudkan sebagai proses saling mengisi, bukan membelah-membagi. PMK sebagai akademisi, praktisi, tokoh publik, dst. tentu saja lebih dulu daripada saya khatam membaca beragam pandangan peneliti mengenai bagaimana hubungan rantau dan kampung bekerja. Sebagaimana Taufik Abdullah dalam Sekolah Dan Politik : Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat, 1927-1933 membahasakan bahwa perantauan mempunyai beragam bentuk. Bahkan dari kecil, anak Minangkabau (lelaki) sudah diajarkan untuk meraih “rantau internal”, sebuah ruang di mana sekumpulan nilai-nilai di sekeliling dan orang yang menyimpang bisa diekspresikan secara terbuka. Ruang ini memberikan jalan keluar filosofis untuk toleransi nilai-nilai dalam situasi adat intensif di mana kehidupan masyarakat didominasi oleh jaringan sosial adat yang rumit dan peraturan yang kompleks.
Dan apa “rantau internal” itu? Lepau, surau, gelanggang permainan. Jadi, rantau jika ditilik dari perspektif sosial-budaya tentu tidak hanya melulu membahas posisi geografis. Rantau bisa jadi berada dalam wilayah geografis kampung itu sendiri, sebagaimana “rantau internal” dibahasakan Taufik Abdullah. Barulah ketika ia (si bujang) dianggap selesai di gelanggang “rantau internal”, ia akan melangkah ke tahapan selanjutnya: “rantau ideal”—secara geografis berjarak dengan kampung.
PMK tentu juga sudah lebih dahulu khatam menjelajahi percik permenungan kultural Muhammad Radjab dalam autobiografinya Semasa Ketjil Dikampung. Di sini kita dapat melihat bagaimana Radjab menggambarkan betapa tidak mudah terlahir sebagai lelaki Minangkabau: lahir dan tumbuh di kampung, hingga dihadapkan pada putusan merantau. Rantau juga menghadapkan orang-orang pada hasrat pengembaraan, jalan lain untuk menambah pengetahuan, terutama menghimpun materi. Rantau adalah jalan lain untuk kembali pada kampung. Hasrat untuk merantau juga tidak semata karena nasib malang dialami di kampung. Bisa jadi ia tidak melarat di kampung, tapi menginginkan petualangan lain: “menukar hidup sentosa di kampung dengan hidup berdjuang dirantau,” kata Radjab.
Kita juga dapat membaca kembali pandangan Mochtar Naim dalam buku Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, yang lebih dekat dengan adagium yang dikutip PMK. Dari penelitian ini kita akan dapat melihat bagaimana hubungan proses “merantau” dengan serangkaian peristiwa politik dan kultural yang panjang. Tidak semudah pemberian makna PMK terhadap sebuah adagium, lalu membelah-bagi pemaknaan melalui oposisi biner: “yang tinggal di kampung adalah orang sangat berguna” dan “merantau karena tidak berguna di kampung”. Proses ini adalah serangkaian peristiwa untuk saling mengisi. Seperti pengalaman di kampung berguna untuk merantau, sebaliknya pengalaman merantau berguna untuk di kampung. Dan tentunya, sekali lagi, PMK sudah lebih dahulu khatam dari saya mencacah pandangan Mochtar Naim ini.
Terakhir, sebagai perantau ulang-alik yang merasa iba pada diri sendiri setelah membaca cuitan PMK, saya menekankan betapa penting untuk memosisikan adagium-adagium Minangkabau pada tempatnya dan tidak menggiring pemaknannya ke ruang binaritas—apalagi pemaknaannya tidak betul. “Rantau” dan “kampung” adalah satuan tidak terpisahkan yang membentuk cara pandang masyarakat Minang. Membelah-bagi dan membanding-bandingkan guna orang “rantau” dan orang “kampung” adalah sebuah kecacatan cara pandang kultural. Bicara lagi soal adagium, tidak seseorang pun yang tidak berguna dalam langgam kehidupan Minangkabau:
Nan buto paambuih lasuang
Nan pakak palapeh badia
Nan lumpuah paunyi rumah
Nan kuaik pambaok baban
Nan binguang disuruah-suruah
Nan cadiak lawan barundiang. (*)


