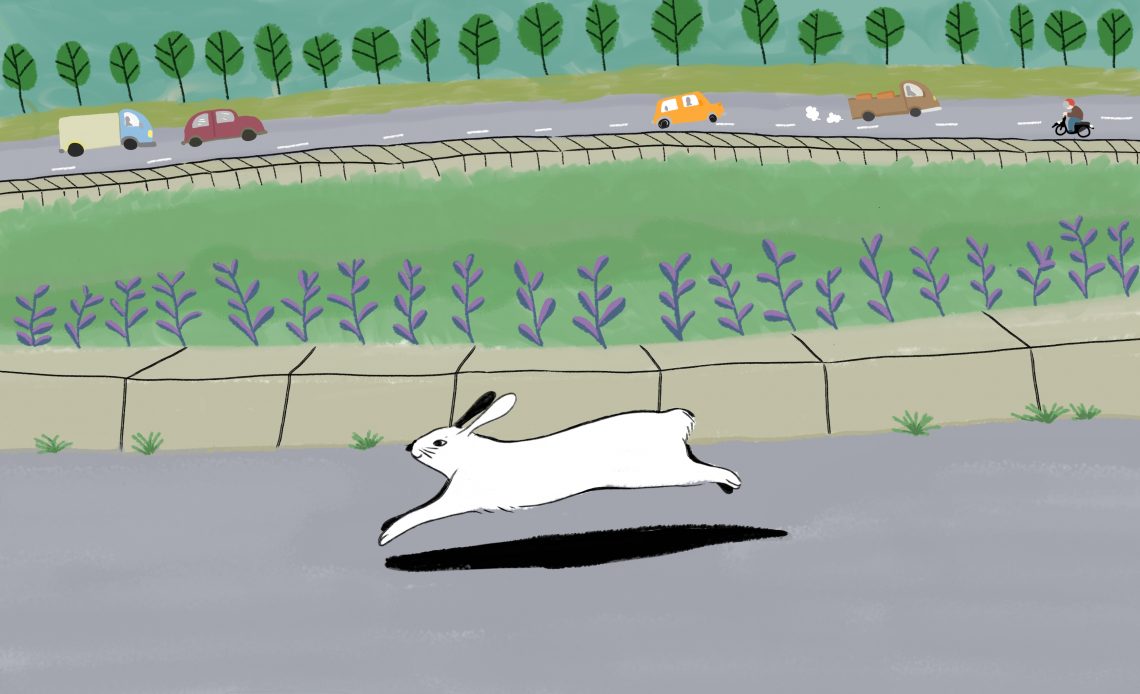
Pada bulan Juli tahun lalu, beruntung, Garak.id menerbitkan satu artikel terjemahan oleh Haldi Patra. Yang diterjemahkan adalah tulisan Guru Besar Sejarah Universitas Andalas, Gusti Asnan dengan judul “Transportation on the West of Sumatra in the Nineteenth Century”. Menjelang hampir setahun tulisan tersebut hadir, kiranya makin relevan untuk dibaca ulang, mengingat sebuah revolusi baru dalam infrastruktur transportasi tengah berada di pintu gerbang Sumatera Barat.
Artikel tersebut memberikan informasi yang sangat kaya mengenai kondisi jalan pada-awal-awal sejarah modern di Sumatera Barat, jaringan jalan setapak dan perkembangannya hingga lepas abad ke 19, jenis-jenis transportasi hingga berapa biaya menggunakan sewa sebuah pedati. Namun kami ingin masuk dan berfokus pada dimensi ekonomi politik dengan melihat setidaknya bagaimana jalan dimanfaatkan dari waktu ke waktu oleh berbagai pihak, dan bagaimana ia berdampak sosial dan ekonomi pada manusia di mana jalan itu berdiri. Dan melalui itu kami ingin memproyeksikannya dalam sebuah analisis lain pada situasi yang Sumbar hadapi hari ini. Persilahkan kami memulai dengan meriview hal yang relevan dari tulisan Gusti Asnan.
Jalanan Pada Awal Sejarah Hingga Abad 19
Konon, dari sebelum abad ke-15, daratan Sumatera Barat hari ini hanya terhubungkan oleh jalanan setapak yang digunakan oleh orang-orang pegunungan ke pesisir (utamanya pesisir barat) untuk mendapatkan garam. Garis-garis setapak inilah yang mengukuhkan relasi antara dataran tinggi dan kawasan pesisir, karena orang-orang yang hidup di pantai belakangan secara umum berasal dari pedalaman dalam jangkauan garis tersebut. Disebutkan paling tidak terdapat lima kelompok jalan setapak yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan pantai dan daerah-daerah baru yang kemudian menjadi rantau-nya.
Pada abad 14 atau 15 fungsi utama jalan setapak sebagai “jalan garam” berganti menjadi “jalan dagang”. Beberapa pos dagang di kawasan pantai bermunculan, dan hubungan antara wilayah pantai dengan pedalaman berubah menjadi hubungan ekonomi perdagangan. Dituliskan bahwa beberapa komoditi telah diangkut melalui jalan dagang ini. Emas menjadi produk pertama dan yang paling penting yang diangkut di hampir semua jalan; kemudian komoditas lainnya seperti kayu lignum aloe, kamper, damar, lilin, madu dan hasil-hasil hutan lainnya. Sementara dari pantai diangkutlah kain, katun, sutra, ikan kering dan tentu saja garam.
Meskipun jaringan jalan ini telah menjadi jalan dagang, penggunaannya masih sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna jalan garam: oleh penduduk lokal sendiri, pedagang dan pengelana. Ini juga mengingat bangsa eropa baru masuk kepedalaman Minangkabau pada tahun 1818.
Ketika hubungan Sumatra dengan dunia luar semakin terbuka, jalan setapak memperoleh arti politis melebihi makna ekonomi yang telah dimiliki sebelumnya. Arti politis ini menjadi jelas ketika Belanda meluaskan pengaruhnya dari pos mereka di kota-kota pantai ke daerah pedalaman. Kampanye militer menggunakan jalan setapak yang sempit dianggap tidak memadai bagi pergerakan militer Belanda. Jalanan sempit itu harus diubah menjadi jalan yang lebih lebar. Maka pada tahun 1833 di bawah Gubernur Jendral Johannes van den Bosch – si pencetus tanam paksa itu – diperbaharuilah bekas jalan dagang yang telah ada sebelumnya dari Padang ke Padang Panjang Via lembah Anai. Kemudian dilanjutkan Padang Panjang dan Bonjol via Padang Luar dan Matua, seterusnya ke Bukittinggi dan Payakumbuh. Bukittinggi (atau Fort de Kock) kemudian menjadi pusat kedudukan militer Belanda di pedalaman; sedangkan Payakumbuh sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi Belanda di dataran tinggi. Di sana Belanda membuka Nederlandsche Handel Maatschappij ( NHM, di sana mereka juga membangun rantai perbentengan di mana merupakan batas Padangsche Bovenlanden dengan hulu sungai yang mengalir ke timur. Tujuan dari pendirian benteng-benteng ini adalah untuk mengekang perdagangan orang-orang pedalaman di beberapa pangkalan, Panambatan dan Pamuatan di timur Payakumbuh. Pada akhir 1860-an, telah terdapat 12 rumah singgah dan pos militer di antara Padang dan Padang Panjang, Padang Panjang ke Bukittinggi dan Payakumbuh serta dari Padang Panjang ke Batusangkar. Dengan kata lain, semua ini adalah bagian dari upaya monopoli sumber-sumber ekonomi di dataran tinggi.
Jalan sekunderpun dibangun semenjak 1848. Jalan tipe ini digunakan terutama untuk menghubungkan beberapa kota dalam sebuah kawasan di Sumatera Barat atau memfasilitasi proses pengangkutan kopi dari beberapa nagari ke gudang penyimpanan kopi pemerintah di ibukota distrik. Para pekerja yang membangun jalan itu terdiri atas kuli-kuli dan masyarakat lokal yang kadang dipekerjakan melalui mekanisme kerja paksa (herendiensten).
Peningkatan dalam kualitas dan kuantitas jalan setelah 1848 berhubungan dengan perintah penanaman kopi dan sistem pengangkutan. Setiap keluarga petani dalam sebuah wilayah dengan iklim dan tanah yang cocok, diminta untuk menanam dan memelihara setidaknya 150 batang kopi. Semua kopi yang dihasilkan harus diangkut ke gudang pemerintah. Kopi-kopi itu dibayar dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Gudang-gudang ini dibangun di hampir seluruh distrik di pantai barat. Untuk pembayaran, petani menerima pembayaran dengan uang tunai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.
Semua jalanan sekunder ini menghubungkan gudang kopi ke ibukota atau kota penting di wilayah itu. Kopi yang diproduksi di Limapuluh Koto, sebagai contoh, dibawa ke Payakumbuh, kopi yang diproduksi di Agam diangkut ke Bukittinggi dan kopi di Tanah Datar ke Batusangkar. Semua kopi dari wilayah itu dibawa ke Padang atau Pariaman dengan jalan utama dari Padang Panjang, via Lembah Anai dan Kayutanam.
Pembangunan jalan mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19. Pembukaan beberapa perkebunan besar pada 1887-an menopang ekspansi pembangunan itu. Jalan sampingan cabang dari jalanan sekunder di Solok, Tanah Datar, Lima Puluh Kota dan Pasaman dibangun ketika beberapa perkebunan besar dibuka di daerah tersebut. Pembukaan sejumlah perkebunan baru itu juga meningkatkan jumlah transportaannemers.
Sebagai hasil dari semua aktivitas pembangunan ini – lanjut Gusti Asnan – Gouvernement van Sumatra’s Westkust pada 1900 menjadi provinsi dengan jalan terpanjang dan jembatan terbesar di luar Jawa. Jalanan kelas I (standar jalan tertinggi) membentang sekitar 153 km, sedangkan jalan kelas II sekitar 651 km dan 2.525 km jalan kelas III. Terdapat enam jembatan lengkung (broogbruggen) dengan panjang lebih dari sepuluh meter dan 115 jembatan lengkung dengan kepanjangan kurang dari sepuluh meter. Terdapat 1.783 jembatan kompleksitas teknik sedang (ligger dan vakbruggen), dengan rata-rata panjangnya 8 meter. Selain itu terdapat 792 jembatan temporer (noodbruggen) dan 2.092 gorong-gorong (kleine doorlaten).
Jalan Sebagai Instrumen Ekonomi
Adalah salah jika memahami jalan dalam pengertian formal semata – bahwa ia adalah sarana perlintasan dari satu lokasi ke lokasi lain. Jalan tentu jauh melebihi makna sebagai sebuah media penghubung saja, di atasnya berdiri fungsi instrumental ekonomi yang dipengaruhi oleh dinamika sosio-politik di sekelilingnya. Dari catatan sejarah Gusti Asnan sebagaimana dirangkum di atas, setidaknya kami melihat telah terjadi dua kali gelombang perkembangan jalan pada abad 19. Yang pertama jalan setapak sebagai jalan garam bertransformasi menjadi jalan dagang. Dan yang kedua adalah jalan dagang bertransformasi menjadi jalan sebagai sarana penaklukkan dan eksploitasi di bawah panji kolonialisme Belanda.
Yang membuat sama ketiga potret jalanan di atas adalah bahwa ia sama-sama berguna dan dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi. Pada awalnya, jalan garam telah menjadi akses mendapatkan serta menyalurkan garam dari pesisir ke pedalaman. Ia memungkinkan asam di gunung bertemu garam dari laut. Belum ada perdagangan sejauh yang tercatat dalam arti perdangangan dengan mode kapitalistik. Jalan setapak ini adalah jalan yang digunakan oleh “siapa saja” dari darek dan sebaliknya.
Barulah pada abad 14 atau 15 mode ekonomi baru muncul di atas jalan-jalan garam. Barang-barang tadi berubah menjadi komoditi. Dia diperdagangkan secara lokal dan terbatas. Begitupun setelahnya, semasa kolonialisme. Emas, kopi dan komoditas lainnya menjadi tonggak ekonomi, diangkut dari pedalaman keluar ke pasar dunia. Tidak bisa disangkal memang bahwa geliat ekonomi sangat dipengaruhi dukungan infrastruktur jalan. Pada masanya komoditas-komoditas terakhir berkontribusi pada kedigdayakan eksploitasi kolonial.
Penguasa Jalanan
Meskipun ketiga potret jalanan itu sama-sama sebagai instrumen ekonomi, namun yang membedakannya adalah bagaimana ia berkembang dan siapa yang mendapatkan keuntungan utama dari keberadaannya. Perubahan dari jalan garam ke jalan dagang, bagaimanapun telah merubah fungsi jalan sebagai akses untuk mengekstraksi garam guna memenuhi kebutuhan lokal, menjadi instrumen perdagangan. Namun berbeda dengan potret jalan masa kolonialisme, “jalan garam” – bahkan “jalan dagang” – setidaknya masih berkembang natural seturut tuntutan kebutuhan yang dialami di tingkat lokal. Sebaliknya perkembangan jalan pada masa kolonial, harus diakui tidak terlepas dari agenda penaklukan militer serta tuntutan perdagangan yang terkoneksi dengan pasar dunia, dengan kolonialis Belanda sebagai aktor utamanya. Sehingga struktur kuasa atas jalan yang sebelumnya telah terbangun secara lokal, runtuh.
Jika kita melihat lagi catatan Gusti Asnan, disebutkan bahwa pada masa jalan dagang atau bahkan sebelumnya, masyarakat pengguna, pengelana dan pedagang harus membayar uang jalan pada pos tertentu yang biasanya berlokasi di perbatasan nagari. Dibayarkan kepada penghulu setempat di mana mereka melintas. Bahkan diceritakan bahwa Raffles sendiripun ketika menjejakkan kaki pertama kali di pedalaman Minangkabau, telah membayar uang jalan sebanyak 26 kali. Uang jalan itu ditentukan oleh orang-orang di nagari-nagari yang dilewati. Pemanfaatan atas uang pungutan itu digunakan untuk keperluan nagari. Disebutkan bahwa jika pembayaran berbentuk barang, maka barang tersebut harus memiliki signifikansi dan arti penting bagi nagari bersangkutan. Seorang penghulu di Air Bangis, misalnya, meminta sejumlah kain kepada seorang wakil dari Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) untuk sekelompok warga miskin yang kehilangan properti mereka dalam sebuah kebakaran.
Apa yang kemudian terjadi di jalanan adalah bergesernya aktor ekonomi dominan dari yang sangat lokal berbasis nagari tadi pada pusat kuasa baru: perusahaan dagang kerajaan Belanda bersama kekuatan militernya. Setelah ditinggalkan Inggris, Belanda mendapatkan kembali pos dagang mereka di kota-kota pantai dan sekaligus membuka peluang mereka meluaskan pengaruh ke daerah pedalaman. Gubernur Jendral Johannes van den Bosch memperbaharui bekas jalan dagang yang telah ada sebelumnya guna memperlancar distribusi kopi dan komoditas lain ke pelabuhan.
Di sini kita melihat pergeseran penguasaan jalan, dari awalnya yang bersifat relatif lebih bebas dan terbuka pada masa jalan garam, menjadi penguasaan-penguasaan lokal di tingkat nagari di mana jalan melintas, dan kemudian semakin tertutup dan dimonopoli militer dan perusahaan dagang Belanda.
Apa bayaran dari semua perkembangan jalan masa kolonial itu, selah satunya adalah lancarnya tanam paksa di tanah Minangkabau. Dan tidak sepenuhnya salah juga jika dikatakan ia berkontribusi pada luluh lantaknya Minangkabau akibat perang Paderi. Kekayaan alam Minangkabau dikeruk sejadi-jadinya dan masyarakat menjadi kuli di halaman rumah gadang mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai infrastruktur jalan sebagai instrumen ekonomi, dan pada masa kolonialisme ia menghamba pada kepentingan akumulasi primitive kolonial Belanda.
Ekonomi Jalan Orde Baru: Sebagai Pembanding
Tidak cukup hingga di situ, usaha untuk terus menghubungkan daerah-daerah pedalaman Sumatera telah juga difikirkan pemerintah kolonial. Anthony Reid dalam Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia, mencatat bahwa jalan trans-Sumatera mulai dibahas untuk pertama kali pada tahun 1916. Pada masa itu, pemerintah kolonial hendak menghubungkan kota-kota penting di Sumatra: Medan, Padang, dan Palembang. Masing-masing dari ketiga kota besar ini merupakan pusat jaringan kereta dan jalan raya. Pada 1917, pemerintah kolonial membangun jalan raya yang menghubungkan Kota Medan dan Pematang Siantar. Kemudian, dari Pematang Siantar disambung lagi ke Prapat, kawasan sejuk di pesisir Danau Toba. Jalan itulah rintisan pertama dari jaringan yang belakangan disebut jalan Trans-Sumatra” tulis budayawan Sitor Situmorang dalam Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX. Pola yang sama tadinya akan dikembangkan di kota-kota lain. Namun pada 1942, balatentara Jepang datang mengobarkan Perang Asia Timur Raya. Pembangunan jalan Trans Sumatra pun terhenti.
Pada masa pasca kemerdekaan, usaha meneruskan pembangunan trans-Sumatera terhambat oleh persoalan keamanan dalam negeri seperti PRRI di Sumatera Tengah. Baru pada tahun 1960 Agenda untuk melanjutkan kembali pembangunan Trans Sumatra baru mendapat tempat. Tapi Soekarno tidak benar-benar bisa mewujudkan itu. Orde Lama ditumbangkan, Soeharto maju mengusung Orde Baru.
Segera setelah Orba mengambil kuasa, berbagai kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi asing diambil. International Monetary Fund (IMF) menuntut komitmen dan kesediaan penguasa baru ini agar sesegera mungkin merealisasikan proyek liberalisasi ekonomi sebagai syarat pokok bagi masuknya investor asing. Di Amsterdam bulan Februari 1967, sebuah kesepakatan ditanda tangani untuk membentuk konsorsium negara-negara kapitalis maju dan lembaga keuangan multilateral untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia. Konsorsium yang dikenal dengan sebutan International Government Group on Indonesia (IGGI) – dan kemudian menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI) – ini, menyalurkan pinjamannya kepada Indonesia, melalui institusi Bank Dunia. Dengan terbentuknya konsorsium pemberi bantuan, sejak tahun 1968-2001, sudah ratusan proyek yang pembangunan Indonesia yang dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia, dengan perkiraan total pinjaman sebesar US$ 29.360,63 milyar. Pada tahun 1967 UU Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan.
Salah satunya adalah proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan pesat jalan lintas Sumatera terjadi sejak rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Pertama tahun 1969 hingga 1974 – Pembangunan terpusat yang kemudian menjadi tradisi ekonomi Orba selama lebih dari tiga dasawarsa. Pembangunan meliputi tiga jalur sekaligus: Jalur Tengah, Jalur Timur, dan Jalur Barat. Selama tiga dekade kekuasaan Orde Baru, setiap provinsi di Sumatra telah terhubung lewat jalan Trans Sumatra.
Bagaimana memaknai keterhubungan fungsional antara berbagai pinjaman pembangunan itu dengan infrastruktur jalan? Satu cara sederhana tentu dengan melihat bahwa suntikan dana tersebut telah membantu Sumatera memiliki jalan lintas yang membelah berbagai provinsi dari selatan ke ujung utara. Namun ada cara analisis berbeda yang melihat bahwa pemberian hutang tersebut tidak terlepas dari upaya lepas dari krisis kapitalisme dan mengakali over-accumulation dalam tubuhnya sendiri. Harvey (2003) mengatakan, jika devaluasi ingin dihindari, maka kapitalisme menemukan cara-cara yang menguntungkan guna menyerap kelebihan modal tersebut. Perluasan geografis dan reorganisasi spasial, serta terhubung dengan pergeseran temporal adalah opsinya, di mana kelebihan modal dipindahkan ke proyek-proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan nilainya, ke sirkulasi kapital. Di sinilah jaringan transportasi bersama dengan infrastruktur fisik dan sosial yang berumur panjang lainnya (komunikasi serta pendidikan dan penelitian misalnya) mendapatkan relevansinya bagi kapitalisme. Maka mengalirlah modal dalam bentuk utang tersebut.
Hasil studi Sritua Arief (2001) menunjukkan, proyek-proyek pembangunan yang dibiayai Bank Dunia yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (sekarang seperti terdengar sebagai harapan palsu), justru makin memiskinkan kelompok miskin dan membangkrutkan usaha kecil. Kelak, ketika krisis moneter mendera Indonesia pada akhir 1997, fondasi ekonomi Indonesia yang mengandalkan utang luar negeri dan modal asing terbukti ternyata sangat rapuh.
Jalan Hari Ini
Jika masa kolonialisme jalan telah menjadi instrumen akumulasi primitive (enclosure) melalui penaklukan dan eksploitasi manusia dan alam, pada era liberalisasi Orde Baru – melalui redistribusi modal berlebih negara-negara maju ke negara-negara berkembang dalam bentuk hutang – jalan adalah media menyelamatkan kapitalisme dari kontradiksinya.
Kemudian, bagaimana pula kita mendefenisikan berbagai proyek infrastruktur jalan yang belakangan massif dilakukan, tidak hanya di Sumatera Barat namun di berbagai wilayah Indonesia? Bagi kami proyek-proyek infrastruktur ini penting untuk dilihat sebagai upaya meneruskan preferensi pasar yang kapitalistik. Agenda infrastruktur ini adalah agenda yang lahir dari elite, bergerak top to down. Bahkan lebih tinggi lagi, ia adalah bagian dari agenda pada level ASEAN yang membayangkan konektivitas negara-negara Asia Tenggara. Agenda ini tertuang dalam Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC) 2025. Sementara MPAC 2025 pun sinergis dengan Belt and Road Initiative (BRI) China, sebuah ambisi RRC membangun “jalur sutera” kedua. Disebutkan juga bahwa pengembangan infrastruktur dan konektivitas seperti kereta api, jalan raya, pelabuhan laut, bandar udara, dan lain-lain diperuntukkan guna “membangun lingkungan bisnis dan investasi yang lebih baik”.[1] Yang artinya memastikan continuity akumulasi kapital.
Namun berbeda dengan akumulasi kapital pada era kolonialisme, usaha-usaha yang tampak hari ini adalah satu bentuk baru dari akumulasi primitive tersebut (the current new enclosures). Ketika jalan dagang yang pernah terbuka dulu dikuasai pemerintah kolonial sebagai instrumen untuk mengeruk komoditas-komoditas perdagangan alam Minangkabau, pada hari ini perlu ditelisik bahwa jalan itu sendiripun adalah komoditas itu sendiri.[2] Ketika dulu jalan membantu distribusi barang-barang dagangan dari pedalaman ke pasar dunia, hari ini kita menghadapi bahwa jalan itu sendiri adalah komoditas yang diperdagangkan. Agaknya benar apa yang ditengarai teoritisi, bahwa kapitalisme bertahan melalui cara memproduksi ruang-ruang baru (capitalism survives through the production of space). Jalan, adalah arena atau ruang baru tersebut.(*)
*Tulisan ini dikerjakan bersama Randi Reimena
Ilustrasi: Amalia Putri
Catatan kaki:
1 Baca juga telaah kami dalam tulisan berikut https://tarbiyahislamiyah.id/tol-untuak-a/?fbclid=IwAR2EX2OdGe7MzHpw79iZg9SNXL_InU64H5LjyjIjQYZd6onFts7UzJaB0Ig
2. Cek berita berikut sebagai contoh awal https://bisnis.tempo.co/read/1455312/waskita-lepas-saham-tol-medan-kualanamu-ke-investor-hong-kong-rp-824-m?fbclid=IwAR3SAQr9PqhmGMpJi19ht_I8xSJ5q-5u7Y0-NlLng67Ob8L6t0w-T2nTnCo
Daftar Bacaan:
Arief, Sritua. 2001. IMF, Bank Dunia dan Indonesia. Muhammadiyah University Press.
De Angelis, Massimo. 2004. Separating the Doing and the Deed:Capital and the Continuous Character of Enclosures. Historical Materialism, volume 12:2 (57–87)
Harvey, David. 2003. New Imperalism. Oxford: Oxford University Press
Patra, Haldi. 2020. Transportasi di Pantai Barat Sumatera Pada Abad 19 (terjemahan). Garak.Id
Reid, Anthony. 2011. Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia. YOI: Jakarta.


