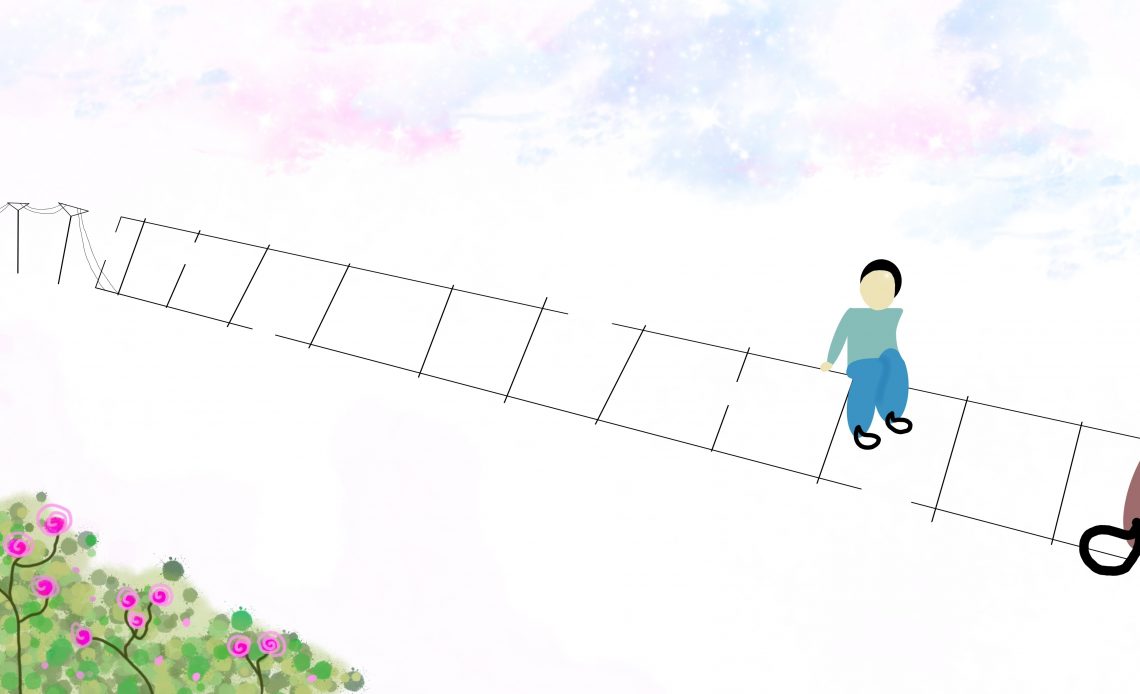
Sejarawan Kuntowijoyo secara tidak langsung pernah memberi perhatian pada tingginya minat masyarakat Sumbar akan sejarahnya sendiri. Buku-buku Rusli Amran tentang Sumatera Barat pernah menjadi buku non-fiksi yang laris pada 1980-an. Menurut Kontowijiyo, buku-buku tersebut laris karena “pembaca terpelajar Sumatera Barat cukup banyak”.
Sampai kini pun, saya berani berkata bahwa keadaannya masih demikian. Masyarakat Sumbar masih sangat tertarik dengan sejarahnya sendiri. Bisa dikatakan, nyaris setiap orang terpelajar di Sumbar hari ini memiliki pengetahuan umum tentang Tan Malaka, Bung Hatta, Pagaruyung, Perang Paderi, PRRI atau PDRI. Di internet, kita bisa dengan gampang mengakses artikel-artikel populer seputar sejarah Sumbar yang jumlahnya tidak sedikit itu.
Hanya saja minat yang besar tersebut tidak diiringi oleh kesadaran untuk memperbaharui cara memandang sejarah. Di kalangan awam, sejarah terlanjur dipahami sebagai “ilmu gampangan” yang bisa dipraktekkan siapa saja serta dikonsumsi mentah-mentah seolah-olah narasi sejarah tidak punya konsekuensi politis. Sejarah ditulis ulang dan disebarkan kadang hanya berdasarkan suka atau tidak suka, hebat tidak-hebatnya seorang pahlawan, berdasar kadar keagamaan seorang tokoh, atau sekedar heroisme konyol anti-pusat-anti-barat.
Sedang di tataran dunia akademik, bisa dikatakan nyaris tidak ada perdebatan metodologis soal bagaimana memandang sejarah Sumbar secara tepat: Kerangka pikir seperti apa yang tepat untuk menulis sejarah Sumatera Barat (juga sejarah secara umum)? Sampai dimana sejarah tentang Sumbar ditulis? Percobaan-percobaan metodologis macam apa yang telah diupayakan sejauh ini? Pertanyaan-pertanyaan macam ini sepertinya cenderung dihindari. Setelah ulasan singkat Taufik Abdullah lewat tulisannya dalam buku kumpulan esai Dialektika Minangkabau (1983) atas beberapa karya akademik, baik dari disiplin sejarah ataupun ilmu sosial dengan perspektif sejarah, bisa dikatakan tidak ada lagi upaya untuk membuat pemetaan baru terkait studi tentang Minangkabau.
Bagaimanapun, satu hal yang cukup menonjol dalam penulisan sejarah tentang Sumbar selama ini ialah ia cenderung ditulis secara insular. Sebagai unit sejarah, ia kerap kali dikaji secara terbatas dalam wilayah administratif Sumbar (itupun dengan penekanan pada Minangkabau), dan dengan satu dan lain cara dipisahkan dari wilayah lainnnya. Jarang sekali ada kajian komparatif. Jikapun ada, biasanya bersifat akademik, sulit diakses dengan mudah sehingga memiliki jarak tersendiri dengan masyarakat luas. Karya akademik lain dengan perspektif komparatif pun tidak jarang yang terjatuh pada glorifikasi Minangkabau. Karya A. Kahin tentang Sumatera Barat yang bisa dikatakan sudah jadi klasik itu bisa dijadikan contoh. Karena aspirasi anti-otoritarianisme Orba-nya, yang dianggap sebagai bagian tidak elok dari gaya penguasaan Jawa, membuat Kahin memberi penilaian positif untuk demokrasi Minangkabau secara berlebihan.
Dalam bukunya, Dari Pemberontakan ke Ingetrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 (2005) itu, Kahin membandingkan Minangkabau dan Jawa secara kelewat ekstrim. Tanpa memeriksa terlebih dahulu realitas kongkret Minangkabau, Demokrasi dan egaliterianisme Minangkabau dijadikannya semacam kebalikan dari Otoritariniasme dan Feodalisme Jawa. Tanpa menafikan arti penting kepeloporan Kahin dalam menulis sejarah lokal, serta komitmen anti-otoritarianismenya, karyanya akan sangat rentan menjadi gudang bahan baku bagi sebagian orang untuk membangun legitimasi historis “keistimewaan Minangkabau”. Dan, nampaknya, memang itulah yang terjadi.
Munculnya wacana DIM (Daerah Istimewa Minangkabau) dengan dengan segala ‘argumen sejarah’nya itu, adalah wajah nyata bobroknya ‘dunia kesejarahan’ di Sumbar. Hal tersebut tampak dari bagiamana para intelektual serta politisi pendukung DIM menempatkan sejarah sebagai salah satu alasan pokok bagi status Istimewa Minangkabau. Di balik ‘argumen sejarah’ tersebut, selain penulisan sejarah yang terlalu insular, terdapat beberapa problem lain yang bisa diidentifikasi. Identifikasi ini tentu saja bersifat percobaan. Perlu kajian sangat serius untuk memetakan persoalan kesejarahan di Sumbar.
DIM dan Teori Orang Besar Warisan Kolonial
Salah satu problem kesejarahan di Sumbar yang mencolok ialah kentalnya corak penulisan sejarah Orang Besar. Sesaknya narasi sejarah Sumatera Barat (atau Minang) oleh para pahlawan, tidak bisa dilepaskan dari salah satu teori sejarah, yang sebenarnya sudah sangat lapuk dan tidak bisa dipertahankan lagi, yaitu The Greatman Theory. Teori Orang Besar (Great-man Theory) adalah teori yang berkembang di Barat pada abad 19. Itu sekitar 200 tahun yang lalu. Salah satu penggagas utamanya, Thomas Carlyle, melihat orang-orang besar seperti Martin Luther, Napoleon, atau Frederick yang Agung sebagai individu-individu spesial yang hadir ke bumi untuk menjalankan misi ilahiah untuk membawa jalan sejarah dunia ke arah yang benar. Orang Besar diyakini lahir dengan takdir khusus, bukan dibentuk misalnya oleh situasi sosialnya.
Inilah yang persis nampak dalam pemahaman sebagian orang Minang, baik pendukung DIM atau bukan, terhadap pahlawan-pahlawannya. Siapa saja bisa dengan lancar menyebut Hatta, Sjahrir, atau Tan Malaka, tapi bisa dikatakan sangat sedikit yang mau tahu dengan konteks historis kemunculannya. Padahal latar kemunculan mereka, sangatlah kompleks. Krisis kapitalisme di Eropa pada kurun 1870-90an, imperialisme, munculnya gerakan buruh internasional, gerakan nasionalis anti-kolonial, adalah kondisi-kondisi yang membuat orang-orang seperti Hatta dan Tan Malaka ada. Mereka tidak akan menjadi Tan Malaka atau Hatta seandainya tetap sekolah di kampung dan tidak bersentuhan dengan situasi global. Namun, dalam Teori Orang Besar, semua itu nyaris tidak diperhitungkan. Yang lebih diperhitungkan, dan disebut berulangkali, ialah peran besar individu-individu seperti Hatta dalam sejarah. Benar. Teori ini berakar pada semacam indivualisme—suatu yang kontrakdiktif dengan klaim komunalisme Minangkabau pendukung DIM.
Di sini etnisitas berperan menghalau konteks historis para pahlawan. Bukannya dikaitkan dengan konteks historisnya, para pahlawan malah dikaitkan dengan etnis. Tan Malaka sebagai tokoh dalam sejarah, kini dilihat lebih sebagai Tan Malaka sebagai orang beretnis Minang. Ini mirip dengan bagaimana para sejarawan penganut teori Orang Besar yang mengaitkan kehebatan individu dengan garis darah atau pewahyuan.
Ironisnya, sebagian orang Minang yang kadang menampilkan diri sebagai anti-Barat, untuk meneladani para pahlawannya, justru secara tidak sadar menari di irama gendang orang Barat itu sendiri. Untuk diketahui, Teori Orang Besar dipatenkan sebagai “sejarah yang modern” di tempat yang kini bernama Indonesia oleh orang Belanda. Dalam buku-buku sejarah Hindia pada waktu itu, yang dibuat oleh sarjana Kolonial, Orang Besar Kulit Putih seperti Willem van Oranye mengisi begitu banyak ruang. Tujuannya jelas untuk membangun mitos kehebatan Orang Besar kulit putih sendiri sambil menanamkan sikap inferior pada pribumi.
Ketimpangan, Bukan Keunikan Sejarah
Etnisitas yang bercampur dengan penulisan sejarah lokal yang insular, kadang dengan semangat berlebihan untuk menantang narasi besar sejarah nasional, ditambah lagi dengan hegemoniknya penulisan sejarah Orang Besar, telah menyelubungi hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif maupun saling sokong antar satu unit sejarah dengan unit sejarah yang lain dengan konsep-konsep abstrak seperti ‘keistimewaan’. Hilangnya relasi antar unit sejarah ini, akan membuat satu unit sejarah menjadi kelihatan unik dalam pengertian yang negatif: relasi absurd antara unit sejarah yang istimewa dengan yang tidak-istimewa.
Tapi persoalannya tidak hanya sampai di sana, ia juga berkaitan dengan suatu pandangan bahwa sejarah bersifat unik. Menurut pandangan ini, sejarah dilihat memiliki sifat yang unik. Hanya terjadi di satu tempat, dan tak bisa terulang kembali. Dengan kata lain, sejarah bersifat lokal dan khusus. Ini adalah nature sejarah yang banyak dipercaya, sudah menjadi semacam konvensi ilmiah di kalangan sejarawan di Indonesia (dan dunia). PDRI misalnya, hanya terjadi sekali, di Sumatera Barat, dengan latar belakangnya yang khusus. Ia tidak mungkin terulang di tempat dan waktu berbeda.
Pandangan ini benar adanya. Namun, di sisi lain, penekanan terhadap ‘yang unik’ dalam sejarah bukan tanpa resiko. Legitimasi ilmiah terhadap ‘yang unik’ dalam sejarah, bukan tidak mungkin menjelma menjadi legitimasi bagi sauvinisme ketika sejarah bertemu dengan etnisitas sempit. Di titik ini, keunikan sejarah yang sebetulnya adalah konsep yang netral dengan sangat mudah dapat terperosok dipahami sebagai keunggulan atau superioritas etnis tertentu.
Hal itulah yang sangat tampak dalam argumen sebagian pendukung DIM. Sejarah Sumatera Barat yang unik dibanding sejarah daerah lainnya, dengan pahlawan-pahlawan nasionalnya yang menonjol serta peristiwa PDRI-nya, dianggap sebagai bentuk keistimewaan—jika tidak ingin disebut superioritas—etnis Minang dibanding etnis lainnya. Dalam keadaan seperti ini, sejarah hanya akan berakhir sebagai pertandingan ‘siapa paling unik’; sejarah etnis paling unik, sejarah pahlawan paling unik, dst.
Siapa yang menentukan istimewa atau tidaknya suatu etnis? Tidak ada ukuran dan indikator yang jelas. Siapa saja bisa berkata sejarah atau etnisnya unik dan karenanya istimewa. Dengan kata lain, sejarah sebagai ‘yang unik’, dalam konteks ini, sama sekali tidak objektif, atau lemah kadar obejektifitasnya sejarahnya.
Salah satu cara menyelesaikan persoalan tersebut adalah menggeser titik-tolak karena titik tolak yang lama tidak lagi bisa dipertahankan. Kita harus beralih dari yang menekankan keunikan ke pandangan yang menekankan ketimpangan. Maksudnya, peristiwa-peristiwa sejarah yang saling berlainan satu antara lain itu, mestilah dilihat sebagai ketimpangan. Titik tolak ini jelas lebih objektif, dengan indikator dan ukuran-ukuran yang jelas. Perbedaan antara jumlah sekolah modern pada masa kolonial di Sumatera Barat dengan wilayah timur Hindia Belanda serta hubungannya dengan eksploitasi sumber-sumber ekonomi setempat misalnya, haruslah dilihat sebagai ketimpangan, bukan keistimewaan atau ketidak-istimewaan salah satu di antaranya.
Begitu juga dengan peran masing-masing daerah dalam sejarah nasional. PDRI memang salah satu peristiwa penting, tapi itu tidak bisa dilihat sebagai bentuk keistimewaan Minangkabau. Sekali lagi, konsep-konsep seperti “istimewa” ini sama sekali tidak objektif—tidak ilmiah. Terjadinya PDRI di Sumbar bukanlah semata-mata karena kaitannya dengan segala keistimewaan Minangkabau sebagaiman dibayangkan pendukung DIM: Tidak ada bukti untuk itu. Ketimpangan dalam segi geografis serta ketimpangan perekonomian kapitalistik antar kawasan yang diciptakan kolonialisme Belanda atau bagaimana proses militerisasi di masa Jepang-lah yang pertama-tama kali mesti diperhitungkan dalam melihat PDRI.
Kesadaran sejarah dan Kesadaran politik
Dengan menggeser sudut pandang, dengan menekankan ketimpangan peristiwa-peristiwa sejarah ketimbang keunikan peristiwa sejarah, maka kita akan sampai pada kesadaran sejarah yang lebih objektif. Kesadaran sejarah yang objektif akan membawa pada pandangan yang objektif terhadap realitas hari ini (begitu juga sebaliknya). Pandangan yang absurd tentang sejarah akan membawa pada pandangan yang absurd atas realitas hari ini, seperti terjadi pada para pendukung DIM. Karena hanya melihat hubungan sejarah antara Minangkabau dengan etnis di wilayah lainnya dalam kerangka istimewa tidak-istimewa, maka mereka hanya sampai pada pertanyaan: seberapa istimewa sejarah sumbar dibanding sejarah daerah lainnya. Padahal, seperti telah disinggung, pertanyaan seperti itu pertanyaan yang tidak bisa diajukan: itu bukanlah pertanyaan historis.
Akibatnya, para pendukung DIM maupun kebanyakan “kalangan pembaca terpelajar” Sumbar gagal mengindentifikasi persoalan yang kongkret dan aktual. Kenapa satu kawasan, dalam kurun sejarah tertentu, bisa memiliki sekolah, surat kabar atau penerbitan yang lebih banyak, dibanding kawasan lainnya. Dalam konteks sejarah nasional, pertanyaan pentingnya bukanlah berapa istimewanya Sumbar berkat jasa sejarahnya dalam sejarah nasional, melainkan kenapa satu daerah bisa memainkan lebih banyak peran dalam alur sejarah nasional sedang yang lain tidak. Atau kenapa beberapa wilayah mengalami proses ‘integrasi’ dengan negara kesatuan yang berbeda satu sama lain, bahkan secara berdarah-darah.
Ini akan membawa kita tiba pada pertanyaan lanjutannya. Mengapa satu daerah miskin, sementara daerah lain lebih makmur. Mengapa kekayaan nasional akhirnya hanya memusat pada satu orang, satu keluarga, satu kawasan. Pendek kata, kenapa setelah puluhan tahun merdeka dan setelah berbagai rezim, amanat konstitusi tentang pemenuhan keadilan sosial tidak kunjung terpenuhi.
Untuk Sumbar sendiri, segala problem kesejarahan tersebut telah menutupi persoalan yang sangat pokok yaitu ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Sumatera Barat. Bagaimana DIM akan menjawab persoalan ketimpangan ekonomi antara Pesisir Selatan, Mentawai, dan Dharmasraya, misalnya, jika para penggagas dan pendukungnya saja tidak melihat hal tersebut sebagai persoalan. Ini belum bicara soal oligark-oligark lokal di Sumbar yang semakin membuat kekayaan terpusat pada satu titik. Atau hambatan-hambatan struktural yang membuat industri perikanan padat-karya di bagian pesisir serta industri songket berbasis nagari di dataran tinggi tidak bisa berkembang menjadi industri padat-modal. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan ditemukan jawabannya dengan kefasihan menyebut nama para pahlawan atau ikut-ikutan mendorong diperpanjangnya daftar pahlawan nasional asal Sumbar seperti yang dilakukan MSI Sumbar.
Bagaimana masalah-masalah tersebut akan terselesaikan jika tidak ada yang mau tahu soal ketimpangan tersebut serta sejarah ketimpangan itu sendiri?
Saya sama sekali tidak anti terhadap tawaran gagasan. Apa pun itu. Hanya saja, selama titik berangkatnya salah, maka bisa dipastikan gagasan yang ditawarakan tidak akan berarti banyak. Kita harus berhenti memandang diri sebagai pewaris sejarah yang unik, dan mulai melihat diri sebagai bagian dari sejarah yang timpang. Penggagas DIM sebetulnya adalah kalangan elit yang punya sumber daya cukup untuk membuat perubahan berarti di Sumatera Barat. Namun selama yang dianggap sejarah di Sumatera Barat hanyalah soal daftar nama pahlawan dan PDRI, selama pola pikir lama masih dipelihara, maka sulit untuk membayangkan Sumatera Barat yang lebih baik ke depannya.


