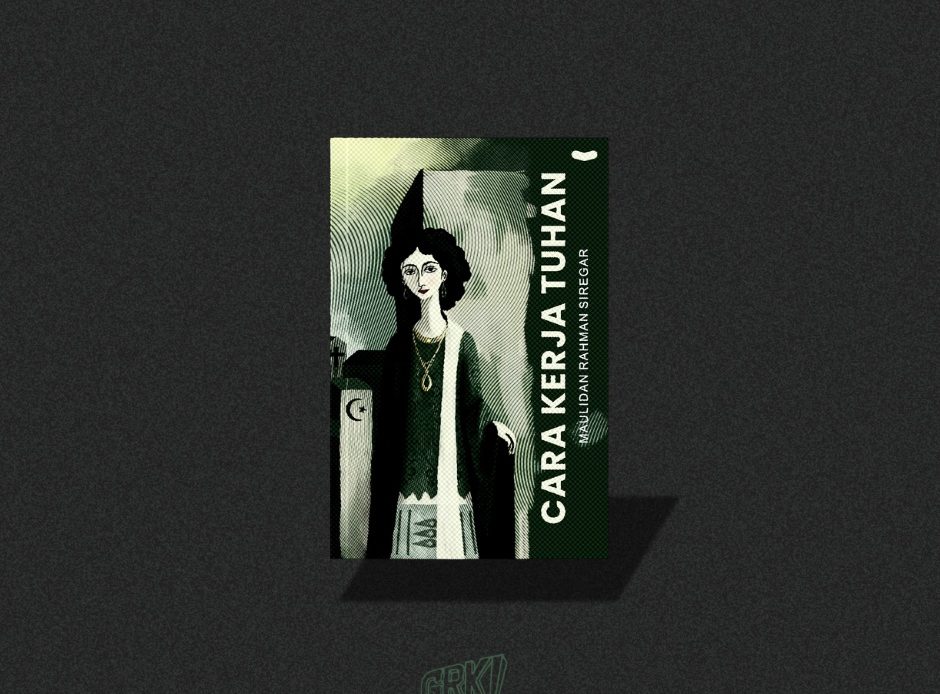
Hati saya bungah. Salah satu penulis yang saya kenal, Maulidan Rahman Siregar, baru saja menerbitkan kumpulan ceritanya. Dengan judul menghentak; Cara Kerja Tuhan, yang terdiri dari 25 cerita pendek. Di masa seperti ini, ongkos produksi yang gila-gilaan, jarak geografis dan kesenjangan infrastuktur antara Jawa-luar Jawa, terbitnya kumpulan cerita ini tentu saja patut diapriesasi. Penerbitnya Rumahkayu pula, penerbit berdedikasi yang tetap menerbitkan buku sastra di Padang, kota dengan arus penjualan buku dan keterbacaan yang begitu rendah bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya di pulau Jawa.
Sebagai penikmat karya sastra, ada beberapa referensi bacaan yang kerap saya sebut ketika memperbincangkan prosa berkualitas, meski saya bukanlah penulis prosa. Dalam pada itu, pembaca prosa berjenis cerpen agaknya bisa memahami bahwa sebuah cerpen memiliki logikanya sendiri, mencakup konsistensi dan koherensi keseluruhan cerita. Keberadaan logika itulah yang menjadikan pembaca memahami konteks penceritaan, bahkan ketika membaca prosa-prosa surealis sekalipun. Meski karya sastra surealis memiliki logika berbeda dari yang berlaku di dunia nyata, ia tetap saja memiliki logika.
Persoalan inilah yang saya temui ketika membaca Cara Kerja Tuhan. Secara umum, cerita-cerita yang termuat di dalamnya mengandung persoalan serius terkait logika, inkonsistensi penceritaan, serta kesalahan ketik (typo), hingga persoalan EYD yang merupakan dasar penulisan.
Sebagai kawan yang kerap bersinggungan dengan Maulidan di tongkrongan, dan saya rasa juga dapat diamati oleh banyak kawan lainnya, Maulidan kerap mencitrakan dirinya sebagai ‘penulis yang asyik, nyeleneh, lagi beda dari kebanyakan umat manusia’. Barangkali citraan ini pula yang mempengaruhi gaya penceritaan Maulidan, namun yang amat disayangkan adalah bila impuls itu seolah menjadi alasan pembenar untuk membiarkan Maulidan terus menulis cerpen yang tidak dapat dibedakan dengan ceracau, dan parahnya memosisikan perempuan sebagai objek.
Jadi, sebagai seorang kawan, ada beberapa hal penting yang agaknya patut saya sampaikan kepada Maulidan. Beginilah, Bang Ucok…
Catatan untuk Maulidan
Antologi yang terdiri dari 25 cerita ini mengandung persoalan serius, yakni ketiadaan kausalitas, logika dan konklusi yang relevan. Secara umum, suatu karya dapat disebut sebagai cerpen, selain dalam hal alur tunggal dan singkatnya cerita, adalah penyelesaian konflik sebagai konklusi. Atau bila tidak ada konflik, sebuah cerpen akan selalu memiliki maksud dan tujuan yang dapat dipahami, bahkan terhadap cerpen yang begitu surealis. Memang terdapat sangat banyak cerpen dengan konklusi yang terasa tanggung, atau bahkan gantung, namun cerpen-cerpen tersebut selalu memiliki logika penceritaan yang jelas.
Ulasan ini menggunakan lima cerita sebagai sampel untuk mengamati ketiadaan kausalitas, logika dan konklusi yang relevan, di antaranya Eci, Nana, Maimunah, Kocak, dan Pilihan Ibu. Pilihan pada lima cerita ini didasari oleh adanya sebuah kesamaan, yakni narasi seks dan cacat logika.
Dalam beberapa karya, pembaca dapat menemukan penulis yang kerap menggunakan narasi adegan seks atau narasi seksualitas lainnya yang berfungsi sebagai peranti yang bekerja dalam struktur cerita. Misalnya seks menjadi konflik dalam cerita, atau seks menjadi penguat hubungan tokoh, atau seks menjadi konstruksi sosial. Sementara narasi seks sama sekali tidak bekerja secara proporsional pada lima cerita tersebut, dan cenderung menjadi variabel utama sebagai alat eksploitasi terhadap tokoh perempuan.
Dalam cerita Eci, misalnya, sejak paragraf pertama Maulidan bernarasi bahwa tokoh Eci selalu mengalami pemerkosaan di setiap kota yang ia singgahi, di mana pengalaman buruk itu dimulai ketika tokoh masih di bawah umur dan dilakukan oleh keluarga angkatnya. Pemerkosaan itu menjadikan Eci terbiasa dengan hubungan intim sehingga ia menjalani kehidupan seks bebas hingga menjadi “pembicara di sebuah kelas modeling online”.
Tidak ada narasi lain dalam cerita Eci selain petualangan seks yang dialami tokoh di setiap fase hidupnya dan narasi tentang bentuk fisik yang begitu eksploitatif. Konklusi di mana Eci digambarkan memiliki taraf kehidupan yang lebih baik tidak ditopang oleh kausalitas penceritaan berdasarkan narasi seks di sepanjang cerita. Maulidan juga tidak menghubungkan adanya kausalitas antara seks bebas yang dialami tokoh sejak SMP dengan ia yang kemudian menjadi “pembicara di sebuah kelas modeling online”. Dalam bahasa sederhana, Maulidan tidak memiliki premis apapun berdasarkan pengalaman pemerkosaan dan “pembicara di sebuah kelas modeling online”.
Alih alih membangun premis, Maulidan justru sekadar bernarasi tentang bagian intim tubuh tokoh sehingga cerita yang dihadirkan sebatas seksualitas dengan menjadikan tokoh Eci sebagai objek eksploitasi seksual. Misalnya:
“Lembut, penuh sopan, berkerudung, dan tentu saja, Eci memiliki lingkar dada yang lucu. Tidak tebal dan besar, sekaligus tidak tipis dan tidak kecil juga. Sesekali nyempil di lipatan baju, sesekali tertutup kerudung. Dada Eci kalau dianalogikan, ya mirip gunung di pecahan seribu. Indah dipandang.” (halaman 10).
Hal sama terjadi pada cerita Nana yang digambarkan mengalami depresi akibat bisul di wajahnya. Tanpa sebab-akibat, cerpen ditutup dengan permintaan Nana untuk dimutilasi, celakanya sebelum pembunuhan terjadi, Nana dan tokoh Ridwan yang akan memutilasinya malah “bercinta sekuat tenaga”. Ada dua persoalan serius di cerita ini, perihal logika mengapa Ridwan bersedia membunuh dan memutilasi tubuh Nana, dan atas dasar apa keduanya harus berhubungan badan terlebih dahulu?
Maimunah juga demikian. Cerita dimulai dengan Dani yang mempersiapkan diri untuk pernikahannya dengan berbekal “video-video resolusi rendah” dan “video-video kualitas jernih”. Narasi jenis video itu memperoleh bentuk pada paragraf kedua, di frasa “sebagian orang mungkin selesai dengan cerita dewasa” yang memperjelas bahwa video dimaksud merujuk pada film porno. Cerita berlanjut dengan adegan romantika Dani dan Maimunah ketika “ia buka pakaian yang ia kenakan, ia buka celana yang ia pakai”, bahwa Maimunah “menyerahkan tubuhnya seutuhnya kepada Dani”.
Meski adegan ranjang tidak terjadi di sini, namun eksistensi narasi seks itu sama sekali tidak berfungsi sebagai peranti penceritaan yang memadai. Hal itu juga terjadi pada konklusi ketika pernikahan Dani dan Maimunah yang menghadirkan dialog, “andai ketika kau telanjang bulat dan semua perabotanmu kumainkan …”.
Disfungsi narasi seks yang tidak memiliki premis berdasarkan kausalitas juga ditemukan pada cerita Kocak ketika “dada perempuan celaka yang besar bikin Kocak jadi tolol…”, dan “setelah beberapa kali main ke hotel bersama perempuan celaka itu…”. Pretensi ini ditemukan hampir pada semua cerita yang menghadirkan tokoh perempuan, di mana seksualitas seolah diletakkan begitu saja tanpa dasar logika yang jelas dan maksud penceritaan yang kuat. Bahkan Maulidan terkesan mengeksploitasi seksualitas perempuan berdasarkan fantasi liar yang dituliskan menjadi cerita yang tak selesai.
Sementara pada cerita berjudul Pilihan Ibu, Maulidan memang berusaha memberi refleksi seputar kehidupan sastrawan yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi dan kisah percintaan yang kandas. Namun bumbu adegan seksual masih dipergunakan dengan takaran dan fungsi yang dapat diperdebatkan. Misalnya pada adegan pertemuan tokoh Marni dan tokoh Rahmat dalam sebuah acara, dan setelahnya mereka “bercinta sekuat tenaga sesudah salat Isya”. Dalam adegan ini pula terdapat dialog “tembak di luar ya, Mas? Jangan hadiahi aku banyak peluru, Mar (cetak tebal oleh peresensi). Jangan!”
Sama halnya dengan cerita-cerita sebelumnya, Maulidan mengabaikan fungsi adegan seks dalam cerita ini, berikut pula fungsi dialog bertendensi seksual. Bahkan bilamana Maulidan mencoba untuk menyederhanakan narasi dengan menyoroti keadaan ekonomi sastrawan yang pada banyak kasus kerap berbanding lurus dengan kehidupan percintaannya, seraya menghilangkan narasi seks tersebut, pesan cerita yang reflektif justru akan membangunan konstruksi cerita yang lebih proporsional.
Ketiadaan kausalitas, logika dan konklusi yang relevan pada cerita-cerita yang terhimpun dalam Cara Kerja Tuhan membawa pertanyaan tentang apakah cerita-cerita di dalamnya dapat dikatakan sebagai cerita pendek atau ceracau pendek? Apakah Cara Kerja Tuhan, beserta seluruh cerita di dalamnya, merupakan sebuah karya sastra atau sekadar igau yang ditulis dan dipublikasikan dalam bentuk buku, sekalipun mayoritas cerita di dalamnya telah dipublikasikan oleh beberapa media yang seyogianya terlebih dahulu melakukan kurasi terhadap logika cerita? Ataukah, Cara Kerja Tuhan, oleh Maulidan, tidak pernah dipandang sebagai sebuah karya sastra yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual atas segala pretensi seksis yang terkandung di dalamnya?
Catatan untuk Hasbunallah Haris
Perbincangan tentang sebuah buku tidak akan pernah terlepas dari pembicaraan ihwal industri. Dalam industri perbukuan, kritik tidak hanya dapat ditujukan kepada penulis sebagai subjek utama dalam proses kreatif yang menghasilkan karya. Lebih dari itu, kritik juga dapat dan bahkan seharusnya turut dialamatkan kepada Editor yang mesti ikut bertanggung jawab atas kualitas karya.
Membincang sejumlah kelemahan kumpulan cerita Cara Kerja Tuhan, secara proporsional, sebenarnya harus turut ditanggung oleh Hasbunallah Haris yang bekerja sebagai Editor.
Jadi, beginilah, Bung Haris…
Bila dicarah per halaman, buku ini memiliki begitu banyak kesalahan EYD yang merupakan dasar kepenulisan. Misalnya, kapan penulisan “di” yang harus dipisah, dan kapan penulisan “di” yang disambung. Kesalahan macam ini ditemukan bahkan sejak halaman 1 dan menjalar hampir di seluruh halaman. Kesalahan yang sama juga terjadi pada pengabaian peran tanda baca seperti tanda petik dan tanda koma yang dapat mengakibatkan pembaca salah memahami maksud penulis.
Selain itu, persoalan salah tulis (typo) juga ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak. Misalnya pada dialog dalam cerita berjudul Pilihan Ibu:
“Tembak di luar ya, Mas? Jangan hadiahi aku banyak peluru, Mar (cetak tebal oleh peresensi). Jangan!”
Dialog kotor antara Rahmat dan Marni rentan mengakibatkan pembaca berspekulasi, apakah “Mar” yang dimaksud penulis adalah tokoh Marni sehingga penutur kalimat itu adalah Rahmat. Bila demikian, apa relevansinya dengan frasa “banyak peluru”?
Ulasan ini memilih sudut pandang adanya salah tulis, bahwa “Mar” yang dimaksud penulis adalah “Mas” sehingga penutur kalimat itu adalah Marni. Dengan kata lain dialog tersebut merupakan sebuah kalimat linier yang diucapkan oleh satu tokoh, yakni Marni.
Kemudian ada juga kesalahan menggunakan tanda baca, hal ini ditemukan pada cerpen Nana, tepatnya di paragraf kedua di halaman 14. Kata “cermin-lah” yang terdapat pada paragraf tersebut seharusnya ditulis “cerminlah”.
Beberapa permasalahan yang diajukan pada bagian ini hanyalah sebagian kecil dari setumpuk masalah yang ditemukan dalam keseluruhan naskah, bahwa Haris sebagai Editor seharusnya memberi saran dalam rangkaian kerja kuratorial melalui proses korespondensi dengan penulis. Buku-buku sejenis dengan Cara Kerja Tuhan yang diterbitkan dengan penuh kesadaran oleh penulisnya, seharusnya, dibarengi dengan pertanggungjawaban intelektual oleh Editor sebagai bentuk kerja kolektif dalam industri perbukuan.
Penilaian kerja intelektual Editor dapat ditemukan pada konstruksi logika cerita. Di cerpen Cara Kerja Tuhan, misalnya, terdapat logika yang kontradiktif pada tokoh Aku yang semula ditulis pengangguran (halaman 2) namun tiba-tiba menjadi pegawai di akhir cerita (halaman 5).
Sementara pada cerita Eci, narasi penulis yang mengatakan bahwa Eci selalu diperkosa di setiap kota yang ia singgahi dan urutan peristiwanya juga mengandung persoalan. Pengalaman seksual tokoh Eci yang terjadi bersama tokoh Ahmad, sekalipun atas dasar suka sama suka, dapat disebut pemerkosaan karena Eci masih berada dalam rentang usia anak, di bawah 18 tahun, dan Ahmad dapat diasumsikan dewasa atau berusia di atas 18 tahun karena statusnya sebagai mahasiswa.
Premis usia Eci dapat ditarik dari narasi paragraf sebelum pemerkosaan itu terjadi, bahwa “Eci hidup bahagia bersama keluarga barunya sampai kelas 3 SMP”, dan paragraf selanjutnya bernarasi tentang petaka pemerkosaan yang dilakukan oleh Ahmad. Sehingga secara per analogiam, peristiwa pemerkosaan itu terjadi ketika Eci masih di jenjang kelas 3 SMP. Dengan kata lain, penulis menyatakan bahwa pemerkosaan oleh Ahmad adalah yang pertama bagi Eci.
Paragraf selanjutnya dimulai dengan “Keluarga baru itu dapat cobaan lagi…”, ketika Ratna, ibu angkat Eci, yang melakukan perjalanan ke luar kota setiap tanggal 20 dimanfaatkan oleh ayah angkat Eci untuk melakukan pemerkosaan. Bahwa “Artinya, sejak kelas 2 SMP semester kedua, Eci diperkosa 24x oleh ayah angkatnya sendiri”.
Di sinilah letak kekeliruan logika penulis. Bahwa pemerkosaan oleh Ahmad bukanlah yang pertama, justru pemerkosaan pertama kali dilakukan oleh ayah angkatnya karena dilakukan pada saat tokoh Eci kelas 2 SMP, sedangkan pemerkosaan oleh Ahmad dilakukan saat Eci kelas 3 SMP.
Persoalan logika lainnya adalah narasi jumlah pemerkosaan oleh ayah angkatnya yang terjadi “sejak kelas 2 SMP semester kedua”. Bahwa:
“Ratna keluar kota setiap tanggal 20, entah apa urusannya. Artinya, Eci diperkosa 24x oleh ayah angkatnya sendiri”.
Semester kedua dimulai pada awal tahun dan “lulus SMP, Eci merasa ada yang salah dari keluarganya” yang menyebabkan Eci pindah ke Bandung. Terdapat dua asumsi yang dapat digunakan untuk memahami narasi tersebut.
Asumsi pertama, pemerkosaan pertama kali dilakukan ayah angkat Eci pada bulan Januari. Asumsi kedua, Eci meninggalkan keluarga itu saat urusan administrasi berkaitan dengan ijazah diselesaikan, artinya Eci berangkat setidaknya pada bulan Juli di tahun berikutnya, katakanlah misalnya sebelum tanggal 20.
Berdasarkan lini masa itu, terdapat 18 kali tanggal 20 setiap bulannya. Dengan kata lain, kalimat “Artinya, sejak kelas 2 SMP semester kedua, Eci diperkosa 24x oleh ayah angkatnya sendiri” menjadi tidak relevan, atau setidaknya membutuhkan penjelasan lainnya karena kata “artinya” pada kalimat tersebut bermakna ekuivalen dengan kalimat “Ratna keluar kota setiap tanggal 20, entah apa urusannya”.
Cacat logika berikutnya terjadi setelah Eci meninggalkan Bandung, dan Batam adalah lokus kemudian. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Eci telah lulus sekolah menengah atas yang ditempuhnya ketika di Bandung, yang tentu saja disertai pengalaman pemerkosaan karena ia masih berusia di bawah 18 tahun. Premis bahwa Eci berada di Batam dalam keadaan sudah lulus sekolah menengah atas dapat ditarik dari kalimat “Bersama teman-temannya, atas restu orang panti, Eci sampai di Batam” dan kalimat “Jurusan yang ia tempuh di SMK itu tidak terpakai sama sekali, sebab, di Batam, Eci tidak menjadi seorang penjahit.”. Dua kalimat itu menggambarkan adanya dua lokus berbeda yang berdiri di balik masing-masing kalimat.
Premis itu memperkuat asumsi bahwa ketika berada di Batam, Eci telah berusia di atas 18 tahun. Sebagaimana yang terjadi pada kota-kota sebelumnya yang oleh penulis disebut bahwa “di setiap kota yang ia singgahi itu pula, Eci selalu diperkosa” (halaman 7).
Di Batam, Eci bertemu Badrun yang selanjutnya menjadi pasangan hubungan badannya. Namun sampai di titik ini ketika Eci telah berusia dewasa, hubungan badannya dengan Badrun tidak lagi dapat dipandang sebagai pemerkosaan karena mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dalam usia dewasa. Artinya, tidak semua hubungan badan yang terjadi pada cerita berjudul Eci merupakan pemerkosaan.
Persoalan logika kembali ditemukan pada cerita berjudul Maimunah. Pada dialog Dani dengan Maimunah (barangkali dilakukan melalui ponsel karena penulis tidak menjelaskan bagaimana dialog itu terjadi sedangkan kedua tokoh belum bertatap muka) ketika lelaki itu akan berkunjung ke rumah kekasihnya:
“Munah, ada kosong rumah?”
“Kosong, Abang. Datanglah ke mari. Mantan suamiku sudah jarang ke sini.”
“Belum kau bunuh dia? Anakmu di mana?”
“Lagi ngaji, Abang. Ia di surau. Pulang biasanya habis Isya.”
“Oke. Sip.”
“Ditunggu, Abang. Jangan lupa pakai martabak. Maimunah lapar sekali. Malas keluar rumah juga. Apa kata orang, janda kok keluar malam?”
…
Pada bagian bercetak tebal, penulis menggambarkan adanya fungsi kontrol sosial, meski seksis, yakni pada pernyataan tokoh Maimunah “Apa kata orang, janda kok keluar malam?”. Situasi yang tergambar pada dialog tersebut memperlihatkan keadaan di mana Maimunah seorang diri di rumahnya, dan tempus dialog itu adalah malam hari.
Lantas, dengan dasar logika apakah fungsi kontrol sosial berjalan bagi janda yang dipandang tabu untuk keluar malam, namun diperbolehkan menerima tamu lelaki pada malam hari dengan waktu yang cukup pula untuk bermesraan hingga Maimunah melepaskan seluruh pakaiannya?
Kerja intelektual Editor seharusnya sampai pada pemeriksaan logis atau tidaknya cerita yang dibangun penulis, dan permasalahan logis-tidaknya cerita ditemukan hampir pada semua cerita yang terhimpun dalam buku ini. Lain halnya bilamana sebuah buku merupakan antologi bersama di mana kerja Editor sebatas pemeriksa aksara yang kesulitan atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkorespondensi dengan semua penulis. Buku Cara Kerja Tuhan memperlihatkan tingginya syahwat penulis untuk mempublikasikan buku dengan kualitas yang dapat dipertanyakan, sekaligus mempertontonkan etos kerja Editor yang begitu rendah.
Sebagai sesama penulis, Haris tentu juga ingin naskahnya diperlakukan dengan baik oleh Editor yang bekerja tidak sekadar untuk menggugurkan tanggung jawab. Seburuk apa pun naskah, bila telah memasuki ranah industrialisasi, naskah itu layak mendapatkan perhatian dari Editor. Saya mendoakan Hasbunallah Haris tidak pernah bernasib sial seperti Maulidan yang logika penceritaannya buruk dan dieditori pula oleh manusia dengan etos kerja buruk.
***
Beberapa permasalahan yang dibahas dalam ulasan ini hanyalah sebagian kecil dari setumpuk masalah yang ditemukan dalam keseluruhan naskah. Kita tentu sepakat bahwa kerja-kerja kesusastraan seharusnya kerja yang dilakoni dengan benar.
Siapa saja boleh bilang ‘tak ada karya yang buruk, tak ada karya yang baik, semuanya subjektif’. Tapi sebelum mendakwahkan hal-hal gigantik macam itu, baiknya kembali dulu ke dasar buat belajar lagi dasar-dasar penulisan.
Sebagai pembaca yang agak serius, saya juga ingin membaca karya kawan-kawan penulis yang dikerjakan dengan serius pula. Meski karyanya mengandung olok-olok, satir, dan semacamnya, akan lebih mudah dinikmati jika dikerjakan secara sungguh-sungguh, termasuk bersungguh-sungguh dalam mempertimbangkan implikasi politis suatu karya. Untuk itu, penulis tentu harus terus membaca dan belajar menulis karya yang dapat dibedakan dari ceracau.
Tidak cukup hanya bermodal ‘gua orangnya asyik, dan beda sendiri!’ Atau “Abang penulis terkenal, Dek. Mana cukup uang penerbit lokal membayar penulis terkenal sebagai Editor!”.
Sebagai penutup saya ingin kutip kalimat bijak klise. Tapi yang klise belum tentu kehabisan guna:
“Hanya seorang sahabat yang berani menampar wajahmu, menunjuk hidungmu, lalu berkata: kau melakukan kesalahan!”.
Sebagaimana pula petuah yang diajarkan Ali bin Abi Thalib, bahwa sahabat yang baik adalah orang yang berkata benar kepadamu, bukan orang yang terus membenarkan perkataanmu.
Dalam hal ini Maulidan, serta Hasbunallah Haris sebagai Editor tentunya, lebih memahami ajaran itu ketimbang saya. Semoga mereka berdua dapat memahami ulasan saya dalam sudut pandang kawan yang baik.(*)
Identitas Buku
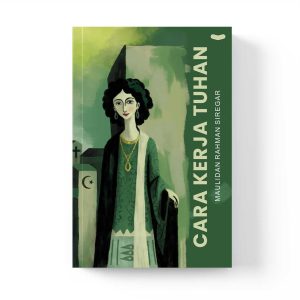
Penulis : Maulidan Rahman Siregar
Penerbit : Rumahkayu Pustaka
Editor : Hasbunallah Haris
Tahun Terbit : Mei 2025 (Cetakan Pertama)
Jumlah Halaman : vi + 140
ISBN : 978-623-8208-70-8


