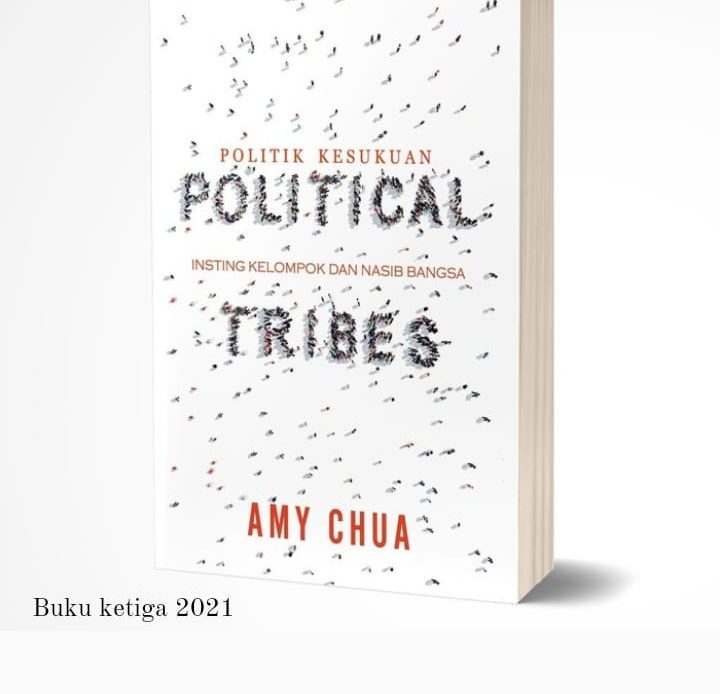
Ketika membaca tulisan Amy Chua secara keseluruhan dalam buku, Politik Kesukuan: Insting Kelompok dan Nasib Bangsa, kita akan disuguhi berbagai kegagalan Amerika Serikat dalam bidang kebijakan politik luar negeri sejak dimulainya era perang dingin. Puncak dari segala kegagalan tersebut dirasakan dan ditangkap oleh Chua, khususnya – semakin menguat – pasca pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Proses kampanye dan kemenangan Donald Trump memantik penguatan tribalisme politik di Amerika Serikat serta kegagalan demi kegagalan dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, khususnya kebijakan soal perang. Direfleksikan oleh Chua dalam tulisannya – sebagai bukti yang ingin ditunjukkan kepada pembaca – bahwa Amerika Serikat kerap melupakan kompleksitas kesukuan dalam mengambil kebijakan. Setidaknya itulah yang disuguhi Chua hampir di keseluruhan isi bukunya. Penuh dengan pesimisme, bahkan cenderung mengarah kepada frustasi dengan sedikit potongan kecil kisah optimisme di dalamnya.
Chua tidak tanggung-tanggung menghakimi dengan menyebutkan “setidaknya selama setengah abad, kita secara spektakuler buta terhadap kekuatan politik kesukuan. Kita cenderung memandang dunia dari segi teritorial negara-bangsa yang terlibat dalam pertempuran ideologis yang hebat – Kapitalisme versus Komunisme, Demokrasi versus Otoritarianisme, Dunia Bebas versus Dunia Jahat” (hal. 2). Fakta tersebut coba diuraikan oleh Chua, mulai dari fenomena yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat yang mengulas kondisi pra dan pasca pemilihan presiden 2016 yang memantik kuatnya wacana dan narasi politik identitas serta populisme, baik di kubu progresif maupun di kubu konservatif.
Pergeseran wajah baru Amerika Serikat yang digambarkan terlihat amat pelik. Walau bermanifestasi dalam wujud konflik konfrontasi yang biner – kulit putih dengan kulit berwarna, kiri dengan kanan, atau progresif/liberal dengan konservatif – nyatanya hal itu tak sepenuhnya berada pada kondisi atau keadaan linear dalam tatanan kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Hal itu diperkuat oleh Chua dengan mengutip pendapat Charles Blow, “bahwa fenomena Trump tanpa belas kasihan dan kita harus tertutup untuk berkompromi dengannya. Namun demikian, jika Anda melihat di luar tajuk utama dan mendengarkan melewati partisan paling keras, anda akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Di seluruh penjuru negeri, orang-orang Amerika biasa melakukan upaya tulus untuk mencapai seberang lorong, memahami sisi lain dan berempati dengan kamanusiaan satu sama lain” (hal. 244).
Hal ini lah yang kemudian memantik berbagai kritik terhadap buku yang ditulis oleh Chua. Chua seolah tak menemukan arah kemana ujung dari tulisannya ini hendak dibawa? ingin mewujudkan tatanan kehidupan Amerika Serikat yang seperti apa? Baik itu dalam konteks pengambilan kebijakan politik dalam maupun luar negeri – Selain menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan aspek kekuatan politik kesukuan. Namun begitu, Chua memiliki pembelaan sendiri dengan menjelaskan, “secara individual, setiap contoh tunggal akan tampak sepele dan sulit untuk membuktikan bahwa mereka mewakili tren. Tentu saja ada suara-suara kuat yang menentang konsiliasi, bersikeras…” (hal. 244).
Sebuah penegasan ulang sebagaimana yang disampaikan oleh Chua saat membuka buku ini pada bagian prolog, bahwa kelompok atau kesukuan dengan beragam perbedaan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang alamiah. Sebagai kodrat kehidupan manusia, seolah Chua hendak menyampaikan kalau konflik adalah bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia yang saling berinteraksi. Sebagai pakar konflik, hal ini merupakan sebuah penegasan yang wajar. Penegasan inilah yang dihantarkan secara implisit lewat kalimat, “Manusia bersifat kelompok. Kita harus menjadi bagian dari kelompok. Kita menginginkan ikatan dan ketertarikan, itulah sebabnya kita menyukai klub, tim, persaudaraan, keluarga. Hampir tidak ada yang menjadi petapa. Bahkan biksu dan biarawan termasuk dalam aturan ini. Tetapi naluri kesukuan bukan hanya naluri untuk dimiliki. Ini juga merupakan insting untuk dikecualikan. Beberapa kelompok bersifat sukarela, beberapa tidak. Beberapa suku menjadi sumber sukacita dan keselamatan; beberapa suku adalah produk mengerikan dari kebencian yang ditebar oleh para pencari kekuasaan oportunistik.” (hal. 1)
“Letupan yang ditangkap oleh Chua diyakininya sebagai gambaran dalam pergeseran wajah Amerika Serikat hari ini serta diakui sebagai pandangannya dalam melihat Amerika Serikat sebagai seorang putri dari seorang imigran” (hal. 243). Sebagai seorang yang memiliki keahlian di bidang konflik etnis dan globalisasi dengan menjadi profesor di John M. Duff Yale Law School, kita dapat memaklumi kalau penjelasan Chua dalam buku ini sangatlah deskriptif – walaupun ada kritik tajam yang disampaikan oleh Ali Khan, seorang profesor hukum emeritus dari Washburn University, perihal ketidakjelasan orientasi dan validasi sumber yang dihadirkan oleh Chua dalam bukunya.
Dengan sangat tajam Ali Khan (2018) mengkritik buku Chua, sebagaimana dikutip dari New York Journals of Books, ia mengatakan, karena kualitas konten bervariasi dari satu bab ke bab lain, tidak jelas apakah buku tersebut ditulis untuk siswa sekolah menengah, mahasiswa, akademisi, politikus, jenderal, atau penumpang yang terdampar di bandara. Buku itu sama sekali tidak ilmiah. Juga tidak mengungkapkan informasi baru yang diambil dari beberapa “dokumen rahasia”. “Buku ini tidak menawarkan analisis empiris atau statistik, juga tidak bergantung pada studi lapangan apa pun yang telah dilakukan penulis di negara-negara yang dianalisis dalam buku tersebut”. Ali Khan secara tidak langsung meragukan kadar akademik dari buku yang ditulis oleh Chua. Sebuah gugatan amat fundamental terhadap sebuah hasil pemikiran dari seorang intelektual.
Tajamnya kritik Ali Khan dalam meragukan kadar keilmiahan karya Chua dapat dikatakan menjadi tumpul seketika saat mantan duta besar Amerika Serikat untuk Afganistan (2014-2016), P. Michael McKinley mengakui kegagalan Amerika Serikat dalam memahami Afganistan. Pengakuan itu dituliskannya dalam sebuah artikel di Foreign Affairs dengan judul, We All Lost Afghanistan: Two Decades of Mistakes, Misjudgments, and Collective Failure (16/8/2021). Artikel yang diturunkan selang beberapa saat setelah Taliban resmi mengambil alih kekuasaan di Afganistan. Mc Kinley menyatakan, “Although we were largely successful in eliminating al Qaeda in the country and reducing the threat of terrorist attacks in the United States, we failed in our approach to counterinsurgency, to Afghan politics, and to “nation building.” We underestimated the resilience of the Taliban. And we misread the geopolitical realities of the region”. Pengakuan McKinley ini seolah menegaskan bahwa buku “Politik Kesukuan: Insting Kelompok dan Nasib Bangsa” merupakan perpaduan antara pengalaman akademik yang tidak perlu diragukan, pengamatan yang amat baik, serta intuisi akademik seorang Amy Chua. Untuk “ramalannya” di buku ini Chua layak disebut sebagai “cenayang”.
Dari situ, kita tidak dapat mengelak kalau buku ini hasil pengamatan dan pengalaman dengan bumbu intuisi akademik. Bisa jadi ini merupakan sebuah kontradiksi yang amat nyata. Pada satu sisi Chua membahas tentang politik kesukuan, sementara di sisi lain yang bersangkutan tidak menyatakan dengan tegas bahwa buku yang ditulisnya merupakan hasil penelitian entografi yang mendalam atau sekadar studi literatur tentang politik kesukuan. Apalagi bab per bab dalam buku ini, Chua begitu fasih menjelaskan kesalahan berbagai macam kondisi serta dampak dari kebutaan Amerika Serikat dalam memahami kekuatan politik kesukuan.
Vietnam, Chua “menuduh” Amerika Serikat buta sejarah perjuangan rakyat Vietnam yang sejak berabad-abad silam sudah anti terhadap China. Belum lepas dari dampak kekalahan pada perang Vietnam, Amerika Serikat mencoba “bermain aman” dengan sekedar membantu logistik perang bagi para mujahid anti-Soviet setelah Soviet melakukan invansi ke Afganistan. Pada akhirnya hal itu disadari oleh Amerika Serikat bahwa mereka sedang membesarkan bibit bagi tumbuhnya Taliban dan Al Qaeda yang kemudian dijadikan sebagai salah satu daftar musuh utama bagi Amerika Serikat.
Tampak tidak belajar dari kesalahan masa lalu, Amerika Serikat kembali mengulang kesalahannya di Irak dan Venezuela. Di Irak, buntut panjang dari kesalahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sebagaimana dituliskan oleh Chua adalah menjadikan negara itu sebagai tempat lahir dan berkembangnya ISIS. Sementara di Venezuela yang notabene merupakan “halaman belakang” bagi Amerika Serikat, mereka terlalu cepat bereaksi terhadap kebijakan dalam negeri dan konflik politik yang terjadi di dalamnya, khususnya dalam memposisikan Hugo Chavez sebagai musuh demokrasi pada awal 2000-an. Vietnam, Afganistan, Irak hingga Venezuela didatangi oleh Amerika Serikat atas nama demokrasi dangan prinsip pencerahan besar – moderenisme, liberalisme, sekularisme, rasionalisme, egalitarianisme, pasar bebas dan lainnya – dengan cara menutup mata terhadap kekuatan politik kesukuan di dalamnya. Hal tersebutlah yang menjadi titik tekan oleh Chua, bahwa kebijakan tidak semata-mata dilaksanakan hanya karena motivasi mengubah atau memperbaiki situasi. Akan tetapi juga perlu memahami kompleksitas kekuatan politik kesukuan di dalamnya.
Tidak sekadar melacak kuantitas keberagaman, namun juga melacak sampai kepada motivasi bertindak dalam keberagaman yang ada, sejauh mana jaringan kekuatan politik kesukuan mampu bekerja, nilai yang menjadi sandaran bertindak setiap individu dalam satu kelompok atau semua anggota, aktor kunci yang menentukan bekerjanya kekuatan politik kesukuan tersebut sampai kepada bagaimana interaksi antar kesukuan yang ada. Kesemuanya harus dilacak jauh ke belakang, sebab apa yang terjadi hari ini dalam realitas politik kesukuan tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang yang telah dibawanya hingga hari ini. Kesadaran semacam ini yang dalam paparan Chua selalu datang terlambat bagi Amerika Serikat.
Salah satu contoh yang dapat ditarik adalah upaya Amerika Serikat dalam menciptakan transisi demokrasi di Irak pada 2005. Pasca pemilu tahun 2005, ketegangan di Irak meningkat dan berubah menjadi konflik sektarian. Korban meningkat dari semua elemen, mulai dari; sipil, kelompok milisi, bahkan tentara Amerika Serikat sendiri. Kesadaran dalam memahami kompleksitas masyarakat Irak yang mulai diubah oleh Amerika Serikat dengan mengubah strategi dan pendekatan, dari militeristik ke pendekatan kultural. Melalui kolonel McMaster pada saat itu, menginstruksikan pasukannya untuk mengambil kursus kilat terperinci dalam kebiasaan, praktik dan sikap kelompok setempat. McMaster melarang tentaranya menggunakan istilah merendahkan seperti “haji” untuk orang Arab dan mengatakan kepada mereka, “Setiap kali Anda memperlakukan seorang Irak dengan tidak hormat, anda bekerja untuk musuh” (hal. 104). McMaster juga meminta beberapa tentaranya mempelajari bahasa Arab, memahami sejarah modern Irak dengan memesan banyak buku The Modern History or Iraq, yang ditulis Phabe Marr. Selain itu pasukannya juga dikirim berinteraksi dengan masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan sekaligus mencari tahu dinamika kelompok dan struktur kekuasaan Tal Afar. Menjumpai dan menghabiskan puluhan jam dalam seminggu untuk bertemu para syekh Sunni maupun syekh Syi’ah. Akhirnya, McMaster mulai membangun aliansi dengan para pemimpin suku yang penting, dengan kesimpulan; satu-satunya cara untuk mengalahkan pemberontakan adalah membuat Sunni dan Syi’ah bekerja bersama melawan para ekstrimis (hal. 104).
Dari gambaran di atas, meskipun hampir keseluruhan isi buku berisikan gambaran kegagalan akibat buta terhadap kekuatan politik kesukuan, Chua tidak lupa memberikan contoh warisan keberhasilan betapa berharganya memahami kekuatan politik kesukuan dalam membuat dan mengeksekusi kebijakan. Walau di sisi lain, kita juga mempertanyakan sikap Chua tentang gagasan identitas nasional yang dibawa negara dengan watak yang cenderung unitarian dan penyeragaman, serta tuntutannya terhadap betapa pentingnya memahami kekuatan politik kesukuan sebagai gambaran keberagaman dan penghormatan terhadap hak-hak rekognisi kelompok. Namun begitu, Chua telah mengajarkan kita tentang pentingnya memahami kondisi di mana kebijakan itu akan dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan menstrukturisasi atau menginstitusionalisasi gagasan ideal perihal kebijakan apa yang akan diambil atau dilaksanakan. (*)
Referensi:
Amy Chua, Politik Kesukuan: Grup Insting dan Nasib Bangsa, terjemahan oleh: Muhammad Iqbal Suma, Manado: Globalindo, 2020.
Ali Khan, A Book Revie; https://www.nyjournalofbooks.com/book-review/political-tribes
P. Michael McKinley https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-16/we-all-lost-afghanistan-taliban
Identitas buku:
Politik Kesukuan: Insting Kelompok dan Nasib Bangsa
(Political Tribes: Group Instinc and the Fate of Nations)
Amy Chua
Manado: Globalindo, 2020
Penerjemah: Muhammad Iqbal Suma


