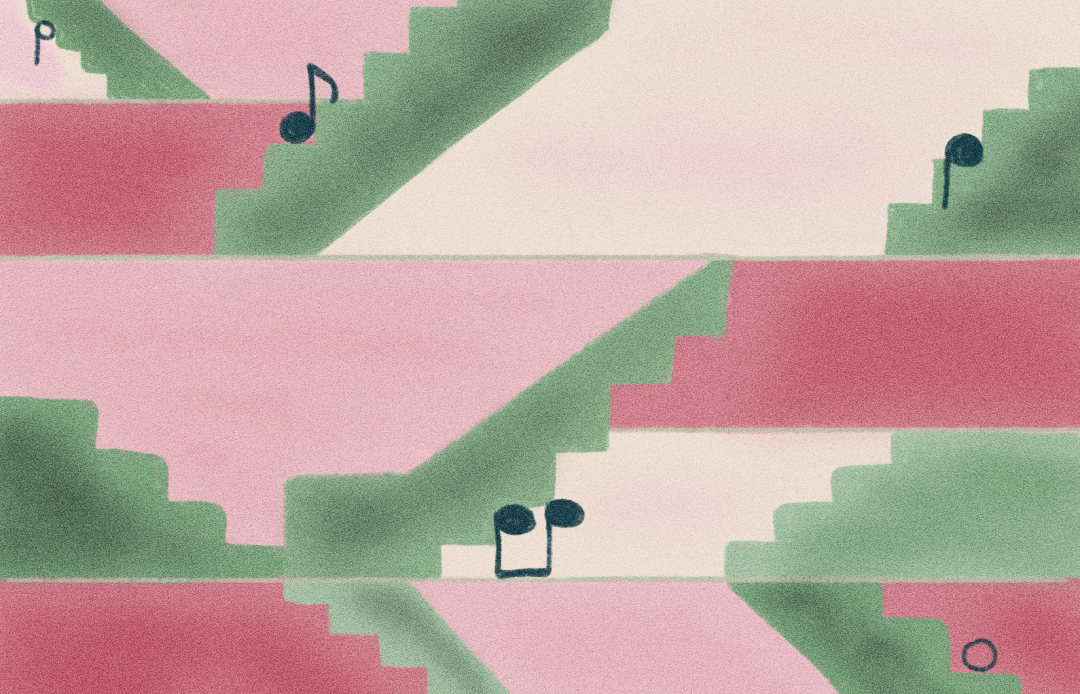
Reductio ad absurdum, “sesatkanlah kekeliruan berpikir agar kau temukan saripati kebenarannya”. Demikanlah analogi yang aku pinjam dari datuk Tan Malaka dan tuan Aristoteles. Sebagaimana tangga nada, naik dan turun adalah dualitas perlangkahan bunyi dengan getaran yang saling berdialog. Bukan bunyi yang manut dan mengiya-iya. Justru mereka berada pada posisi yang selalu berhadap-hadapan. Dengan sifat bunyi yang unik, di dalam tataran musik, keduanya seringkali berjumpa secara “enharmonik” dalam keterpilinan nada-nada kromatikanya. Walaupun begitu, getaran keduanya tetaplah bergerak dari sumbu masing-masing. Satunya, punya gerakan naik yang tajam (sharp), sedikit kering, tegas, dan berwibawa. Ia seperti anggang terbang bersitumpu dan menusuk pintu-pintu langit keberbunyian. Di sisi lain, gerakan satunya lagi melayang turun dengan kepipihan (flat), sedikit basah, lentur, dan sederhana. Ia pun seperti anggang hinggap mencakam, dan menyejukan hamparan bumi di keberbunyiannya.
Dalam perkembangan musik Barat, terutama sejak masa Yunani yang berlanjut ke Gregorian Chant, kedua gerakan di atas bersumber dari tetrachord, yakni skala musik empat nada. Dari skala tersebut terdapat dua (Dia) jarak interval yang boleh dikatakan bulat penuh. Dan, satu interval dengan jarak 1/2. Bilamana anda mulai dari tonika C, maka gerakan naiknya C-D-E-F (konsep Gregorian, Medieval, atau musik Abad Pertengahan). Skala seperti ini dirinci jadi seperti ini: 1,1, 1/2. Berbeda halnya jika anda mulai dari C dengan gerakan turun (konsep Yunani). Skalanya digambarkan seperti ini: C-b-a-g dengan jarak 1/2, 1, 1.
Bagi kawan-kawan musisi, tentu sebahagiannya (musisi jazz dan musik serius), aku rasa paham dengan apa yang aku maksud di atas. Dari sistem tetrachord tersebutlah yang disebut sebagai Dia (siklus lima atau cycle of fifth) berkembang jadi Diatonis dengan turunan beberapa mode dan scales, seperti; ionis (otentik mayor), doris, frigis, lidis, miksolidis, aeolis (otentik minor), dan lokris.
Adapun terjadinya perbedaan sistem jenjang dan tangga nada tersebut di Barat, disebabkan oleh beberapa faktor. Terutama irisan banyak hal dalam peradaban Yunani (filsafat) dan peradaban Romawi (kekuasaan). Irisan sistem nada Yunani yang bertangga turun, ditinjau dari kesejarahannya ‘sempat’ meredup di Barat. Namun dari literasi kajian Islam, menyebutkan bahwa filsafat Yunani yang meredup, disebut kembali bersinar di tangan ilmuan Islam, seperti: Al Kindi, Al Farabi, Ibnu Sina (Avecenna), Ibnu Rusyd (Averroes), dan tokoh lainnya. Selain matematika, fisika, dan lain sebagainya. Ilmu musik yang pernah berjaya di masa Yunani kembali disegarkan piranti Al Musikanya oleh ilmuan Islam. Sementara, di Barat sendiri, kedudukan seni bunyi Yunani beralih cara dan digantikan oleh hirarki berjenjang naik di masa peradaban Romawi.
Berdasarkan beberapa sumber musik yang aku baca, katanya telah terjadi ‘kekeliruan’ dalam memaknai pergerakan interval dan tonikanya. Peradaban musik Yunani yang sebelumnya mendasari pangkal bunyi di nada “Mi”, lalu bertangga turun menjadi Mi-Re-Do-Si. Urutan tersebut jika dilihat dari aspek jarak interval, maka penggambarannya adalah 1, 1, 1/2. Anicius Manlius Severinus Boethius, seorang ahli dari Romawi, kemudian menerjemahkannya secara terbalik menjadi Do-Re-Mi-Fa (1, 1, 1/2) berjenjang naik. Menurutku itu terjadi karena ia hanya melihatnya dari kacamata jarak interval semata.
Pradugaku, sistem Romawi yang dianggap oleh para musikolog tumbuh dari ‘kekeliruan’ inilah yang di masa selanjutnya dikenal sebagai musik modal dan terus berkembang menjadi musik tonal. Saat ini, sistem tonal juga bisa anda perhatikan dalam industri musik Pop. Dan, di Abad 20, musik Barat berkembang lagi menjadi musik postonal (musik serius dengan konotasi komposisi yang rumit dan butuh renungan). Di masa postonal ini pula, sistem Yunani yang sempat meredup perkembanganya di Barat, disebut-sebut kembali bersinar. Tentu saja, dengan resepsi, tafsir-tafsir dan pendekatan terbaru para komposer Abad 20. Sebuah ‘Musik Baru’ dengan tataran dan konsep yang lebih mengedepankan emansipasi disonansi ketimbang konsonan.
Disonansi, yang sebelumnya dianggap distorsi, lewat penolakannya, seakan mendapat ruang baru ‘melawan’ sistem harmonisasi konsonan di era musik Klasikal. Eksistensi bunyi disonansi dianggap seirama dengan pertumbuhan filsafat eksistensialis di Abad 20. Arti katanya, mengada dan mewaktunya disonansi, telah meruntuhkan keberadaan musik tonal yang dulunya cenderung menghegemoni kadens (kalimat akhir lagu yang mana esensial bunyinya diwajibkan pulang ke pautan tonikanya). Dengan demikian, keberpusatan musik Klasik yang berjaya di rentang Abad 17, 18, dan 19 pun menjadi buram. Dalam hal ini, disonansi berkontribusi besar atas terjadinya keburaman tersebut. Ia diidentikan dengan ‘kekosongan’, bunyi gadungan, bluenote, tritone, sruti, pakiak saluang. Ambiguitas musiknya tidak lagi dikendalikan oleh satu kekuatan. Justru, melalui ambiguitas tersebut, disonansi berempati terhadap yang liyan. Sebuah getaran asing yang menjadi medan bunyi liar tak bertuan. Ketidakbertuanan ruang disonansi tersebutlah, yang aku sebut sebagai medan improvisasi yang membuka portal bunyi mistik non diatonis. Terutama, eksistensi suara-suara Timur untuk bermain di gelanggang yang sama.
Mistikal Bunyi Non-diatonis
Menariknya, sistem disonansi Abad 20 tersebut di atas, aku rasa, citarasa getarannya beririsan dengan sistem nada-nada kesukuan di luar konteks Barat yang diatonis. Katakanlah di Asia. Di wilayah ini, dalam ketradisian seni bunyinya, sepengetahuanku tidak mengenal sistem tetrachord. Sebagaimana contoh sistem anhemitonc-pentatonic yang tersebar di beberapa teritori peradaban kuno: Asia (Tiongkok, Jepang, Asia Tenggara), Afrika, Mesir, Anglo, Siberian, dan Maya. Menurut beberapa sumber, terutama di Asia Timur dan Tenggara, ada yang mengatakan, ‘alamlah’ yang diperkirakan turut mendorong sublimasi bunyi kemanusiaan. Suara-suara masyarakat komunal primitif yang lantang menyembulkan keindahan nyanyian anhemitonc-pentatonic dari kedalaman batin.
Sebagai contoh, silahkan anda ambil sampel dari dendang Minangkabau, tembang Sunda, sinden Jawa, dan nyanyian lain di Timur. Umumnya, mantra, doa, dan zikirnya bercorak melisma dan sullabe yang dimulai dari nada nada puncak, lalu perlahan-lahan turun melandai ke bawah. Hal ini ditinjau dari satuan hertz maupun logaritma cent-nya, pada dasarnya berbeda jauh dengan sistem equal temperament atau just intonation yang berlaku dalam pengukuran musik Barat. Sehubungan dengan fenomena bunyi yang dianggap liyan (bunyi asing jika diukur dengan kacamata Barat) inilah, aku amati, seperti dekat dengan ritus keberserahan bunyi ke pemilik semesta bunyi. Sebuah kedalaman bernyanyi yg saling berbagi, peduli, dan tolong menolong. Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam spirit Austronesian, Mongolid, dan Tar-tar Lautan: Suara-suara Murba! Walau ini masih asumsi, tapi, begitulah yang aku rasa sensasinya bergetar secara berulang-ulang. Terutama ketika magma bunyi tersebut ditelusuri kemisteriusannya lewat riset, pengujicobaan di labor, maupun sebagai partisipan aktif.
Sehubungan dengan itu, di masa datangnya pengaruh Hindu, Budha, dan Islam ke tanah Austronesia: Tanah para Tualang Mamak (Kedatukan dan kedatuan), pun bisa disebut sebagai masa pertemuan dari dualitas bunyi yang menyembul dari bumi, dan bunyi yang menitah dari langit. Bebunyian masyarakat Tualang Mamak yang dulunya berdendang duduk bahamparan. Dikarenakan masuknya pengaruh nyanyian ‘Sampradaya‘ (sistem keguruan, Parayogi dan Banthe Hindu-Budha), dan irama para ‘Mursyid‘ (pengaruh Islam), lambat laun, keotentikan nyanyian anhemitonic-pentatonic pun berarsiran dengan ragas India, dan maqamat qiraah Timur Tengah. Ia menubuh dalam rambatan kultur bunyi yang sayup-sayup sampai, bersemilir di dedaunan Madang dan Jilatang. Ia berkisah di hamparan persawahan dan pantai-pantai. Ia tiupkan kediriannya masuk ke pendengaran para bocah yang disenandungi buai kaum ibu, senandung negeri Puan: Suara-suara Matrilini!
Coba saja perhatikan dengan seksama dan dengar dengan hati khusyuk nyanyian Slendro di Jawa. Ragam nyanyian seperti ini juga berkembang di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya di Indonesia. Bahkan tersebar ke banyak peradaban kuno yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Demikian pula irama Pelog. Selain di Jawa dan Bali. Irama nyanyian pelog pun bisa ditelusuri dalam nyanyian Karnatik di India Selatan. Begitupun Madenda. Skala yang berkembang di Sunda ini juga tersebar di Bukit Barisan Sumatera. Di Jepang dikenal sebagai Hirojoshi. Bahkan, aku sedikit curiga. Irama madenda ini serasa terhubung dengan ratapan Ilau di Minangkabau dan mantra-mantra kuno Zarathustra: doanya para Majusi!
Bukankah di ketiga skala nada di atas, di Indonesia, tampak bahwa menjadinya bebunyian tersebut bukanlah abrakadabra. Ia mewujud oleh adanya sentuhan-sentuhan dan pertalian peradaban yang sophisticated. Keotentikan yang bergumul dengan ketidak-otentikan. Ia melahirkan kelindan bunyi antara irama kemasyarakatan dan irama sufistik dalam peraduan keras-lunak di tataran sunyi, kosong (emptiness). Sebuah tataran Saaluang-Sabunian dari getaran longang/kosong (empty) yg bermukim di rayuan pulau kelapa, ‘kemenjadian’ dengan daya ledak atomik.
Namun, sungguh sayang di sayang. Kemantagian bunyi seperti yang aku narasikan di atas, lambat laun terkikis oleh datangnya Anggang baru dari Barat. Tidak saja rempah dan kekayaan alam lainnya yang mereka gerogoti. Nyanyian kultur para-budi, para-datuan pun dihisapnya sampai ke akar terdalamnya. Di kafetaria, di pasar rakyat, di dalam transportasi, di hotel, di rumah, di mana saja, bahkan di kamar mandi, dan ruang tidur yang sangat privasi sekalipun, ia menyusup sedemikian rupa. Kita dilenakan oleh budaya Pop, yang cepat saji, yang menang di kemasan bunyi. Kita pun terlena! Itu yang aku khawatirkan. Kita menjadi asing dengan bunyi diri. Kita terjebak dengan rasa bangga yang naif. Sementara, di depan kita, kolonialisasi bergerak senyap. Ia nina bobokan nyanyian semu di hampir keseluruhan sendi keberbunyian kita. Saat ini semua itu tengah berlangsung, dan terus menjalar rimpang di lokus-lokus kebudayaan Nusantara.
Apakah kita mesti menolak mentah-mentah citra Barat yang disebarkan lewat kolonialisasi musikal? Bagiku tidaklah sejauh itu. Mana yang baik bolehlah kita serap. Misalnya, strategi penciptaan seni bunyi dengan turunan akademisnya. Aku rasa, kontribusi pengetahuannya, di sisi lain, bermanfaat pula untuk menelaah sumber-sumber musikalitas kita. Bagiku, dipadupadankan kontennya, mungkin adalah jalan terbaik. Jalan pertemuan baru (intersection of logic) antara ‘kesadaran’ Timur-Barat. Diyakini, sebuah rambatan (propagation) bebunyian masa depan, berpotensi memunculkan novelty bunyi yang akan ‘hadir’ dalam ruang dialektika permusikan dunia. Sebuah getaran rhizomatic yang kerimpangan bunyinya berjenjang naik bertangga turun. Terserah, apapun bentuk pengekspresiannya. (*)
Ilustrasi Amalia Putri


