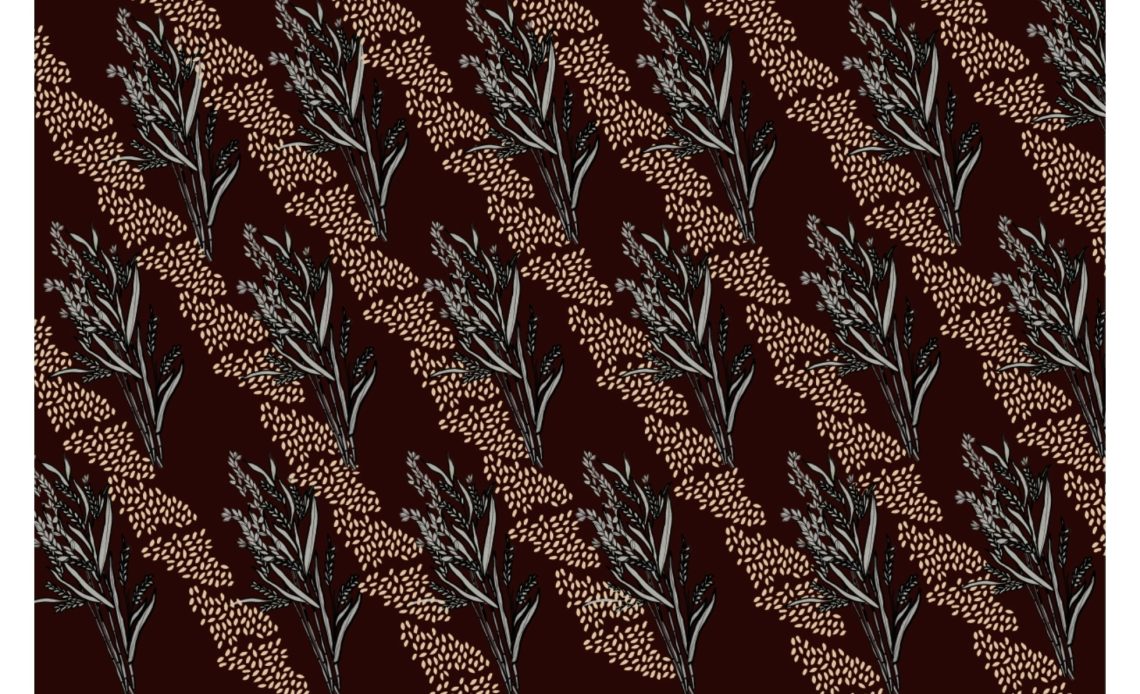
Li, Semedi dan Layang-Layang tak Bertali
Bicara perkebunan kelapa sawit di Riau dan hubungannya dengan petani kecil, rasanya kita perlu menjenguk catatan Tania Murray Li dan Pujo Semedi dalam buku terbaru mereka, Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit (2022, cet. Ke-2, 2025). Menurut mereka, statistik kelapa sawit Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa empat provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, memiliki 7 juta hektar kebun sawit, 53 persen di antaranya merupakan milik perkebunan, dan 47 persen milik petani kecil. Riau, tulis mereka, adalah provinsi dengan porsi petani kecil tertinggi, mencapai 69 persen (2004: 39).
Jika petani kecil disebut sebagai pemilik lahan, yang di Riau jumlahnya mencapai 69 persen, maka dapat diasumsikan hampir separuh lahan sawit di Riau merupakan milik masyarakat, bukan perusahaan. Bila ini benar, mungkin “petani kecil” yang dimaksud berada di bagian Riau yang lain, bukan di kawasan masyarakat adat Talang Mamak Indragiri, setidaknya di Kecamatan Rakit Kulim dan Siberida. Ini mengingat di kawasan tersebut sepanjang mata memandang, semua lahan milik perusahaan.
Dalam istilah Tania Li sendiri saat menggambarkan perkebunan di kawasan Tanjung (sebuah nama samaran di Kalimantan Barat),“Lima perkebunan menghampar tempel-menempel di wilayah seluas 65.000 hektar (2023: 41).” Di kawasan Talang Mamak idem ditto, sami mawon alias sama saja. Di sini setidaknya empat perusahaan “menghampar tempel-menempel” di wilayah seluas ribuan hektar.
Profil petani kecil yang disebut Li dan Semedi memiliki “produksi mandiri”, juga tidak tersua di kawasan Talang Mamak. Li menyebut, sebagaimana di masa kolonial, perusahaan perkebunan dan para kroninya memiliki insentif untuk menekan produksi mandiri petani kecil karena petani kecil dianggap menggembosi monopoli mereka atas lahan dan tenaga kerja, serta mengancam narasi bahwa hanya perusahaan perkebunan yang mampu berproduksi dengan efisien. Namun berlawanan dengan narasi ini, banyak penelitian mengonfirmasi bahwa petani kecil dapat menghasilkan panen sawit per hektar sebanyak panen kebun milik perusahaan. Lagi pula, “tidak ada kekhususan agronomis sawit yang membenarkan perlunya kehadiran dominan perkebunan sebagai pola pembangunan,” tulis Li dan Semedi (2023: 37).
Di Talang Sungai Parit, masyarakat adat Talang Mamak tidak mampu berproduksi mandiri, apalagi menggembosi monopoli perusahaan, alih-alih semakin memperkuat narasi timpang perusahaan.
Lebih lanjut Li dan Semedi juga menyebut bahwa budidaya sawit tidak rumit (….) sehingga tidak ada persoalan teknis sekala usaha tani. Pekerja menyiang gulma, memumpuk dan memanen secara manual. Petani mandiri yang punya akses ke bibit unggul dan pupuk serta merawat kebun dengan tekun bisa mencapai panen per hektar setara atau bahkan lebih tinggi daripada panen kebun perusahaan; biaya produksi per ton mereka juga lebih rendah karena mereka tidak perlu membayar manajer, mandor dan satpam (2023: 38).
Barangkali Li dan Semedi harus memeriksa kembali Cramb dan McCharty yang diacunya, karena persoalannya tidak sesederhana itu. Apalagi jika dilihat dalam konteks orang Talang Mamak yang tak punya akses kepada bibit pilihan atau bibit unggul, pupuk, bahkan lahan. Hal mana dapat dicermati dari catatan saya terdahulu atas keluarga Imron yang memiliki perkebunan sawit secara memprihatinkan (Garak.id, 9 Mei 2024).
Imron merupakan pemuda Talang Mamak yang bersama kakak dan adik-adiknya diajak ayahnya bersama ibu mereka tinggal di kebun, di Dusun Satu Desa Talang Sungai Parit. Mereka tinggal di atas rumah kayu seluas 8 x 9 meter yang bangunannya sebaik rumah-rumah di pusat kampung. Tapi melihat letaknya di tengah kebun sawit dan mencapainya harus melewati jalan kebun yang jauh, maka secara “fungsi” rumah itu dibuat untuk menunggui kebun sawit mereka seluas 5 hektar.
Sayangnya dari kebun seluas itu, mereka hanya bisa panen paling banyak 500 kg sekali tiga bulan. Itu karena mereka tak sanggup beli pupuk yang mahal, sementara pupuk organik juga sulit mereka dapatkan. Lebih parah lagi, ketiadaan akses untuk mendapatkan bibit unggul membuat sawit yang mereka tunggui seolah menyodorkan kesia-siaan. Selain harga bibit unggul mahal, pengetahuan mereka atas bibit juga kurang.
Pihak perkebunan—yang notabene menjanjikan akan menampung hasil kebun penduduk—serta pihak terkait seperti Dinas Pertanian, tak pernah mendampingi petani dalam hal memilih bibit. Banyak penduduk membeli bibit KW, dan setia merawat dan menungguinya sampai panen, tanpa pernah membayangkan bahwa bibit sawit yang mereka tanam bukan yang terbaik. Itu baru diketahui saat panen yang tentu saja sudah terlambat.
Di bagian lain, Tania Li dan Pujo Semedi menyebut bahwa persoalan teknis utama kebun sawit adalah pabrik pengolah dan transportasi. Sebab pohon sawit menghasilkan tandan buah segar yang harus dipanen setiap dua minggu dan diproses di pabrik dalam jangka 48 jam sebelum kualitas minyaknya turun. Jalur jalan yang lancar dan kapasitas pabrik pengolah yang memadai menjadi urusan genting di sini (2023: 37).
Di kawasan Talang Mamak terdapat beberapa pabrik sawit, meski kondisi jalan tak semuanya baik, tapi jarak yang tak terlalu jauh seharusnya mempermudah mereka menjual hasil panen. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Adalah wajar sebagai petani kecil mereka tak memiliki moda transportasi sendiri, dan karenanya mereka menjual sawit melalui pengepul (tentu dengan harga miring).
Nah, pihak pengepul inilah yang harus membawa barang dagangnya berputar-putar mencari harga yang paling baik di antara pabrik, dan itu artinya menambah biaya angkut, apalagi harus menempuh jalan yang rusak. Sedihnya, semuanya dibebankan kepada petani kecil melalui penentuan harga jual. Posisi mereka lemah, sebab umumnya petani sawit di Talang Sungai Parit bukanlah petani inti maupun plasma. Petani inti/plasma tentu terikat kontrak dengan perusahaan sebagai jaminan menampung hasil panen dalam skema kerja sama mutualisma. Petani sawit Talang Sungai Parit semata tergantung kepada pengepul.
Di sisi lain, jelaslah mereka tidak termasuk kategori petani mandiri, sekalipun bebas menjual hasil panen ke mana pun. Mereka lebih tepatnya dapat diibaratkan sebagai layang-layang tidak bertali. Mereka memang bebas, melayang-layang di awan, tapi tak punya ikatan apa pun dengan sistem di bumi yang dapat memberi mereka kepastian.
Jika dalam kategori Li dan Semedi, petani mandiri termasuk warga pendatang yang membeli lahan dari pemilik tanah adat, maka itu pun tak tersua di kawasan Talang Mamak sebab tanah adat bagi mereka adalah milik kolektif yang tak mungkin diperjualbelikan. Dalam kenyataannya itu pun telah diambil perusahaan atas nama HGU.
Yang bisa mereka jual—dan ini memang banyak terjadi—adalah jatah tanah warisan, meskipun secara umum itu juga bagian dari tanah adat; namun dari segi kepemilikan sudah berada di tangan masing-masing keluarga. Mereka yang membutuhkan modal untuk ikut bertanam sawit, atau keperluan mendadak seperti ada anggota keluarga yang sakit, dan bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, terpaksa melepas satu-dua tumpak lahan yang dimiliki, dijual dengan harga miring kepada warga pendatang. Warga pendatang sekarang memiliki lahan kebun mandiri di tengah masyarakat suku tuha yang susah-payah hidup sehari-hari ini, jauh dari mandiri.
Dalam catatan Li dan Semedi lebih lanjut, adakalanya warga pendatang merambah hutan primer dengan dukungan pejabat setempat, manajer perkebunan, profesional perkotaan dan pengusaha yang membeli tanah dan memperkerjakan manajer untuk menjalankan perkebunan tanpa izin. Termasuk pula di sini para pemilik tanah adat yang menanam sawit di lahan mereka sendiri sebagai sumber penghasilan rumah tangga yang menguntungkan (2023: 40).
Dari sini terlihat bahwa apa yang dikaji Li dan Semedi di Tanjung, Kalimantan Barat, secara khusus tidak selalu relevan dengan kawasan lain. Di kawasan Talang Mamak, bahkan dalam banyak hal, amatan mereka mengandung banyak ironi. Selain ironi yang disebutkan di atas, di bagian akhir ini juga dapat dicatat bahwa masyarakat asli tak lagi punya hutan adat, bahkan untuk perkebunan sendiri mereka mengubah kebun-kebun sebelumnya, karet atau padi, menjadi kebun sawit dengan luasan tak seberapa.
Tapi mengenai warga pendatang yang membeli lahan justru benar. Banyak petani dari daerah luar yang punya kebun pribadi di kawasan Talang Mamak. Mereka dimudahkan karena diterima bekerja di pabrik atau karyawan perusahaan. Waktu di luar kerja mereka gunakan mengurus kebun sendiri yang dibeli dengan harga “murah-meriah” dari penduduk lokal. Ini terutama dilakukan orang Batak yang dalam konteks fenomena perkebunan sawit disebut Hary Santoso (2023) sebagai “gerobak pasir”.
Nasib Padi Ladang dan Ladang Padi
Sepanjang sejarah Republik, perhatian atas eksistensi padi ladang nyaris tidak ada. Apa yang disebut penghasil padi pastilah mengarah kepada sawah. Menurut Dr. M.M. Sri Setyati Harjadi, pertanian ladang merupakan sistem yang paling tidak berkembang, jika dibandingkan dengan sistem tegal pekarangan dan sistem sawah. Sistem ladang masih berupa peralihan dari tahap pengumpul ke tahap penanam. Pengoalahan tanahnya minim, produktivitas berdasarkan lapisan humus dari hutan, meskipun ketersediaan sumber tanah disebut tak terbatas—sebutan yang kini juga tidak tepat sebab tanah perladangan terus bersaing dengan tambang dan perkebunan besar. Sistem tegalan disebut cukup berkembang dengan pengelolaan intensif dan bersinambung. Sedangkan sistem sawah memiliki teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam pengolahan tanah dan air (1980: 20).
Tak heran, fokus negara lebih banyak kepada persawahan, berikut pengadaan infrastruktur dan program-program pangan. Waduk dan bendungan-bendungan besar dibangun demi mengalirkan air irigasi. Program intensif pertanian, teknologi benih, koperasi, peran serta Bulog, sampai kepada proyek cetak sawah baru, semua merujuk kepada sawah sebagai penghasil padi utama. Maka kebijakan pertanian pangan menyangkut tanaman padi selalu diarahkan kepada padi sawah, bahkan sejak zaman kolonial sebagaimana dapat kita baca dalam Budidaya Padi di Jawa (1986) suntingan Sajogyo dan William L. Collier.
Salah satu program besar Politik Etik pada setengah akhir pemerintahan Hindia Belanda adalah irigasi, selain edukasi dan transmigrasi. Irigasi merujuk kepada sawah dan juga perkebunan. Dua program lainnya, yakni edukasi (pendidikan) dan transmigrasi secara tidak langsung juga berkaitan dengan sawah dan perkebunan. Transmigrasi memindahkan masyarakat dari Jawa ke Sumatera, ke lahan-lahan yang menyediakan sawah dan perkebunan, dan para operatornya, yakni mandor-mandor dan administratur dihasilkan di dunia pendidikan.
Di tengah itu semua, padi ladang menjadi cerita yang sayup-sayup sampai, hanya diketahui dan dijalani oleh keluarga-keluarga yang berbasiskan masyarakat adat. Jika pun ada berbagai liputan tentang ritual menanam atau memanen padi sebagaimana liputan fenomenal sepanjang masa atas saren taun masyarakat Badui atau ritual basamuk umang (merayakan terbitnya bulir padi) di kalangan orang Dayak Meratus di Loksado atau pesta panen di Long Peleban, hulu Sungai Kayan, semua itu berhenti pada eksotisme tradisi lokal. Jarang mengulik ada apa di sebalik tradisi bertanam padi ladang dan apa masalah yang mereka hadapi.
Orang merasa puas hanya dengan menyaksikan ikatan-ikatan padi diusung sepanjang jalan dusun menuju lumbung sebagai simbol kemakmuran. Tak ada yang bertanya lagi apa dan bagaimana padi ladang ditanam dan sampai menghasilkan. Lebih dari itu, apakah benar masyarakat adatnya makmur, terutama jika kita mengacu lambang padi dan kapas di perisai Burung Garuda. Apakah secara sandang dan pangan warga benar-benar sudah sejahtera dan beroleh keadilan sosial yang setimpal?
Atas kenyataan tersebut, tentu saja pola bertanam padi seperti di kalangan suku Talang Mamak akan tersingkir dari perhatian publik dan pemerintah. Padi atau beras sebagai sumber pangan utama seolah dianggap selesai dengan ketersediaan beras di pasar. Padi ladang dianggap sebagai tambahan belaka dari usaha pengadaan dan persediaan pangan. Padahal, padi ladang pernah menjadi andalan pangan masyarakat adat, dan pengabaian atas eksistensinya telah menyebabkan padi ladang jauh berkurang dan bahkan menghilang.
Bagi masyarakat Talang Mamak sendiri, pilihan atas padi ladang, dan bukan padi sawah, berkait erat dengan lingkungan hidup mereka di kawasan hutan, sekalipun itu hutan daratan rendah yang sebagian bahkan berupa rawa gambut. Aktivitas bertani mereka berlangsung di tanah kering berupa kebun dan ladang (huma). Sawah hampir tidak dikenal meskipun dalam jenis padi ladang yang mereka tanam ada juga jenis padi paya yang sengaja ditanam di lahan basah, di sepanjang anak sungai atau rawa-rawa.
Jika kita bicara ladang atau huma, tentu saja kaitannya sangat erat dengan hutan sebagai sumber pengadaan lahan. Pola berladang pindah dengan membuka hutan seperti pada masa hutan ulayat masih jaya tak mungkin lagi dilakukan. Hutan telah lebih dulu habis seiring munculnya produksi kayu besar-besaran oleh perusahaan pemilik HPH. Setelah itu, sisa hutan dipungkasi oleh perusahaan perkebunan yang kali ini memegang surat sakti bernama HGU.
Akibatnya masyarakat adat yang mengandalkan hutan untuk aktivitas hidupnya, tak mungkin lagi mengadakan pola berladang seperti warisan moyang. Mereka mulai membangun pola menetap dengan lahan yang tetap. Lahan itu kadang terdiri dari beberapa tumpak. Posisinya ada yang dekat dari rumah di kampung sehingga nantinya berubah menjadi kebun, namun ada juga terletak jauh di bekas kawasan hutan yang masih disebut ladang. Toh, lahan yang tinggal tak seberapa itu pun tak lepas dari incaran perusahaan atau calo tanah.
Padi ladang bisa tumbuh di lahan kering tanpa irigasi dan bersifat tadah hujan. Tahan hama dan penyakit, ramah lingkungan karena tak perlu pupuk dan pestisida. Biaya produksi rendah. Cocok untuk pertanian berkelanjutan dan bisa dipakai dengan pola tanam tumpang sari. Itulah antara lain keunggulan padi ladang yang terbukti lestari sejak beratus tahun silam tanpa keterlibatan tangan pemerintah dengan seabreg program Revolusi Hijau-nya.
Ladang atau kebun yang sudah penuh oleh tanaman tua seperti karet, dan belakangan kelapa sawit, tentu tak bisa lagi ditanami padi karena tanah telah sepenuhnya tertutup tajuk pohonan. Tapi biasanya orang Talang Mamak sengaja menyisakan sekian luasan lahan untuk bertanam palawija seperti sayuran dan itu pula yang sekali setahun ditanami padi.
Dari proses ini terlihat bahwa lahan padi kian menyempit, dan proses yang sudah sulit itu pun dipersulit dengan memutus mata rantai proses berladang yang selama ini diwariskan: dilarang membakar lahan. Dalam kondisi itu, praktis warga Talang Mamak merupakan petani kecil dengan lahan terbatas, dan tak mungkin lagi membuka lahan baru karena hutan sudah berubah menjadi lahan HGU untuk perusahaan perkebunan besar. Bahkan gerak-gerik mereka dibatasi untuk memperlakukan lahan mereka sendiri sesuai kebijakan dan tradisi lokal.
Di Talang Mamak, sebagaimana kita tahu, keterhalangan berladang padi bukan semata soal lahan. Warga sebenarnya masih antusias bercocok tanam padi di huma-ladang. Sebab untuk diketahui, dan ini sudah sering saya ulangi, padi ladang bagi orang Talang Mamak selain buat kebutuhan pangan, juga untuk kebutuhan ritual.
Dulu, mereka tidak perlu membeli beras. Hasil panen padi di ladang mereka simpan di lumbung-lumbung kencana atau di atas rumah, lalu ditumbuk sesuai kebutuhan. Untuk ritual, sebutlah upacara naik tanah atau tepung tawar (upacara kematian), kelahiran atau begawai (pernikahan), perangkat adat dan pemimpin upacara seperti batin, dukun, balian dan kumantan memerlukan beras dari padi ladang untuk sesaji dan persembahan—sekaligus buat hidangan dalam upacara tersebut. Jika beras dari padi ladang dianggap tak mencukupi untuk para tamu atau undangan, minimal pihak dukun dan jajarannya harus mengecap nasi dari beras padi ladang. Itu baru bisa dianggap memenuhi syarat rukun ritual.
Kini proses berladang (behuma) mereka terbentur larangan membakar lahan yang dikeluarkan pemerintah. Larangan itu, sebenarnya berlaku di seluruh Indonesia sebagaimana digambarkan Budi Kurniawan, seorang aktivis lingkungan di Kalimantan Selatan (Radar Banjarmasin, 23 Oktober 2019).
Menurut Budi, larangan itu merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua undang-undang itu mengancam pembakar lahan dengan sanksi kurungan 3-15 tahun penjara dengan denda Rp 1,5-15 miliar. Selain ketiga Undang-Undang di atas, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 62 adalah pasal yang membolehkan masyarakat membakar lahan untuk perladangan dengan luas tak lebih dari dua hektar dengan memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing masyarakat, akan tetapi tak pernah dimunculkan.
Petugas pemerintah kemudian mengartikannya secara “pukul-rata” antara perusahaan besar dan petani kecil. Ini menyebabkan warga tak bisa membakar lahan untuk proses bertanam padi, sebagaimana telah saya tulis dalam cerpen “Dilarang Menyalakan Api di Ladang Padi” (Jurnal Maarif, Vol. 19 No. 1/2024):
DI sepanjang jalan ke ladangnya, Pak Denak kepikiran Datuk Miri. Ia merasa sangat kasihan kepada Datuk Miri yang jatuh sakit semenjak pulang dari kantor polisi gara-gara berladang padi, dan kabar itu sudah santer terdengar dalam dua minggu terakhir. Sepulang dari kantor polisi yang berakhir damai, Datuk Miri justru jatuh sakit, dan kini dalam sakitnya, ia tak punya sebutir pun padi ladang buat ditumbuk sebagai syarat ritual bedukun.
Sudah berkali-kali terjadi peristiwa peladang berurusan dengan petugas kepolisian di Polsek Rakit Kulim. Hal ini sudah lama menggelisahkan benak Pak Denak.
………………………….
Tahun-tahun menyiksa telah dilalui Pak Denak dengan kabut asap pekat membubung ke udara, hasil pembukaan lahan besar-besaran di tanah ulayat kaumnya. Asap itu menyebar tanpa peduli batas-batas wilayah, tentu saja, menyebabkan langit hitam kelabu berminggu-minggu, menggumpalkan awan pengab yang bergerak di atas kota-kota dan sampai juga ke negara tetangga yang di sana disebut jerebu. Memintas jarak-pandang tinggal hanya dalam hitungan depa dan banyak penerbangan pesawat terpaksa ditunda.
…………………………..
Setelah fase pembakaran lahan besar-besaran itu dianggap selesai, ditandai mulai tumbuh dan mekarnya pelepah-pelepah sawit di hamparan gambut ribuan hektar, bahkan pabrik-pabrik CPO mulai beroperasi yang merekrut para pekerja dari mana-mana—tapi hanya beberapa orang saja masyarakat asli kampungnya yang diterima—tiba-tiba keluar larangan bahwa para peladang dilarang menyalakan api di ladang mereka. Termasuk di ladang padi, di mana api amat dibutuhkan sejak zaman poyangnya.
“Menanggung!” begitulah teriak orang kampung, terutama mereka yang harus tetap bertanam padi.
Lucunya, pengumuman tentang bahaya kebakaran lahan kini banyak dibuat dan dipancangkan di perkebunan milik perusahaan, sebagaimana kami lihat di kawasan Sungai Limau saat kami harus jalan memutar lewat Siberida yang lebih jauh—karena jalan ke Air Molek putus di Batu Mandi. Tentu saja, karena lahan kebun mereka sudah terbuka dan sawit mereka sudah berproduksi. Maka saatnya menjadi pahlawan atas lingkungan dengan cara yang naif seperti memasang papan atau banner himbauan di setiap petak lahan: Dilarang Membakar Lahan. Hal yang notabene sukses mereka lakukan belasan tahun lalu dengan menimbulkan bencana kabut asap berbulan-bulan di atas langit Sumatera, tanpa ada konsekwensi hukum yang jelas bagi para pelakunya.
Kini, setelah hutan ulayat berubah menjadi perkebunan, masyarakat adatlah yang seolah perlu diwaspadai dan diperingatkan. Dan mereka, operator “pendudukan perkebunan sawit” (istilah Li dan Semedi) merasa diri sebagai pahlawan.
Saat itulah kami merasa perlu membentang selembar kain batik bermotif padi ladang di balai desa Talang Sungai Parit untuk menyatakan sikap bahwa padi ladang merupakan sumber pangan masyarakat Talang Mamak. Membakar lahan secara pantas dan benar adalah bagian dari ritual untuk menjaga eksistensi masyarakat adat sekaligus menjaga kedaulatan pangan. Atau, di gerbang perkebunan besar, ingin kami rentang selembar lagi kain batik bermotif tolak bala, dari mana kami menunjukkan bahwa serbuan sawit yang tak terkendali telah menimbulkan gangguan ekologis. Masyarakat adat berhak atas tanah adat dan hutan ulayat yang lestari, tapi suara mereka tak pernah digubris.
Selembar batik dan sehampar padi ladang, terkait erat dengan sandang-pangan masyarakat adat, sebagaimana kami hayati di Talang Sungai Parit yang kini terjepit di antara raksasa sawit. Tapi harapan mereka tergambar begitu kuat dalam motif khas yang digali dan diangkat dari khazanah budaya serta pergulatan hidup mereka sendiri. (Selesai)
Foto: Motif Padi Ladang, karya Nur Wahida Idris.


