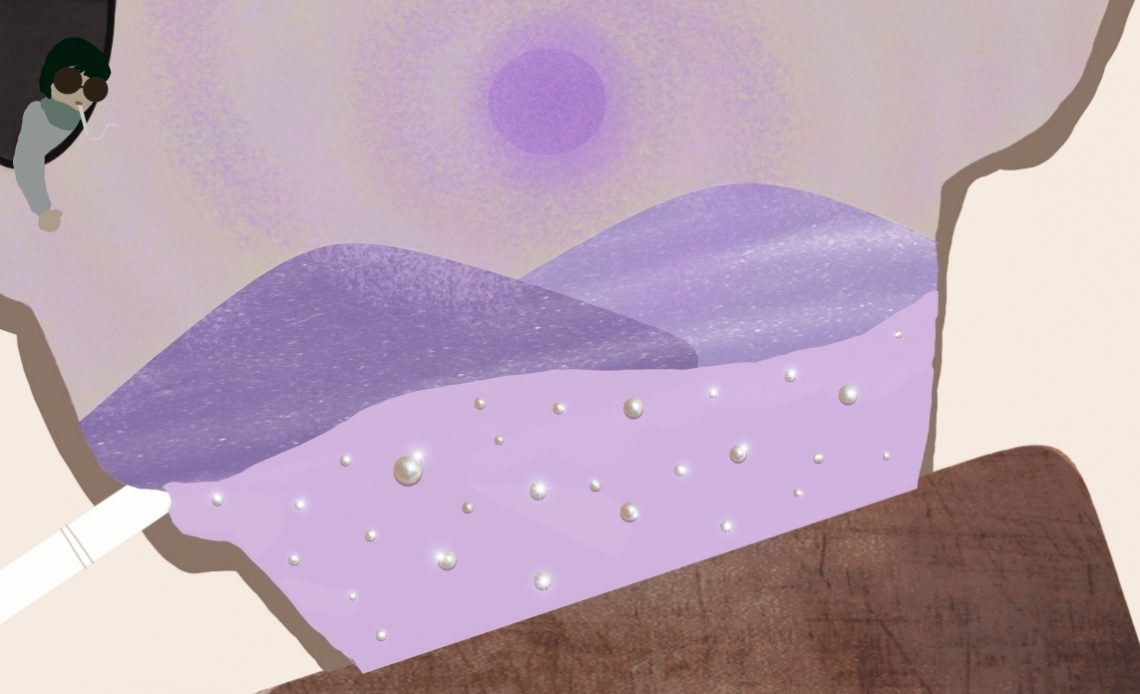
“Bagiku kau istimewa, Bang”.
Seorang gadis apa adanya, menyurukkan senyumnya setelah menuturkan pelan dan jujur kalimat itu. Kepalanya menunduk. Rambutnya yang lurus hitam seketika menjuntai ikut menutupi mata sang gadis dari tatapan orang di hadapannya – laki-laki pensiunan yang masih saja senang menyarungkan seragamnya kemana-mana.
“Kamu jangan begitu, aku tidak enak hati. Aku tidak sempurna, Dek!” Kata si abang dengan tertahan.
Dia menunduk melihat badan diri, merasa canggung atas penilaian si gadis. Laki-laki ini tampan untuk usianya yang sudah tidak muda. Boleh lah – walaupun ada cebang dik keningnya dan bajunya yang sering itu-itu saja. Tapi bagi si gadis, si abang tetap istimewa.
Singkat kata, mereka beranjak, saling menggenggam tangan dan melangkah, mungkin ke KUA.
***
Saya tidak tahu bagaimana mengkategorikan relasi manusia seperti peristiwa naratif di atas. Para sosiolog barangkali – dan semestinya – bisa membantu kita menjelaskan secara teoritis. Tapi sangat gampang menganggap relasi mereka begitulah “manis”. Tak perlu berpanjang-panjang menjelaskan kenapa manis, sebagaimana tidak diperlukan penjelasan kenapa si gadis menganggap istimewa si abang yang cebang itu. Apapun argumen si gadis dan bantahan si abang yang canggung, wajah cebangnya tetap istimewa di mata sang gadis.
“Ah mereka kan sedang jatuh cinta, mereka buta” – kata pujangga sinis. Terus kenapa? Mau penjelasan logis, kita tahu kemana akan bertanya. Namun agaknya apapun itu analisisnya, saya menduga mereka bersepakat kalau memang abang adek ini menggemaskan. Satu relasi yang membuat hati semua yang melihat, membaca, menyaksikannya, menjadi hangat. Positif, kecuali anda cemburu karena satu dan lain hal.
Beda cerita dengan peristiwa naratif kedua berikut.
Seorang laki-laki duduk mengangkat kaki kirinya ke kursi panjang. Sayap celana cutbray-nya yang berbentuk lonceng itu mengibas-ngibas ditiup angin sore. Bulu kakinya tampak lurus panjang. Padahal dia sudah berumur. Apa semua orang orang dewasa punya keriting bulu kaki? Ah siapa yang tau. Sandal jepit kumalnya mestinya perlu dia cuci dulu sebelum dia putuskan melarikannya dari entah surau mana. Mesti jepit, secara keseluruhan kaki kirinya memang tampak jumawa. Cukup lah itu saja, bagian lain badan tak perlulah digadang-gadangkan. Yang jelas ia memang terlihat menggagahkan tampilan.
“Macam ini lah seragam abang dulu, Dek. Cuma sedikit diproduksi pada masanya. Langka ini barang”. Si abang mengakhiri basa basi. Melemparkan senyum ke si gadis, dan angan-angannya pada masa lalu yang gemilang. Lobang hidungnya kembang kempis. Si gadis membalas senyum, sepantasnya, sambil mengusap hidungnya yang tidak gatal.
Terakhir mereka bertemu memang sudah lama, dan pertemuan sore itu menjadi sangat penting dan genting. Bagi si abang, hubungan mereka yang naik turun berbilang masa, ingin direformasi barang sedikit. Maka ditemuinyalah si gadis.
“Abang ini sudah jauh berjalan, Dek, dan juga banyak bersua orang. Dari itulah kemuliaan abang dapatkan. Ke Samarinda abang satu kali, abang bertemu “orang kita” di sana. Pengusaha kaya. Ada juga pengajar, tapi belum punya mobil. Tapi sudah Dotor dia. Hebat sekali orang itu. Dia pernah ke Amerika sekolah, dan ternyata’ dek…menurut kabar, banyak memang orang-orang kita yang tinggal hidup disana. Macam-macam jasanya. Luar biasa”.
Si abang terus bercerita pengalaman jauh berjalannya kian kemari. Batu cincin dari sebuah sungai di lembah yang termasyhurpun diperlihatkan. Ikatnya mengkilap, gilang gemilang. Warisan ibunya turun temurun. Laki-laki itu terus bercerita tentang keagungan diri. Sayap cutbray kali ini dikibas-kibas si abang sendiri. Lagi dan lagi. Si gadis berakhir khusuk pada lamunan sendiri.
Di atas segala pengistimewaan diri itu, disodorkannyalah pinangan. “terimalah suntingan ku dek, tak ada tandingnya aku dihadapan yang lain. Jadikan aku yang teristimewa bagi mu”. Sang gadis mencibir, mencibir dari belakang. Dia mengajak pergi si lelaki. Barangkali ke polisi.
***
Ada satu kesamaan setidaknya dari dua cerita di atas, yaitu tentang keistimewaan. Namun lahir dalam peristiwa yang berbeda. Yang pertama lahir dari satu orang atas orang lain, yang kedua lahir dari seseorang tentang diri sendiri. Yang pertama datang sebagai pujian, yang kedua datang sebagai kesombongan. Yang pertama menggemaskan, yang terakhir – maaf berkata – cukup menjijikkan. Terlepas benar dan salahnya keagungan sang lelaki kedua, sikapnya yang tak pantas tak terbantah.
Tulisan ini tidak bermaksud menyembunyikan pesan di dalam satir. Sebaliknya, sasarannya jelas. Ia menunjuk pada proposal sebagian kecil masyarakat di Sumatera Barat agar bisa dianggap istimewa di tengah pergaulan dengan daerah lain. Sebuah usaha yang akan menggadaikan keegalitarianan yang dipuja puji itu, dengan sebuah laku eksklusif. Kena kita pada etika.
Agar tulisan ini tidak dikatakan sebagai penjaga moral dan etika saja, ada baiknya saya masuk sedikit lebih ke bawah, pada hal-hal yang lebih material. Karena naskah ini (unduh di sini) adalah naskah akademik tentu ia perlu diuji secara akademik. Banyak kebolongan yang bisa diangkat, namun satu hal mendasar saja cukup kiranya, untuk mengatakan naskah akademik ini, tidak akademik, dengan implikasi turunannya, argumentasi akhir yang diusung lemah atas nama metodologi.
Kelemahan itu langsung dengan terang terlihat pada paragraf pertama ringkasan naskah, yang menyebutkan Provinsi DIM adalah aspirasi mayoritas masyarakat Minangkabau, bahkan dengan sedikit tendensi menglorifikasi bahwa ia juga merupakan aspirasi bangsa Indonesia. Klaim ini serius, yang sayangnya tidak ada satupun pembuktian empirik yang dinyatakan dalam naskah, bahwa memang ia aspirasi mayoritas. Dengan begitu, bagi kami seluruh argumentasi yang muncul selanjutnya dalam naskah ini, telah runtuh dengan sendirinya – hingga nanti muncul bentuk pembuktian lain.
Meskipun kemudian naskah ini bukanlah lagi naskah yang lahir dari aspirasi mayoritas, ia tetap bisa diposisikan sebagai aspirasi beberapa kalangan – katakanlah “aspirasi tim kerja penyusun” saja. Dengan begitu ada eloknya juga kita selami, apa benar yang menjadi buah angan dari mereka, dan mengungkap secukupnya kebolongan-kebolongan yang bagi kami penting untuk dicermati ulang.
Landasan yuridis yang dirujuk sebagai pembenar pengajuan keistimewaan adalah adanya amanah konstitusi tentang perlindungan hukum atas masyarakat adat. Disebutkan secara konstitusional menurut ketentuan Pasal 18B UUD NRI 1945: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.
Ada satu kebenaran berfikir dan dua kesalahan bersikap dari pengusung DIM. Tim penyusun benar dalam hal: bahwa konstitusi Indonesia memang mengakui dan menghormati sekaligus melindungi masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan Pasal 18B UUD NRI 1945. Usaha-usaha untuk menerjemahkan konsitusi ini kedalam peraturan teknis perundang-undangan sudah berlangsung lama oleh beragam masyarakat adat di pelosok Nusantara. Namun, adanya pesan konstitusional pengakuan dan penghormatan atas ragam masyarakat hukum adat tidak lantas menjadi alasan untuk sebuah “keistimewaan”. Karena pada akhirnya semua kelompok masyarakat hukum adat, adalah istimewa.
Kesalahan kedua adalah proposal keistimewaan ini seperti keluar dari gerakan bersama masyarakat hukum adat Nusantara atas rintisan perjuangan hak mereka dalam beberapa dasawarsa terakhir. Singkatnya, UUD yang menjadi rujukan tim penyusun DIM adalah pesan konstitusional bagi negara atas seluruh masyarakat hukum adat, bukan perihal pengistimewaan satu diantara yang lain. Lagi-lagi pengusung DIM lalai memperhatikan etika hidup berjuang bersama.
Selain itu naskah akademik ini juga pberbicara tentang tiga hal pokok. Yang pertama adalah klaim tatanan yang ideal; tentang filsafat, sejarah baik, tatanan sosio-kultural yang dibayangkan, tentang tatanan matrilineal yang dibayangkan, tatanan pemerintahan nagari dan pengelolaan properti yang dibayangkan. Semua klaim ini bersifat normatif, abstraksi yang tidak selalu bertemu dengan kondisi faktualnya. Setidaknya dalam dinamika kehidupan masyarakat minang hari ini, ia sungguhlah penuh dengan perdebatan.
Yang kedua kondisi aktual hari ini, yang bercerita tentang kemerosotan sehingga perlu revitalisasi macam-macam. Sayang, datanya pun tidak tampil dengan baik. Yang ketiga mengenai tuntutan pengistimewaan yang didasarkan pada UUD.
Pertanyaannya adalah pengusung DIM ingin menompangkan keistimewaan diri dalam hal apa? Pada klaim filsafat, sejarah dan romantisme tatanan masa lalu? Atau pada kemerosotan-kemerosotan aktual hari ini? Apa yang mau diistimewakan pada satu masyarakat yang secara wacana begitu agung digadang-gadangkan, dalam aktual hari ini “merosot”, bukan siapa-siapa? Mau mengistimewakan ketercerabutan dirikah? Para penyusun naskah akademik nampaknya berfikir lain. Dua hal yang kontradiktif itu disatukan sebagai argumen mengistimewakan diri, yang justru memperlihatkan dengan terang kegalauan eksistensi.
Sebagai sebuah masukan, argumentasi-argumentasi mengenai sejarah masa lalu, filsafat dan norma-norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau secara umum – entah tatanan matrilineal, tata pemerintahan nagari hingga pengelolaan tanah ulayat – baiknya ditempatkan pada posisi sosio-kultural yang terus diperdebatkan dan dinamis mengikuti perkembangan jaman. Perihal point-point yang dianggap penting untuk dipertahankan, diperbaiki dan direvitalisasi tentu sudah menjadi keharusan. Namun mengedepankan “keistimewaan” sebagai sebuah jalan memerlukan penterjemahan turunannya secara material, yang mana pada bagian ini kelemahan utama dari pengaju. Ada baiknya berbagai persoalan internal masyarakat Minangkabau hari ini diidentifikasi dengan lebih jernih pada basis-basis pengusung kebudayaan itu sendiri secara lebih kongkrit, lepas dari label abstrak yang tidak penting. Persoalan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dievaluasi ulang, mengenali kerentanan-kerentanan yang ada dan bersama-sama menghadapi sumber kerentanan tersebut secara politik. (*)



Tidak menjelaskan apa-apa