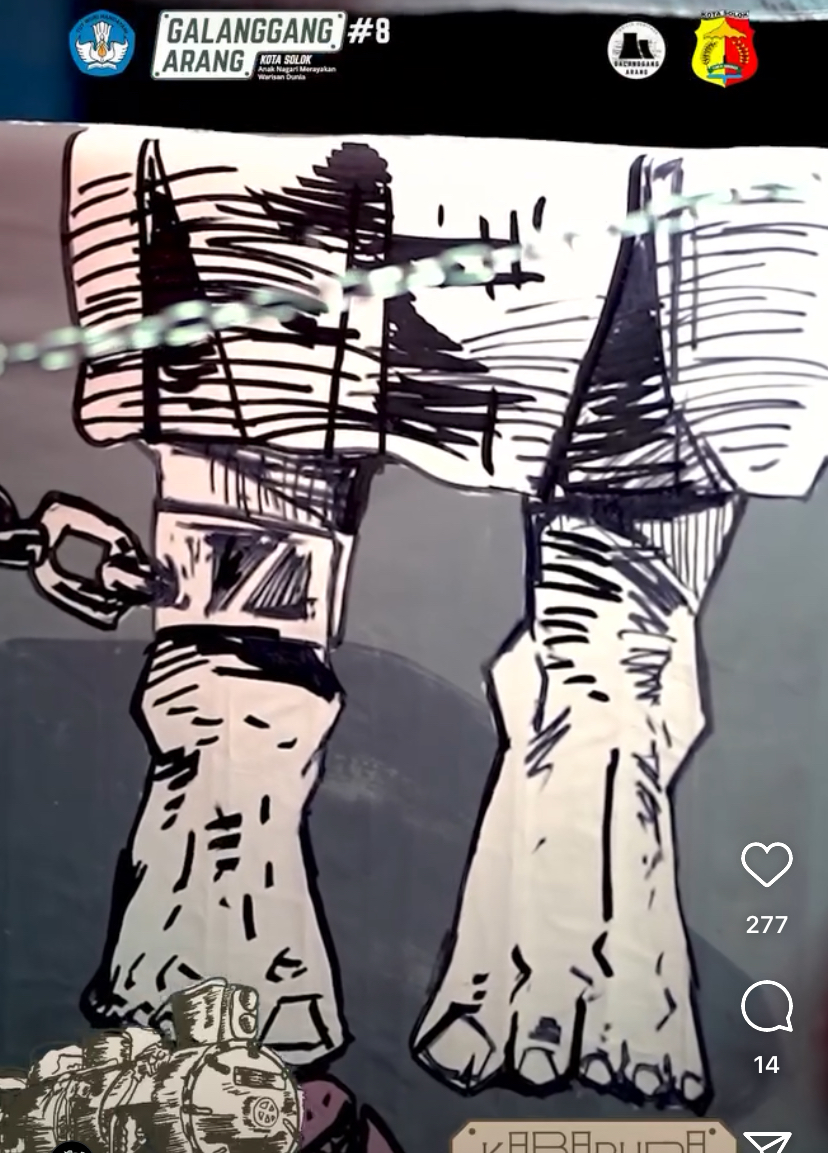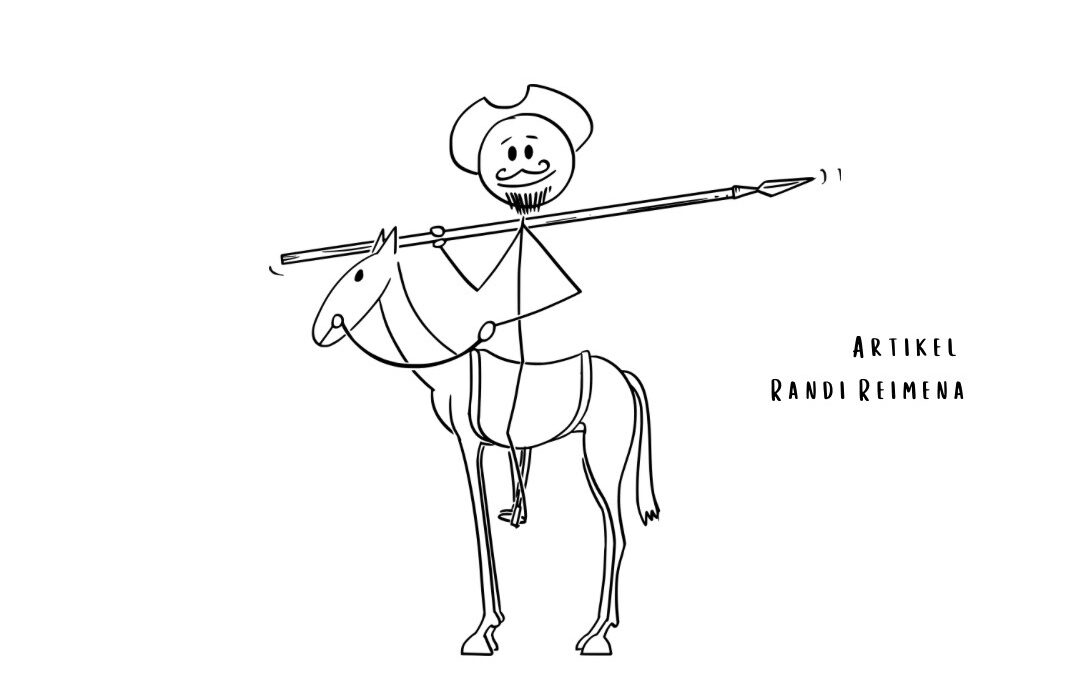
Aturan dasar terpelajar dalam mengkritik adalah paham dulu dengan apa yang mau dikritik. Mengkritik tidak cukup dengan modal heroisme saja. Jadi sebelum membuat tulisan yang konon kritik itu pahami dulu apa itu WTBOS, ya, Jaka HB.
Sebetulnya dengan sedikit riset, sebagaimana kerja jurnalis umumnya, Jaka bisa pahami dengan cepat apa itu WTBOS. Tapi ya begitulah, inflansi heroisme, defisit anu.
Btw, tulisan ini adalah tanggapan atas tulisan Jaka yang membalas tulisan saya sebelumnya. Dan saya menulis ini sambil makan mie dan mendengar lagu NOFX, band punk kesukaan saya: The Idiot Are Taking Over.
Lets, go!
Saya akan bantu jelaskan apa itu WTBOS lebih dulu. Setelah itu baru kita bahas kaitan antara Galanggang Arang, tambang, dan dekolonisasi yang ditanyakan Jaka dalam tulisan terbarunya.
Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto adalah situs-situs bekas fasilitas penambangan, kereta api, dan pelabuhan, yang merentang dari Kota Sawahlunto hingga Pelabuhan Teluk Bayur. Ia terbagi dalam tiga zona. Zona A di beberapa situs di Sawahlunto. Zona B ialah jaringan kereta api dari Ombilin ke Pelabuhan Teluk Bayur. Dan zona C adalah fasilitas penampungan batubara di Teluk Bayur.
Galanggang Arang diadakan sebagai upaya mengaktivasi ekosistem kebudayaan di tiga zona tersebut. Galanggang Arang karena itu tidak hanya terpusat di Sawahlunto. Galanggang Arang juga ada di Solok, Kayutanam, Padangpanjang, dan lainnya.
Tarik nafasnya. Tahan sebentar. Ini penting saya jelaskan biar Jaka tak bingung sendiri kalau mau mengkritik suatu festival kebudayaan.
Setelah itu, dalam Galanggang Arang ada tiga kuratorial. Ada Kuratorial Kaba Rupa, Kuratorial Kaba Buni dan Kuratorial Kaba Baro. Di samping itu, ada namanya kegiatan Jelajah Galanggang.
Setiap kuratorial punya fokus masing-masing. Kuratorial Kaba Rupa fokus ke karya rupa. Kuratorial Kaba Buni ke pertunjukan musik. Dan Kuratorial Kaba Baro ke produksi pengetahuan.
Dalam Galanggang Arang, setiap kuratornya menekankan partisipasi anak nagari di sepanjang WTBOS untuk mempertunjukkan karya-karya seni budaya miliknya. Baik yang berhubungan langsung dengan WTBOS, maupun tidak. Karya itu banyak jenisnya. Mulai dari komposisi musik hingga tarian. Selain itu, juga ada seniman-seniman dari luar nagari yang ikut terlibat.
Sudah pahamkah? Oke lanjut.
Karena tidak hanya terpusat di Sawahlunto, maka tidak di semua kegiatan Galanggang Arang muncul narasi orang rantai.
Ini ada alasannya. Produksi teks mengenai orang rantai sudah sangat banyak. Seperti telah saya tulis sebelumnya, di museum dan bahkan di mural-mural yang disponsori pemerintah, narasi orang rantai begitu kuat. Buku, vidio, bahkan pada bangunan-bangunan di Sawahlunto itu sendiri juga melekat narasi orang rantai. Namun narasi ini terpusat di Sawahlunto.
Sementara itu produksi narasi soal pekerja paksa di sepanjang Zona B sangat sedikit. Hanya beberapa buku yang membahas soal pekerja paksa ini. Bangunan-bangunan di mana pekerja paksa ini tinggal berdempet-dempet juga sudah tidak ada karena hanya berupa bedeng kayu.
Demikian juga dengan Zona C. Teks mengenai pekerja paksa yang membangun pelabuhan dan Silo Gunung penampung batubara, sangat terbatas.
Karena itulah, di luar Zona A, kesenian-kesenian yang dihidupkan oleh anak nagarinya, yang kemudian berpartisipasi dalam Galanggang Arang, cenderung tidak berkaitan langsung dengan sejarah pekerja paksa dan orang rantai.
Meski begitu, seperti yang saya tunjukkan di tulisan sebelumnya, narasi itu bukan berarti tidak ada. Ia tetap ada, dalam buku, di website, dan karya seni rupa di Galanggang Arang.
Sekarang mari masuk ke soal Galanggang Arang.
Setelah menerangkan kenapa tidak mungkin untuk menjadikan narasi orang rantai dalam rangkaian Galanggang Arang sebagai narasi utama seperti yang Jaka harapkan, kini mari kita lihat apa sebetulnya mau si Galanggang Arang ini.
Jadi, kegiatan-kegiatan di Galanggang Arang adalah upaya untuk mengaktivasi dan menguatkan ekosistem budaya WTBOS yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2019 lalu.
Dengan adanya aktivasi berupa festival, pemerintah berharap datangnya wisatawan, dan terbentuknya ruang-ruang ekonomi. Jika berjalan baik dan bisa dipertahankan, maka akan terbentuk ekosistem budaya di mana masing-masing partisinya saling menghidupi. Tapi ini baru suatu ideal, belum sesuatu yang sudah terwujud. Karena itulah ia disebut ‘upaya’.
Mungkin jiwa pahlawan Jaka akan sedikit terkejut mendengar pernyataan berikut ini. Tapi itulah kenyataannya. Galanggang Arang sedari awal memang tidak berhubungan langsung dengan kampanye anti-tambang atau energi kotor. Ia lebih kepada upaya aktivasi bangunan-bangunan bekas penambangan di masa kolonial.
Apakah lantas semua yang terlibat di dalamnya kemudian ikut berdosa karena tidak mempedulikan korban-korban tambang ‘ilegal’ hari ini?
Tidak juga. Karena memang sejak awal kampanye anti-tambang bukanlah domain Galanggang Arang. Galanggang Arang lebih ke cultural heritage, bukan soal bentang alam atau nature heritage. Jadi jangkauannya sangat terbatas, tidak sampai ke soal tambang-tambang ‘ilegal’ dan dampak-dampaknya.
Yang lebih penting, tolong catat baik-baik ya Jak, tambang-tambang ‘ilegal’ yang Jaka sebut di tulisan itu, bukan bagian dari WTBOS.
Tapi jika Jaka ingin mengajak teman-teman seniman dan budayawan untuk terlibat dalam kampanye anti energi kotor itu, saya kira banyak juga yang tertarik untuk ikut. Sekalipun Jaka ingin tampil sebagai malaikat, dengan membuat orang di luar lingkaran Jaka seolah seperti setan, meski Jaka sejak kemarin melihat dirinya lebih unggul secara moral daripada orang-orang yang terlibat di Galanggang Arang, saya akan tetap dukung kampanye itu. Hanya saja, memang tidak bisa dalam Galanggang Arang ini.
Nah, sekarang masuk ke pertanyaan inti. Dari siapa Galanggang Arang merebut WTBOS?
Jawabannya dari kolonialisme. Kolonialisme tidak hanya soal masa lalu, ia juga suatu episteme (sistem berfikir) yang menyusup kepada objek jajahannya bahkan jauh setelah sang kolonialis angkat kaki.
Tapi, di sini kita perlu batasi, bahwa yang dibicarakan di sini adalah WTBOS. Bukan hal di luar itu.
Waktu Belanda berkuasa, hanya merekalah yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang bisa mengelola aktivitas penambangan, perkeretaapian di sepanjang kawasan WTBOS hari ini. Mereka melegitimasi sikapnya itu dengan asumsi rasial: bahwa orang jajahan tidak punya kapasitas untuk mengelolanya.
Setelah WTBOS ditinggalkan oleh Belanda, ia kini bisa dikelola oleh masyarakat/anak nagari sendiri sebagai pemilik sahnya. Lewat Galanggang Arang, kini ia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, potensi pariwisatanya dan budayanya bisa digali dan dikembangkan.
Jika dulu pribumi dianggap tidak punya kapasitas untuk melakukan hal semacam ini karena kolonialisme mencangkokkan perasaan inferior, kini pribumi bisa membuang perasaan inferior itu, lalu menegakkan kepala dan berupaya menghidupkan ekosistem WTBOS dengan tangannya sendiri.
Jika kolonialisme membatas-batasi siapa yang bisa terlibat dalam pengelolaan WTBOS, maka dekolonisasi menginginkan ia bisa dikelola secara inklusif. Pemanfaatannya tidak lagi memandang ras dan etnis.
Itulah dekolonisasi dalam konteks WTBOS. Jika Jaka ingin membahas dekolonisasi dalam konteks lebih luas, bukan di sini gelanggangnya.
Dekolonisasi menekankan keaktoran atau agensi. Anak jajahan yang dulu hanya objek, kini jadi subjek dalam dalam kaitannya dengan WTBOS. Karena mereka subjek, ia kini berdaya untuk memberi bentuk dan makna baru atas WTBOS. Seperti yang saya tulis sebelumnya, hal tersebut tampak dalam keaktoran para keturunan orang rantai di museum-museum pemerintah.
Gedung-gedung yang dulu digunakan untuk mengeksploitasi leluhurnya, kini digunakan sebagai media untuk menyampaikan narasi ketertindasan leluhurnya. Gedung-gedung yang dulu memancarkan makna supperioritas kulit putih, telah dijebol maknanya dan di atasnya dibangun makna baru. Lebih dari itu, mereka juga menggunakan gedung-gedung itu sebagai medium untuk menyebarkan narasi soal kondisi ketertindasan mereka hari ini.
Itulah dekolonisasi. Ia merupakan tantangan terhadap episteme kolonial yang menganggap objek jajahan tak punya kemampuan kognitif yang memadai, bahkan untuk menceritakan sejarahnya sendiri. Persis seperti Jaka yang tidak percaya pada kemampuan para keturunan orang rantai dalam membangun dan menyampaikan sendiri narasi sejarah dan perlawanannya lewat Patung Mandor di Museum Mbah Soero.
“Seharusnya patung itu membuat kalian paham bahwa inferioritas terhadap penjajah masih melekat dalam alam bawah sadar masyarakat” hardik Jaka dalam tulisannya. Aduh terkejut saya.
Asal Jaka tahu, saya sudah mewawancarai para pekerja museum yang ikut mengkurasi isi museum Mbah Soero. Bagi mereka itu bukan bentuk inferioritas. Lebih dari itu, lewat patung itu mereka ingin menyampaikan dua hal sekaligus: nasib leluhurnya, dan nasibnya hari ini yang tak jauh berbeda leluhurnya.
Berlawanan dengan asumsi ‘geladak kapal’ Jaka itu, yang melihat patung itu sebagai indikasi inferioritas, bukti di jalanan di lapangan, malah menunjukkan bahwa patung itu diberi makna dan muatan perlawanan oleh subjek-subjek yang punya daya.
Dengan mendirikan patung itu, mereka ingin membawa narasi perlawanan itu ke tengah gelanggang, ke ruang public (public sphere)
Dekolonisasi memang hidup dari dan di pinggir, dari kalangan marjinal, di kawasan terjajah. Keaktoran mereka dalam sejarah berangkat dari luka kolonial (colonial wound), yang menginginkan suaranya menyeruak ke tengah, didengar, wujudnya diakui, dan menjadi tantangan bagi tatanan lama yang menjajah.
Saya ingatkan lagi ya, mohon simak pelan-pelan ya Jaka. Dekolonisasi di sini dibicarakan dalam konteks WTBOS sebagai colonial heritage, BUKAN DEKOLONIAL DALAM ARTI LUAS.
Jaka bertanya lagi soal narasi orang rantai di Galanggang Arang. Padahal sudah saya jawab di tulisan sebelumnya. Tapi okelah, ada sedikit kemajuan, ada pertanyaan tambahan soal ‘karya seni baru’.
“Apakah Galanggang Arang kemudian memunculkan karya seni baru yang memperlihatkan ‘orang rantai’ melawan dan memutus rantainya? Apakah ada yang merepresentasikan perlawanan orang rantai?” tanya Jaka.
Saya tahu persis Jaka sama sekali tak datang ke Galanggang Arang manapun. Karena itu saya bilang ia menulis dari atas menara benteng—benteng Fort De Kock, misalnya. Tentu saja ia tidak melihat adanya karya seni baru yang memperlihatkan orang rantai di rangkaian Galanggang Arang. Sebenarnya cukup dengan menengok akun IG @kabarupa, pertanyaannya akan terjawab. Tapi bagaimana lagi, pahlawan kita ini nampaknya sudah tak kuasa menahan hasrat untuk tampil sebagai si paling peduli orang rantai.
Oke. Saya bantu lagi jelaskan. Ada beberapa karya seni yang dipamerkan di Kuratorial Kaba Rupa yang memperlihatkan orang rantai. Di Galanggang Arang Solok, misalnya, di dinding gerbong kereta yang sudah tak terpakai, ada mural yang menggambarkan orang rantai dengan tubuh kurus tengah bekerja dengan kepayahan. Ada juga komik yang memperlihatkan dengan jelas kaki berantai orang rantai. Juga ada karya instalasi yang bicara soal sukarnya hidup sebagai penempa rel besi di zaman penjajahan.
Bebarapa karya seni yang menampilkan orang rantai di Galanggang Arang Kota Solok. Sumber foto: @Kabarupa.
Memang karya seni-karya seni itu tidak semegah patung The Worker and Kolkhoz di Moskow, juga bukan pencapaian artistik yang luar biasa sekali, tapi setidaknya para perupa sama sekali bukan orang yang tak peduli atau ingin mengaburkan sejarah orang rantai. Bagaimanapun mereka tak memalingkan muka dari kebenaran sejarah. Mudah-mudahan di tahun kedua atau ketiga nanti ada patung serupa itu di Kuratorial Kabar Rupa.
Setelah menjelaskan panjang lebar soal bagaimana narasi orang rantai hadir di Galanggang Arang, ditambah penjelasan soal karya seni di Kabar Rupa, maka saya katakan tidak ada yang namanya “hanya mengkapitalisir dan mengglorifikasi penderitaan orang rantai.”
Jika Jaka masih bersikeras mengatakan Galanggang Arang itu hanya mengkapitalisir dan mengglorifikasi, saya tak tahu lagi harus menjawab apa. Terserah Jaka lah lagi kalau begitu. Atau jika Jaka sanggup, cobalah terangkan benar konsep ‘kapitalisir’ dan ‘glorifikasi’ yang Jaka maksud. Biar kita enak gelutnya.
Apa yang persisnya dimaksud kapitalisir dan glorifikasi? Sampai batas mana seorang perupa atau suatu festival bisa dikatakan tidak melakukan kapitalisir dan glorifikasi? Apa indikator-indikatornya? (Kalau tidak sanggup tidak apa-apa juga).
Tapi setelah saya baca lagi lambat-lambat dan berulang-ulang tulisan Jaka, saya akhirnya tahu sumber masalahnya.
Jaka secara ajaib, diam-diam menyangka kata ‘Tambang’ dalam WTBOS berarti tambang dalam arti harfiah. Kata ‘Tambang’ itu dianggapnya sama dengan tambang-tambang ‘ilegal’ di sekitar Sawahlunto. Luar biasa, pikir saya. Betul-betul menyala pemikiran abangku Jaka ini. Brilian. Epic.
Dari cocoklogi terselubung itu lah semua sumber kekonyolan Jaka. Berbekal hal lawak itu lah Jaka melempar tuduhan-tuduhan heroiknya. Bahwa “Gelanggang Arang justru merayakan dan melanggengkan kejayaan eksploitasi batubara yang menjadi sumber kedukaan itu.”
Jadi begini. Karena ada kata “Tambang” dalam WTBOS, maka Jaka mengira perayaannya dalam bentuk Galanggang Arang sama dengan perayaan atas tambang-tambang ‘ilegal’ yang hari ini menghancurkan hidup banyak orang.
Padahal kata ‘Tambang’ di WTBOS itu merujuk pada bekas tambang di masa lalu dan segala fasilitas penopang eksploitasi batubaranya. Tidak merujuk pada semua tambang yang hari ini ada di sekitar Sawahlunto atau di tempat lain.
Coba simak baik-baik kutipan dari tulisan Jaka ini:
“Hari ini, apakah WTBOS (Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto) kemudian membuat mental yang tertanam dalam alam bawah sadar kolektif Sawahlunto ini memutus rantai tersebut?”. Di sinilah ia melihat ada ‘Tambang’ dalam WTBOS.
Berangkat dari kekonyolannya itu, ia dengan penuh percaya diri bertanya:
“Sedangkan hari ini apa yang Galanggang Arang atau WTBOS lakukan hari ini?” Lalu masih dengan kadar kepercayaan diri yang tinggi, ia jawab sendiri bahwa “Tambang tetap di atas segalanya” bagi Galanggang Arang.
Di sana tampak upayanya untuk meyakinkan pembaca bahwa WTBOS tetap menempatkan tambang di atas segalanya bahkan di atas kemanusian hanya karena dalam WTBOS ada kata ‘Tambang’. Sekali lagi saya terpana. Wow. Dahsyat.
Jaka yang bijak bestari, adanya kata ‘Tambang’ di WTBOS bukan berarti WTBOS itu meletakkan kemanusian di bawah batubara.
“Tambang tetap jaya baik dalam kondisi belum merdeka dan sudah merdeka hari ini. Apakah dengan kegiatan itu memengaruhi orang-orang Sawahlunto kalau tambang itu buruk?” lanjutnya masih dengan kepercayaan diri yang tinggi.
Di sini Jaka berusaha menekankan bahwa perayaan atas WTBOS akan menghindarkan orang-orang Sawahlunto dari gagasan ‘tambang itu buruk’ karena di WTBOS ada kata ‘Tambang’.
Berbekal cocoklogi itu, Jaka bisa melebarkan persoalan ke soal infeksi paru-paru karena asap PLTU. Ia mencoba menggiring seolah-olah Galanggang Arang turut merayakan keluarnya asap beracun dari cerobong-cerobong problematik itu karena bahan bakarnya berasal dari tambang batubara. Mantap betul, kawan.
Lagipula, WTBOS itu lebih ke benda mati, kawan. Beda dengan Galanggang Arang. Yang menghidupkkan WTBOS, salah satunya, adalah Galanggang Arang. Tapi sudahlah.
Awalnya saya kira semua kekonyolan ini sepenuhnya bersumber dari semacam kesombongan intelektual Jaka yang tidak berniat memahami dulu objek yang mau dikritik. Ya mau bagaimana lagi. Sudah penuh gelasnya mungkin, sempat saya berpikir begini.
Tapi ternyata saya menulis panjang lebar hanya untuk membereskan semacam logical fallacy yang diidap jurnalis bernama Jaka HB. Tapi tak apalah. Itung-itung latihan menulis.
Karena merayakan WTBOS sudah disamakannya dengan merayakan semua tambang di dunia ini dan segala hal jahat yang melekat pada tambang, Jaka melepaskan pukulan pamungkasnya. Bahwa “even Gelanggang Arang justru merayakan dan melanggengkan kejayaan eksploitasi batubara yang menjadi sumber kedukaan itu.”
Aduh Jaka, betapa heroik dirimu. Semua yang terlibat di Galanggang Arang pasti akan segera bertobat setelah semua ini lalu angkat senjata menumpas tambang-tambang.
Tapi, sudahlah, Jak. Kalau penjuluk itu sayup, jangan paksakan menjuluk dahan yang tinggi. Juluk saja yang rendah-rendah dulu.
Sebagai tambahan, kalau balasan Jaka Atas tulisan ini benar-benar layak untuk ditanggapi, maka saya akan tanggapi tujuh hari tujuh malam. Tapi kala balasannya hanya mengulang kesalahan berpikir dan ketidakcukupan pemahaman yang hanya bermodal heroisme, tidak akan saya layani.
Dua tulisan Jaka yang judulnya bombastis tapi isinya hanyalah kumpulan quote itu, saya rasa sudah cukup untuk membuktikan kepada khalayak ramai betapa intelek, progresifnya, dan kritisnya Jaka.
Terima kasih. (*)
***Ada banyak sumber mengenai dekolonisasi. Ada yang membahas dekolonisasi dalam lingkup luas, ada yang membahas dalam konteks dekolonisasi warisan kolonial. Saya memakai beberapa di antaranya sebagai rujukan. 1) “The Logic of Coloniality dan the Limits of Poscoloniality: Colonial Studies, Postcoloniality, dan Decoloniality”. Dan 2) Decolonizing Colonial Heritage: New Agenda and Practices in adn Beyond Europe. Dan 3) Decolonizing European Colonial Heritage in Urban Spaces—An Introduction to the Special Issue.