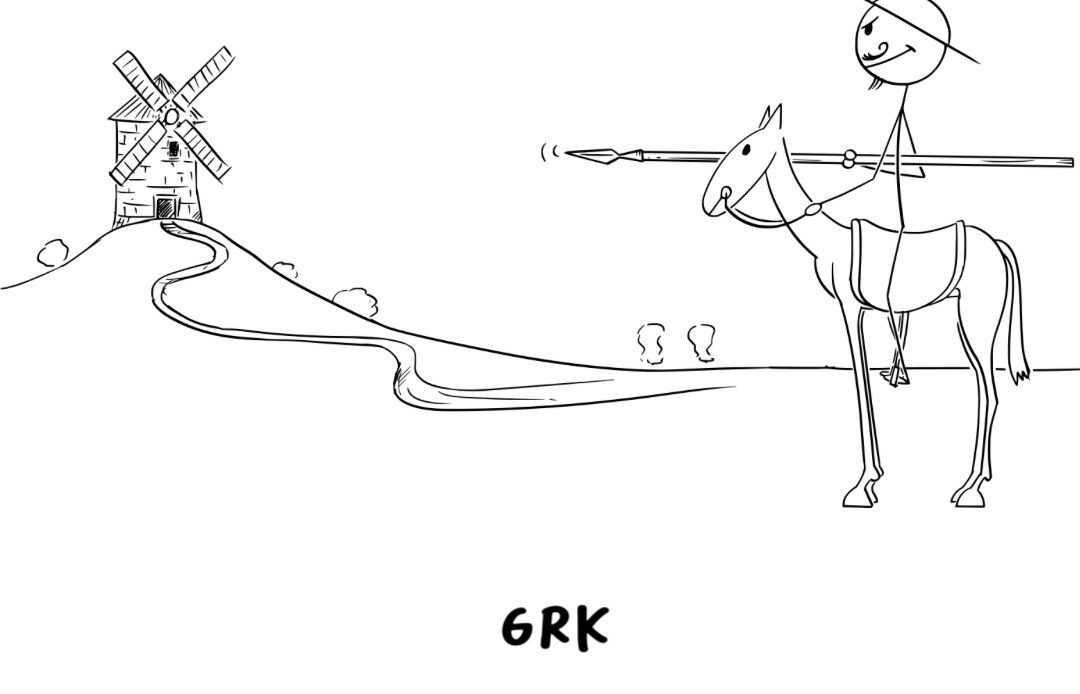
Untuk Jaka HB yang baik, kawan satu kost saya, yang kalau dia batuk malam-malam, kedengaran sekali dari kamar saya.
Tadi Jaka mengirim pesan WA berisi link tulisan berjudul “Gelanggang Arang dan Upaya yang -Hanya- Menceritakan Ulang dan Meromantisir Narasi Sejarah Eksotik”. Tulisannya sangat bagus. Jaka bertanya banyak hal seputar Galanggang Arang.
Baiklah akan saya jawab tulisan di Roehanna Project yang seperti ditulis dari geladak kapal dan dari atas menara benteng itu.
Mari mulai dengan membuat terang apa yang dirayakan di Galanggang Arang.
Dalam tulisan saya yang direspon Jaka, saya telah menulis dengan jelas bahwa “Apa yang dirayakan dalam gelaran Galanggang Arang adalah kebudayaan dalam bentuk kesenian yang hidup dan berkembang di nagari-nagari di sepanjang ekosistem WTBOS.”
Yang dirayakan di Galanggang Arang bukanlah kolonialisme. Saya rasa ini clear, kecuali Jaka punya bukti bahwa yang dirayakan adalah kekejaman kolonialisme atau keberhasilan Belanda menjarah kawasan yang hari ini disebut Indonesia. Mana tahu ada yang mengibarkan bendera Belanda dan menandu foto Ratu Wilhelmina di acara Galanggang Arang.
Karena itu pretensi Jaka HB menyamakan Festival Galanggang Arang dengan perayaan Columbus Day, sebetulnya tidak berdasar.
“Sejarah kelam ini mengingatkan kita pada praktik kolonialisme di banyak tempat, termasuk Indonesia. Salah satu contohnya di Sawahlunto, tepatnya pada Gelanggang Arang”, tulis Jaka.
Sungguh ceroboh menjadikan Galanggang Arang sebagai contoh “sejarah kelam […] praktik kolonialisme di banyak tempat”. Agak membingungkan sebetulnya. Perbandingan itu tidak tepat. Sejarah kolonialisme di Sawahlunto adalah satu hal, Festival Galanggang Arang adalah hal lain lagi. Jaka temanku, hanya karena ada hal yang “mengingatkan kita” tidak otomatis dua barang berbeda menjadi barang yang sama.
Saya baca terus tulisan Jaka dengan penuh semangat. Ia lalu menulis bahwa:
“Perayaan Gelanggang Arang seringkali mengaburkan kompleksitas penderitaan para tahanan dan pekerja paksa di masa kolonial Belanda. Festival ini menampilkan kesenian-kesenian yang dibawa tahanan Belanda dari pelbagai daerah.”
Mungkin karena inilah Jaka berpikir bahwa perayaan Galanggang Arang sama dengan Perayaan Columbus Day. Jaka melihat Galangang Arang seringkali mengaburkan sejarah sebenarnya, yaitu sejarah penderitaan dan pekerja paksa di masa kolonial. Dan saya ikut bertanggungjawab atas perbuatan keji macam itu.
Astaghfirullah. Semangat saya pudur. Saya merasa betul-betul berdosa karena telah ikut mengaburkan sejarah, tidak peduli pada penindasan dan nasib orang rantai, padahal saya lulusan sejarah. Saya tambah terpuruk ketika membaca kutipan Howard Zinn, sejarawan idola saya, soal netralitas di hadapan kebathilan dipakai Jaka untuk membangun framing seolah saya orang super bebal yang pantas dihanyutkan ke Batang Kuranji. Oh, kutuklah saya Om Zinn, yang telah menaiki kereta kolonial ini.
Tapi saya ingat kalau telah menulis banyak hal soal “kompleksitas penderitaan para tahanan dan pekerja paksa di masa kolonial itu” dan hubungannya dengan “kesenian-kesenian yang dibawa tahanan Belanda dari berbagai daerah”.
Untuk Jaka dan Jaka-jaka lainnya ketahui, Galanggang Arang bukan sebatas perayaan dalam bentuk kesenian. Galanggang Arang juga soal produksi pengetahuan. Ada penelitian terkait situs-situs WTBOS dengan berbagai pendekatan. Hasilnya ada satu buku yang membahas mulai dari sejarah buruh, orang rantai, hingga artikel yang membahas soal kemungkinan pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang (Silakan lihat resensinya di sini.).
Di samping itu, ada situs bernama ombilinheritage.id yang jadi semacam ‘pusat’ informasi mengenai WTBOS. Di situs itu, jika Jaka sedang tidak sibuk berjuang untuk kaum tertindas, silakan diubek-ubek isinya. Di sana ada artikel-artikel yang akan menjawab keresahan-keresahan jiwa Jaka dan Jaka-jaka lainnya. Buku dan website ini adalah program dalam Kuratorial Kaba Baro, salah satu kuratorial di Galanggang Arang.
Sekarang kita masuk pada pertanyaan Jaka soal “Mengapa kesenian-kesenian etnik itu ada?”
Untuk menjawabnya silakan kunjungi tulisan saya di ombilinheritage.id. Judulnya “Wayang Sawahlunto: Yang Lahir dari Sejarah Ketimpangan dan Penindasan”. Baca juga tulisan saya lainnya berjudul “Tonel Sawahlunto: Seni Pertunjukan yang mengolok-olok Kolonialisme”. Banyak lagi tulisan serupa. Sila cek sendiri.
Oh, mungkin Jaka terlalu sibuk untuk membaca bahan-bahan yang sudah ada alias riset kecil-kecilan. Sini saya bantu jelaskan kalau begitu. Di sana dijelaskan bahwa kesenian-kesenian itu adalah produk dari sekaligus respon atas ketimpangan dan penindasan. Juga disinggung soal bagaimana kesenian-kesenian itu digunakan oleh kolonial yang dalam bahasa Jaka “‘orang rantai’ yang dipaksa menonton kesenian yang ada agar uang mereka habis dan tidak bisa melarikan diri dari Sawahlunto.” (Huruf ‘S’ besar di kata Sawahlunto, saya yang edit).
Karena itulah penting untuk merawat WTBOS secara fisik. Bangunan-bangunan bekas penambangan dan Kota Sawahlunto itu bukan sekadar benda mati. Mengutip Erwiza Erman, ia bukti visual sejarah manusia yang penuh kekerasan, diskriminasi, dan kontrol super ketat. (Kalau Jaka dan Jaka-jaka lainnya belum baca salah satu disertasi termantap itu, ini linknya).
Sekali lagi, dalam konteks inilah penting untuk merawat bangunan-bangunan itu. Jika ia diruntuhkan, atau dibiarkan hancur, maka bukti visual di mana orang rantai ‘diikat’ dengan hiburan kesenian akan ikut hilang. Dengan kata lain, merawat bangunan-bangunan itu sama artinya dengan merawat latar sejarah kemunculan kesenian-kesenian yang ada di Sawahlunto. Jika bangunan-bangunan itu hilang karena tak dirawat, maka latar sejarahnya, yaitu sejarah penindasan dan penghinaan, akan ikut kehilangan basis materialnya.
Jika basis material itu hilang, maka kesenian-kesenian itu berpotensi menjadi sesuatu yang ‘luhur’, yang tak punya konteks sejarah. Jika begini, maka Jaka pantas untuk bertanya “Apakah perayaan ini benar-benar mengungkap penderitaan para ‘orang rantai’ yang bekerja paksa di tambang-tambang batubara? Ataukah hanya sekadar meromantisasi masa lalu tanpa mengakui ketidakadilan yang mereka alami?”
Kembali ke soal produksi pengetahuan yang jadi bagian dari upaya “mengungkapkan penderitaan para orang rantai di Galanggang Arang”. Selain mempublikasikan tulisan-tulisan dalam bentuk artikel ringan, saya bersama Heru Joni Putra juga melakukan penelitian soal kelas pekerja di Sawahlunto dengan judul “Abu di atas Tunggul: Posisi Kelas Pekerja di Dalam dan Luar Museum” yang dibukukan di buku yang saya singgung di atas.
Artikel di buku itu menjelaskan soal bagaimana kondisi kelas pekerja di Sawahlunto hari ini, dalam hal ini pekerja di tiga museum pemerintah. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan orang rantai. Ternyata mereka melihat dirinya bak abu di atas tunggul. Mereka bekerja di bawah UMR, terlilit utang, tak punya tanah, dan masa tua yang tak pasti. Mereka melihat dirinya tak jauh beda dengan leluhurnya.
Dan mereka menjadikan museum-museum itu sebagai untuk medium menyampaikan narasi tersebut. Museum-museum itu mereka kerahkan untuk menyampaikan narasi mengenai orang rantai, bahkan lengkap dengan nisan, rantai, serta nama-nama orang rantai. Dengan kata lain, mereka melakukan humanisasi atas orang rantai yang telah didehumanisasi secara brutal oleh penjajah. Dengan menyampaikan narasi ini, mereka tidak hanya bicara soal masa lalu, tapi kondisi mereka di hari ini.
Inilah yang saya sebut dekolonisasi. Dulu gedung-gedung museum itu adalah bekas fasilitas yang terkait penambangan yaitu dapur umum, gedung hiburan, serta stasiun. Jika dulu gedung-gedung itu digunakan sebagai alat eksploitasi kini ia digunakan untuk tujuan penghapusan eksploitasi. Tujuannya jelas belum berhasil, tapi setidaknya siapa yang berwenang memanfaatkan gedung-gedung itu dalam konteks penyebaran narasi kini sudah beralih ke tangan keturunan orang rantai sendiri.

Foto ruang utama Museum Mbah Soero. Ini adalah bagian dari buku Pemetaan WTBOS. Empat foto itu adalah orang-orang rantai lengkap dengan nama dan sukunya. Orang rantai, hadir di perayaan Galanggang Arang, salah satunya lewat buku ini.
Selain di museum, selama riset di Sawahlunto, juga ditemukan adanya narasi yang sama di beberapa bentuk kesenian. Salah satu yang mencolok adalah Wayang Sawahlunto. Wayang ini benar-benar menjungkirbalikkan narasi sejarah bikinan kolonial. Pendekatan yang digunakannya juga melampaui para sejarawan umumnya. Lakon itu juga menjawab pertanyaan Jaka soal “Siapa mereka yang menjadi ‘orang rantai’? Bagaimana penggambaran sejarah mereka hari ini?”
Saya kutipkan bagian dari artikel tersebut yang membahas Lakon Samin Soerosentiko itu:
“Lakon ini dibuka dengan prolog mengenai krisis ekonomi di Eropa pada masa-masa akhir abad ke-19. Untuk menyelamatkan diri dari krisis, kerajaan Belanda semakin meningkatkan eksploitasi di koloninya, Hindia Belanda, salah satunya dengan menerapkan sistem tanam paksa. Kebijakan tersebut, dan kolonialisme itu sendiri, telah memicu krisis sosial dan ketimpangan di Hindia Belanda terutama pulau Jawa. Kriminalitas merebak karena sistem yang rusak, orang-orang mulai protes dan membangkang. Merekalah yang ditangkap, dijadikan narapidana, lalu dikirim ke lubang-lubang penambangan di Sumatera Barat sebagai orang rantai—tenaga kerja dalam jumlah besar yang dibutuhkan sebagai bagian dari upaya Belanda menyelamatkan negerinya dari krisis: proyek pembangunan industri batubara.
Samin Surosentiko, seorang pemimpin spiritual dari Blora adalah salah satu orang rantai, korban dari sistem yang rusak tersebut. Ia awalnya ditangkap karena tidak mau membayar pajak dan mengikuti sistem tanam paksa. Di penjara ia memiliki banyak pengikut. Belanda membujuk mereka agar mau dikirim ke Sawahlunto demi hidup yang lebih baik, tidak hanya untuk para tahanan tapi juga pribumi umumnya. Belanda menjanjikan mereka kebebasan, gaji, dan pekerjaan. Samin yang mengira misi itu adalah demi ‘kepentingan rakyat’ nusantara, ‘kepentingan bangsa dan negara’, menyetujui untuk pergi ke Sawahlunto, untuk sementara menaati perintah Belanda, dengan catatan akan bertempur sampai mati jika ternyata dibohongi.
Di Sawahlunto, pengikut Samin semakin banyak dan beragam secara etnis. Mulai dari Jawa, Batak, bahkan Tionghoa. Samin dan pengikutnya yang tahu telah ditipu, melarikan diri. Mereka dikejar. Samin berubah wujud menjadi harimau, mengalahkan pasukan pengejar, lalu moksa, lesap entah kemana. Cerita lakon itu berakhir di sini.”
Dari kutipan tersebut tampak bahwa para seniman di Sawahlunto tidak hanya menceritakan soal mengapa mereka jadi orang rantai dan siapa yang dilawan oleh mereka, mereka ingin merehabilitasi orang rantai.
Dan upaya rehabilitasi ini telah mereka mulai sejak tahun 1970-an, jauh sebelum Jaka dan Jaka-jaka lainnya berhasil menemukan bahwa saya sama sekali tidak peduli dengan sejarah ketidakadilan.
Selain di buku, dan website, sebetulnya teman-teman perupa yang terlibat di Galanggang Arang juga bekerja keras untuk merancang karya rupa yang bercerita tentang penindasan orang rantai. Jika saja Jaka sempat datang ke festival tahun lalu, maka bisa dilihat beberapa karya macam ini.
Memori-memori seperti itulah salah satunya yang ingin dirawat dan dirayakan di Galanggang Arang.
Sekali lagi, itulah yang saya maksud dekolonisasi. Jika belum jelas saya perjelas lagi. Dekolonisasi di sini bukan berarti harus mempertahankan warisan memori yang sudah ada begitu saja, melainkan menghancurkan yang lama dan memberi pemaknaan baru atas situs tersebut.
Lalu Jaka bertanya lagi “Apakah itu berarti kita harus mempertahankan warisan memori yang sudah ada begitu saja, seperti patung-patung orang Belanda yang memandori orang-orang rantai?”
Setahu saya hanya ada satu patung mandor Belanda di Museum Mbah Soero. Ada dua patung lainnya, tapi itu patung separuh badan Ijzerman, sang kepala tambang, di Sawahlunto. Satu di museum tambang milik perusahaan, satu lagi di halaman depan Museum Stasiun Kereta Api. Tapi sudahlah.
Apakah patung itu mewariskan memori yang sudah ada? Betul, patung itu dibuat pada 2007 oleh Dwi Sandra perupa asal Sawahlunto. Patung seorang mandor berwajah bengis yang tengah mengawasi dua orang rantai mendorong gerobak batubara itu adalah hasil kurasi para pekerja museum Mbah Soero dan para kurator resmi dari pemerintah yang juga bersimpati pada orang rantai. Patung itu adalah bagian dari upaya mereka untuk menyampaikan memori soal penindasan di masa lalu sekaligus bisa dilihat sebagai simbolisasi atas nasib keturunan orang rantai hari ini.
Jika Jaka berpikir bahwa patung itu didirikan untuk merayakan kolonialisme, dan menganggap remeh kemampuan para keturunan orang rantai untuk menarasikan sendiri sejarahnya, lalu memilih medium yang tepat untuk itu, saya tak tahu harus omong apa. Mungkin benar saya terjun saja ke Batang Kuranji.
Jaka juga bertanya soal “dampak positif untuk siapa?” Ia lalu menulis seolah saya membenarkan dampak positif kolonialisme. Jaka, saya ingin bercarut pungkang kepadamu. Tapi nanti saja di kostan. Wkwkwk.
Wahai Jaka, mana tulisan saya yang mengarah ke framingmu ini: “Gelanggang Arang juga menyoroti sisi positif dari perkembangan infrastruktur yang menghubungkan Kota Padang ke pedalaman, termasuk pelabuhan Emmahaven yang kini bernama Teluk Bayur sebagai kota bandar terpenting, serta berbagai dampak positif lainnya untuk mobilisasi”. Mana?
Saya hanya menulis soal dampak positif adanya Galanggang Arang di hari ini buat masyarakat di sekitar Kawasan WTBOS, bukan dampak positif infrastruktur kolonial di masa lalu. Ini saya kutipkan lengkap:
“WTBOS sebagai colonial heritage sudah sepantasnya direbut (reclaim), diberi makna baru, kembali menjadi milik masyarakat/anak Nagari, dan memberi dampak positif dalam berbagai bentuk. Mulai dari ekonomi hingga pemanfaatan dan pengelolaan WTBOS secara lebih inklusif.”
Yang saya tulis memanglah pembayangan ideal saya atas Galanggang Arang, ia jelas belum terwujud 100%. Jaka benar, ini bukan pekerjaan main-main dan mudah. Apalagi dalam konteks pekerja museum-museum di Sawahlunto dan keturunan orang rantai umumnya. Yang bisa dilakukan adalah membantu terwujudnya kondisi ideal tersebut. Jika Jaka tidak sibuk, lagi-lagi, bolehlah bantu-bantu mengorganisir kelas pekerja di Sawahlunto itu karena salah satu temuan saya adalah absennya kesadaran kelas di antara kelas pekerja di sana.
Tapi ada satu lagi artikel saya yang mungkin lebih tepat untuk menjawab pertanyaan Jaka. Judulnya “Jalur Kereta Api, Tambang Ombilin, dan Perayaan-Perayaan.” Selamat membaca, kalau mau. Kalau jadi dibaca, maka Jaka bisa bertura-tura pada orang-orang dalam tulisan itu karena perayaan-perayaan di situ sungguh cocok dengan Perayaan Columbus Day.
Sudah dulu ya, saya lelah dengan permainan ‘siapa paling pahlawan’ ini. (*)


